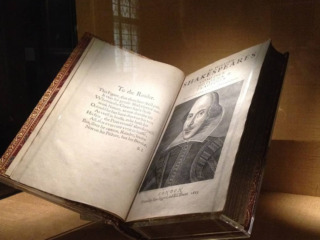Jalan Buntu Transportasi di Ibu Kota Banten
 Zahra Ghazala Wasahda, Mahasiswa Semester 1 Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (Foto: Dok. Pribadi)
Zahra Ghazala Wasahda, Mahasiswa Semester 1 Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD — Transportasi adalah denyut nadi kehidupan kota. Ia bukan sekadar soal jalan dan kendaraan, melainkan menyangkut bagaimana masyarakat bekerja, belajar, berinteraksi, hingga menikmati kehidupan sehari-hari. Di Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, persoalan transportasi telah lama menjadi keluhan utama warga.
Macet di jam berangkat dan pulang kerja, antrean kendaraan yang tak kunjung bergerak, hingga perbaikan jalan yang terasa “salah waktu” menjadi pemandangan akrab. Ironisnya, kota yang semestinya menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat justru terjebak dalam masalah transportasi yang seolah tak berujung.
Akar Masalah: Pertumbuhan Kendaraan vs Infrastruktur Terbatas
Masalah ini tentu tidak muncul tiba-tiba. Pertumbuhan penduduk yang pesat diikuti lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi menjadi faktor utama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kendaraan bermotor di Banten terus naik tiap tahun, bahkan menembus 6 juta unit pada 2024.
Di Serang, jalan kota yang relatif sempit harus menampung arus kendaraan yang kian padat. Pilihan masyarakat untuk lebih mengandalkan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum makin memperparah keadaan. Transportasi umum dianggap kurang nyaman, rutenya terbatas, dan tidak terintegrasi. Akibatnya, beban jalan utama semakin tak terkendali.
Keterbatasan infrastruktur jalan memperburuk situasi. Ruas-ruas jalan di pusat kota masih minim pelebaran, sementara perbaikan kerap dilakukan di siang hari ketika lalu lintas padat. Sistem pengaturan lalu lintas pun masih manual, dengan lampu merah yang kaku dan tidak menyesuaikan kondisi lapangan. Teknologi modern seperti traffic light adaptif atau pemantauan berbasis CCTV belum dimanfaatkan secara optimal.
Semua faktor itu bertemu dalam satu simpul: kemacetan yang menjadi rutinitas harian.
Dampak: Ekonomi, Sosial, hingga Lingkungan
Masalah transportasi ini menimbulkan dampak luas. Dari sisi ekonomi, kemacetan berarti waktu dan energi terbuang. Pekerja terlambat masuk kantor, pelajar kehilangan jam belajar, pedagang terlambat mengantarkan dagangan. Ongkos bahan bakar dan logistik meningkat, produktivitas menurun, dan pada akhirnya menggerus pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari sisi sosial, kemacetan menimbulkan frustrasi dan stres. Warga yang seharian bekerja harus menghadapi jalanan penuh kendaraan, polusi udara, dan suara klakson bersahutan. Interaksi sosial pun terganggu; masyarakat enggan keluar rumah jika harus menghadapi macet. Tak jarang, kemacetan juga memicu pelanggaran lalu lintas—dari melawan arus hingga menerobos lampu merah—yang justru memperbesar risiko kecelakaan.
Dari sisi lingkungan, akumulasi kendaraan menghasilkan emisi gas buang yang menurunkan kualitas udara. Polusi suara meningkat, sementara risiko kesehatan masyarakat—mulai dari penyakit pernapasan hingga stres kronis—kian membayang.
Dengan kata lain, masalah transportasi di Serang bukan sekadar soal jalan macet, melainkan soal kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup.
Belajar dari Kota Lain
Jika dibandingkan dengan kota lain, Serang masih tertinggal dalam pengelolaan transportasi. Jakarta misalnya, meski juga macet, sudah mencoba menerapkan sistem ganjil-genap dan menghadirkan moda transportasi massal seperti MRT dan TransJakarta. Bandung mulai mengembangkan bus ramah lingkungan dan menata angkutan kota.
Serang bisa belajar dari langkah-langkah ini, tentu dengan skala yang lebih kecil dan sesuai kebutuhan lokal.
Jalan Keluar: Dari Solusi Praktis hingga Reformasi Jangka Panjang
Melihat kompleksitas masalah, solusi harus ditempuh secara komprehensif. Beberapa langkah mendesak yang bisa dilakukan pemerintah antara lain:
- Manajemen lalu lintas yang cerdas – perbaikan jalan sebaiknya dilakukan pada malam hari; lampu lalu lintas diganti dengan sistem adaptif yang bisa membaca volume kendaraan.
- Revitalisasi transportasi umum – perbanyak armada, perbaiki kualitas layanan, perluas rute, dan integrasikan antarmoda. Transportasi umum yang nyaman, aman, dan tepat waktu akan mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi.
- Pengendalian kendaraan pribadi – sistem ganjil-genap, tarif parkir tinggi di pusat kota, hingga jalur khusus bus bisa menjadi opsi untuk mengurangi beban lalu lintas.
- Pembangunan infrastruktur baru – pelebaran jalan, pembangunan flyover dan underpass, serta jalur alternatif menuju pusat kota. Infrastruktur ini bukan sekadar menambah kapasitas, tetapi juga menyebarkan arus kendaraan.
- Partisipasi masyarakat – edukasi pentingnya menggunakan transportasi umum, berbagi kendaraan (carpooling), hingga menggunakan sepeda untuk jarak dekat. Tanpa kesadaran kolektif, semua kebijakan pemerintah hanya akan menjadi tambal sulam.
Penutup: Dari Jalan Buntu ke Jalan Keluar
Jalan buntu transportasi di Serang sejatinya adalah cermin dari tata kelola kota yang masih perlu banyak dibenahi. Masalah ini bukan hanya tentang keterlambatan di jalan, tetapi juga soal masa depan pembangunan kota.
Jika dibiarkan, kemacetan akan menjadi penghalang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. Namun, jika ditangani dengan serius dan konsisten, Serang justru bisa menjadi contoh bagaimana sebuah kota menata transportasi demi masa depan yang lebih baik.
Kota yang bebas macet memang terdengar seperti utopia. Tetapi, utopia bisa diwujudkan dengan langkah nyata yang berani. Kota Serang layak mendapatkan mobilitas yang lebih baik—bukan sekadar demi kelancaran lalu lintas, melainkan demi kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
Penulis: Zahra Ghazala Wasahda, Mahasiswa Semester 1 Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)