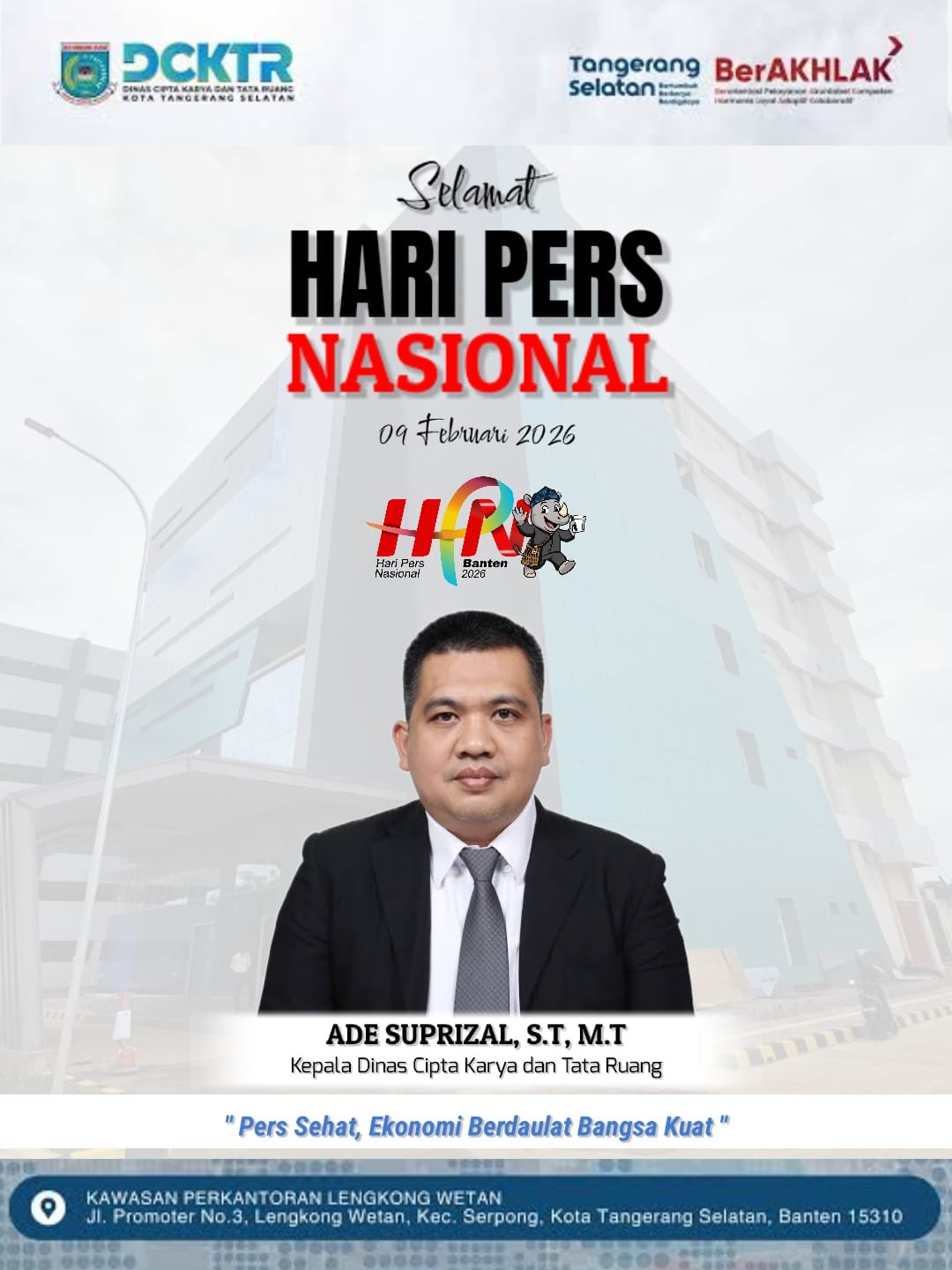Sistem Demokrasi Indonesia: Antara Ruang Harapan & Bayang-Bayang Tantangan
 Ilustrasi untuk sistem demokrasi Indonesia. (Foto: Freepik)
Ilustrasi untuk sistem demokrasi Indonesia. (Foto: Freepik)OPINI | TD – Pada masa Orde Baru, praktik dalam sistem demokrasi Indonesia masih berjalan dalam sistem yang sangat terbatas. Pemilu memang diselenggarakan secara rutin tetapi partisipasi politik rakyat dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Partai-partai dibatasi secara politis, dan kebijakan publik lebih cenderung terpusat pada elit penguasa.
Sistem demokrasi Indonesia pada masa itu hanyalah sebatas prosedural administratif. Dan, belum menyentuh substansi kedaulatan rakyat secara utuh. Barulah setelah reformasi yang dimulai pasca krisis ekonomi 1997, Negara Indonesia mulai memasuki babak baru dalam penerapan demokrasi yang lebih baik. Yaitu dengan kebebasan berpolitik, pemilu yang kompetitif, kebebasan pers, serta kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dalam ruang politik yang lebih terbuka.
Catatan Awal Penulis
Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai kritik tajam terhadap sistem Pemerintah Indonesia. Penulis hanya berusaha untuk menyajikan pandangan obyektif berdasarkan fakta dan realita yang berkembang di lapangan. Tujuannya adalah untuk menghadirkan gambaran yang jujur dan apa adanya, sekaligus sebagai bahan renungan bersama untuk melihat wajah demokrasi Indonesia pada saat ini secara lebih bijaksana.
Demokrasi : Jalan Panjang Yang Sedang Kita Lalui
Sejak era reformasi, Pemerintah Indonesia telah memilih asas demokrasi sebagai dasar ideologi bernegara. Sistem ini cukup membawa banyak harapan namun juga tidak luput dari tantangan yang mengiringinya. Demokrasi membuka pintu partisipasi aktif secara terbuka serta kebebasan dalam beraspirasi, namun dalam perjalanannya juga menghadirkan gelombang persoalan yang kerapkali sulit untuk dipecahkan atau mendapatkan solusi terbaik.
Berikut ini 7 poin refleksi penting yang mewarnai wajah demokrasi Indonesia pada saat ini :
1️⃣ Kesempatan Yang Terbuka Bagi Seluruh Warga Negara Indonesia
Demokrasi memberikan ruang kesetaraan formal tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki kebebasan dan hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin tanpa memandang suku, agama serta latar belakang ekonomi atau pendidikan. Siapapun boleh maju untuk pemilihan kepala desa, wali kota, gubernur, presiden dan anggota DPR (legislatif). Tidak ada garis keturunan kekuasaan yang diwariskan secara otomatis seperti pada sistem politik monarki atau dinasti. Setidaknya secara konstitusional semuanya memiliki hak dan kesempatan yang sama.
Hal ini memberikan ruang mobilitas politik yang sangat luas dalam struktur sosial bermasyakat. Seorang guru, pekerja profesional, pengusaha, dosen, akademisi, atau aktivis, secara prinsip bisa bersaing di panggung politik baik regional maupun nasional. Tidak ada pembagian kasta sosial yang membatasi akses untuk menuju kekuasaan yang menjadi landasan utama bagi prinsip demokrasi yaitu pintu yang bersifat terbuka bagi siapa saja.
2️⃣ Sirkulasi Kekuasaan Yang Terjaga
Dalam sistem demokrasi Indonesia, kekuasaan tidak bersifat seumur hidup. Contohnya pada pemilihan umum Presiden, maka rakyat “dipanggil” pada setiap 5 tahun sekali untuk menentukan siapa yang layak memimpin pada periode berikutnya. Jika seorang pemimpin tidak memenuhi harapan ketika menjabat maka rakyat memiliki hak untuk menggantinya melalui pemilu selanjutnya. Mekanisme ini akan bisa menjaga sirkulasi kekuasaan berjalan dengan tertib dan aman.
Proses ini mencegah lahirnya penguasa absolut, monarki dan tirani. Dengan adanya pembatasan masa jabatan maka demokrasi senantiasa menjaga kesegaran rotasi kepemimpinan dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan jangka panjang serta memberi ruang regenerasi pemimpin dengan ide-ide baru sesuai dengan kebutuhan zaman.
3️⃣ Aspirasi Rakyat Lebih Tersalurkan
Masyarakat kini memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan ide, pendapat, kritik, maupun tuntutan. Media massa, media sosial, forum publik, hingga aksi demonstrasi yang secara terbuka menjadi saluran partisipasi rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan.
Jika di masa lalu khususnya pada masa orde baru kritik dari rakyat dan media kepada pemerintah sering dibungkam, maka kini suara publik sudah secara umum menjadi bagian penting dalam memberikan aspirasi serta koreksi sosial-politik. Bahkan media sosial bisa menjadi alat kontrol kekuasaan yang cepat dan masif, di mana suara rakyat (netizen) dapat viral dalam hitungan jam, menciptakan tekanan publik terhadap pengambil keputusan.
4️⃣ Biaya Politik Yang Melangit
Namun di balik ruang kebebasan itu ada persoalan besar yang sedang mengintai yaitu biaya politik yang sangat mahal. Mulai dari pendanaan kampanye, penggalangan dukungan hingga penyediaan logistik pemilu memerlukan dana yang sangat besar. Akibatnya banyak calon yang terpaksa bergantung pada sponsor politik, pengusaha atau bahkan oligarki.
Praktik politik dengan biaya super mahal ini memicu kesenjangan kesempatan dalam dunia politik. Kandidat tanpa akses modal yang kuat kerapkali tersingkir di tahap awal sehingga membuat demokrasi perlahan menjadi ajang eksklusif bagi mereka yang bermodal besar.
5️⃣ Politik Uang dan Transaksionalisme
Politik uang (money politic) kerap kali muncul sebagai pintu transaksional yang paling kasat mata, terutama di tingkat akar rumput seperti pemilihan kepala desa (kades). Uang digunakan bukan hanya untuk keperluan logistik kampanye tetapi juga untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Praktik ini bisa menggeser nilai sakral demokrasi dari kontestasi gagasan menjadi arena transaksi pragmatis.
Jika hak suara pemilih bisa dibeli seperti komoditas dan bukan lagi ekspresi nurani maka relasi antara pemilih dan kandidat pun menjadi bergeser bukan pada gagasan pembangunan, tetapi pada kalkulasi keuntungan jangka pendek. Ketika uang yang berbicara maka idealisme demokrasi pelan-pelan akan menjadi terkikis.
6️⃣ Kekuasaan Sebagai Ladang “Balas Dendam”
Setelah berhasil merebut jabatan maka sebagian pejabat akan menghadapi tekanan psikologis untuk mengembalikan “investasi politik” yang telah dikeluarkannya. Dalam situasi ini mereka mulai berusaha mencari berbagai celah korupsi, kolusi dan nepotisme, bukan sekadar untuk pengembalian modal, tetapi juga untuk menumpuk kekayaan pribadi dengan cara yang melanggar ketentuan hukum. Akhirnya jabatan publik tidak lagi menjadi ruang pengabdian, melainkan berubah menjadi ladang pengembalian modal dan akumulasi kekayaan.
Dari sinilah asal muara berbagai skandal korupsi bermunculan, mulai dari tingkat akar rumput hingga tingkat elit politik. Hal ini bukan semata karena faktor moral pribadi pejabat, tetapi karena desain sistem yang mendorong mereka masuk ke dalam pusaran praktik politik transaksional.
7️⃣ Dominasi Oligarki Politik
Demokrasi idealnya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun realitas politik saat ini kian memperlihatkan dominasi elite yang menguasai modal, partai, media, dan jaringan kekuasaan. Oligarki mengatur siapa saja yang boleh masuk gelanggang politik dan siapa yang mesti dikunci sejak awal sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat.
Bahkan untuk kasus yang lebih ironis adalah publik tetap diundang untuk memilih, namun siapa nanti yang akan terpilih sesungguhnya telah ditentukan sebelumnya oleh kekuatan modal di balik layar. Akibatnya demokrasi perlahan bergeser menjadi panggung terbatas yang hanya bisa diisi oleh nama-nama yang didukung oleh elite finansial dan kekuatan politik tertentu.
Refleksi Akhir
Sistem demokrasi Indonesia sejatinya menyimpan potensi besar sebagai alat partisipasi rakyat. Namun kekuatannya sangat ditentukan oleh bagaimana sistem ini dijalankan. Bahaya utama demokrasi bukanlah dari luar, tetapi dari internal yaitu hilangnya amanah dan pengabdian serta rusaknya integritas kekuasaan.
Perbaikan sistem demokrasi Indonesia tidak cukup pada prosedur teknis pemilu. Ia memerlukan pendidikan politik masyarakat, pembiayaan politik yang transparan dan wajar, serta lahirnya pemimpin yang berjiwa amanah yang mengembalikan makna kekuasaan sebagai ladang pengabdian dan bukan sebagai instrumen transaksi terselubung yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.
Penulis: Sugeng Prasetyo
Editor: Patricia