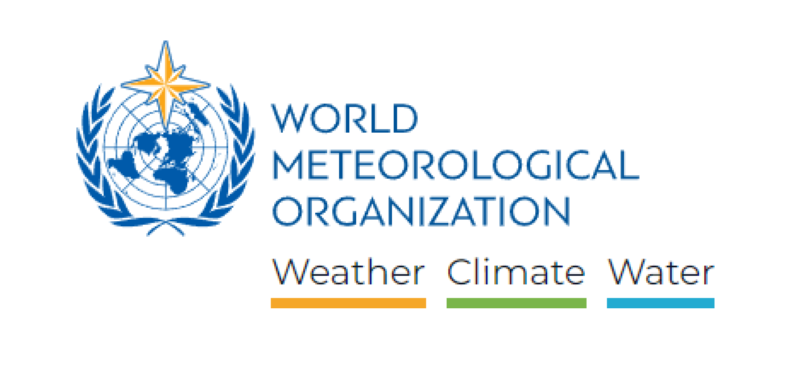Politik 2025: Antara Harapan dan Kekhawatiran
 Ilustrasi: Aksi mahasiswa di Jakarta, 2025 (Foto: David Wadie Fisher-Freberg / Wikimedia Commons)
Ilustrasi: Aksi mahasiswa di Jakarta, 2025 (Foto: David Wadie Fisher-Freberg / Wikimedia Commons)OPINI | TD – Tahun politik baru resmi dimulai. Setelah gegap gempita Pemilu 2024 dengan segala drama, intrik, dan ketegangan, kini perhatian publik tertuju pada wajah pemerintahan baru.
Pertanyaan pun bergema di benak banyak orang: Apakah 2025 akan menjadi awal era perubahan nyata? Atau justru hanya mengulang drama lama—penuh janji manis, sarat intrik politik, tetapi minim aksi nyata?
Politik di Indonesia memang selalu menarik. Ia bukan sekadar tontonan di layar kaca atau trending topic di media sosial. Politik hadir di obrolan warung kopi, ruang kelas mahasiswa, hingga ruang keluarga saat harga kebutuhan pokok melonjak. Maka, setiap kali rezim baru lahir, masyarakat ikut berdebar. Ada yang optimis, ada yang sinis, dan ada pula yang memilih cuek dengan alasan: “Ah, ujung-ujungnya sama saja.”
Harapan Baru Pasca Pemilu
Meski demikian, awal 2025 tetap membawa angin optimisme. Publik berharap pemerintahan baru berani membuat gebrakan, bukan sekadar kosmetik politik, tetapi langkah konkret yang benar-benar terasa manfaatnya bagi rakyat.
Peta kekuasaan pasca Pemilu 2024 berubah cukup signifikan. Koalisi yang terbentuk dinilai bisa membawa stabilitas politik. Stabilitas inilah yang ditunggu, sebab ia dapat menjadi fondasi untuk reformasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.
Masyarakat sudah jenuh dengan janji kampanye yang mudah menguap. Mereka ingin bukti nyata, bukan sekadar “politik kata-kata.” Politik seharusnya menyentuh kebutuhan rakyat sehari-hari, bukan hanya menghiasi panggung debat.
Generasi muda juga hadir dengan semangat baru. Mereka mendorong isu-isu relevan dengan masa depan: transisi energi, keberlanjutan lingkungan, digitalisasi, hingga inklusi sosial. Politik kini lebih cair, muncul lewat thread Twitter (X), podcast, hingga konten TikTok—membuat isu-isu publik lebih mudah diakses dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Kekhawatiran yang Masih Membayangi
Namun, di balik optimisme, ada rasa waswas. Politik Indonesia masih dihantui oleh penyakit lama: polarisasi dan politik transaksional.
Polarisasi Pemilu 2024 memang mereda setelah hasil resmi diumumkan, tetapi luka sosialnya belum benar-benar sembuh. Media sosial masih penuh debat panas, bahkan menjurus pada ujaran kebencian. Di lapangan, masyarakat masih terbelah dalam kelompok-kelompok yang saling curiga. Jika tidak dikelola, kondisi ini bisa menggerogoti persatuan nasional.
Politik transaksional juga tetap jadi momok. Koalisi besar pasca pemilu memang menjanjikan stabilitas, tetapi berisiko melahirkan kompromi berlebihan. Demi menjaga kursi kekuasaan, visi jangka panjang bisa dikorbankan. Alih-alih fokus membangun bangsa, elite justru sibuk berbagi jatah.
Masalah ekonomi pun menambah daftar kekhawatiran. APBN 2026 akan menjadi “tes awal.” Apakah kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada rakyat? Atau justru semakin memperlebar kesenjangan sosial? Pertanyaan rakyat sederhana: “Kami sudah bayar pajak, kami sudah patuh aturan. Tapi apa imbalannya? Apakah uang itu kembali untuk kesejahteraan kami, atau menguap entah ke mana?”
Politik Butuh Kedewasaan
Di tengah tarik-menarik antara harapan dan kekhawatiran, yang paling dibutuhkan Indonesia sebenarnya sederhana: kedewasaan politik.
Elite politik harus ingat, jabatan bukan sekadar simbol atau kursi empuk, melainkan amanah besar. Jika elite sibuk bertengkar atau hanya memikirkan diri sendiri, maka demokrasi bisa mandek.
Masyarakat sipil juga tidak boleh pasif. Demokrasi sehat butuh warga negara yang kritis, berani mengawasi, dan berani bersuara. Jika publik diam, panggung politik akan terus dikuasai elite tanpa ada kontrol dari bawah.
Generasi muda pun punya tanggung jawab lebih besar. Jangan berhenti hanya menjadi komentator online. Perlu aksi nyata: bergabung dengan organisasi sosial, membangun gerakan lingkungan, mendorong inovasi digital, atau sekadar mengedukasi masyarakat lewat konten kreatif. Energi anak muda bisa menjadi mesin perubahan jika diarahkan dengan tepat.
Politik, Ekonomi, dan Masa Depan Sosial
Politik tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Setiap kebijakan politik berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Contoh sederhana: harga beras. Ketika pemerintah salah kelola, harga melonjak dan rakyat menjerit. Begitu pula dengan kebijakan energi. Transisi energi bukan sekadar soal mobil listrik atau panel surya, melainkan soal akses energi murah bagi rakyat kecil.
Tantangan besar pemerintahan baru adalah menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan visi jangka panjang. Apakah mereka berani membuat kebijakan pro-rakyat meski tidak populer di kalangan elite?
Masa Depan di Persimpangan
Politik 2025 ibarat berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada peluang menjadikan tahun ini tonggak perubahan. Di sisi lain, ada risiko mengulang kesalahan lama yang membuat rakyat semakin lelah.
Tantangan kita bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan dijalankan. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Demokrasi harus hidup dalam transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat.
Kesimpulan: Asa dan Cemas yang Berjalan Bersama
Harapan dan kekhawatiran kini berjalan beriringan. Masa depan politik Indonesia 2025 ditentukan oleh tiga hal:
- Komitmen elite politik dalam memegang amanah,
- Kedewasaan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan,
- Keberanian generasi muda hadir sebagai agen perubahan.
Jika tiga hal ini berjalan beriringan, maka 2025 bukan sekadar tahun transisi, melainkan awal dari politik Indonesia yang lebih matang, lebih jujur, dan lebih berpihak pada rakyat.
Namun jika gagal, bukan mustahil 2025 akan tercatat sebagai tahun penuh kekecewaan.
Pada akhirnya, politik adalah tentang masa depan bersama. Pertanyaannya kini: apakah kita siap menjaga asa sekaligus mengelola cemas demi melahirkan Indonesia yang lebih baik?
Penulis: Hasna Zhafirah, Mahasiswa Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta. (*)