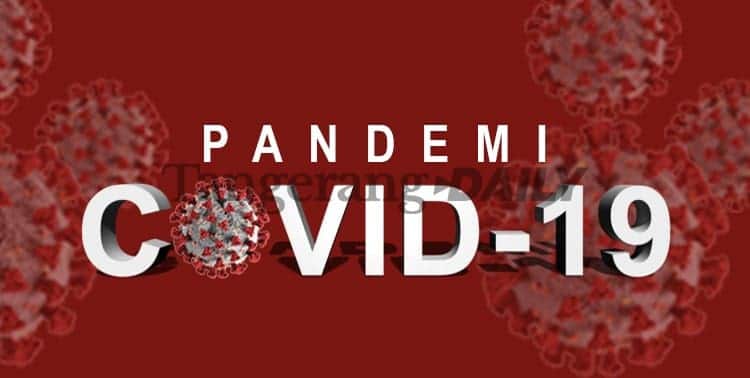Geng Solo di 2029: Demokrasi atau Dinasti?
 Suasana pencoblosan di TPS 099, Jakarta Utara pada Pemilu 2019. Proses seperti inilah yang akan kembali menentukan arah demokrasi Indonesia di 2029, di tengah perdebatan soal politik dinasti dan dominasi “Geng Solo”. (Foto: Jeromi Mikhael / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.)
Suasana pencoblosan di TPS 099, Jakarta Utara pada Pemilu 2019. Proses seperti inilah yang akan kembali menentukan arah demokrasi Indonesia di 2029, di tengah perdebatan soal politik dinasti dan dominasi “Geng Solo”. (Foto: Jeromi Mikhael / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.)OPINI | TD — Ada satu kalimat yang belakangan sering terdengar: “Geng Solo di 2029.” Sekilas terdengar seperti satire politik, tetapi ternyata tidak. Ia bukan gosip, bukan ejekan, melainkan cermin dari realitas politik Indonesia hari ini. Dari sebuah kota kecil bernama Solo, muncul lingkar kekuasaan yang kini menjadi salah satu poros utama politik nasional.
Indonesia ini luas. Puluhan provinsi, ratusan juta penduduk, dan generasi mudanya berlimpah dengan potensi. Namun, anehnya, ruang kekuasaan kita justru terasa sempit—seolah hanya dimiliki segelintir orang dari satu kota, dari satu keluarga.
Dinasti, Bukan Sekadar Isu
Dinasti politik bukan hal baru. Di tingkat desa, kabupaten, hingga pusat, pola ini sudah lama hidup: anak menggantikan bapak, istri menggantikan suami, saudara menggantikan saudara. Dalihnya selalu seragam—“punya pengalaman,” “sudah terbukti,” atau “sudah tahu medan.” Tapi mari jujur, alasan itu hanyalah selimut halus untuk mempertahankan kekuasaan.
“Geng Solo” hanya salah satu contoh paling nyata. Apakah salah secara hukum? Tidak. Tapi apakah sehat untuk demokrasi? Jelas tidak. Rakyat memang memilih, tetapi apakah pilihannya benar-benar bebas? Jika kandidat yang muncul hanyalah orang-orang dari lingkar keluarga tertentu, sementara akses ke media, partai, dan modal hanya berputar di sana, maka rakyat sesungguhnya sedang memilih di ruang yang sudah dipagari.
Dari Blusukan ke Dinasti
Jejak “Geng Solo” bermula dari Jokowi. Dari wali kota Solo yang sederhana dengan gaya blusukan, ia melesat ke Jakarta, lalu dua periode menjadi presiden. Itu prestasi besar yang diakui. Namun dari titik inilah benih politik keluarga mulai tumbuh.
Putra sulungnya, Gibran Rakabuming, melompat dari dunia kuliner ke kursi wali kota Solo, lalu langsung masuk bursa cawapres 2024. Adiknya, Kaesang Pangarep, tanpa pengalaman panjang di politik, tiba-tiba diangkat menjadi ketua umum partai.
Lompatan mereka diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan ini jelas membuka jalan bagi Gibran, dan ironisnya dibacakan ketika Ketua MK adalah ipar Jokowi. Meski belakangan ada sanksi etik, tetapi jalan sudah terbuka. Apakah ini kebetulan? Atau memang disiapkan jauh sebelumnya?
Agenda Menuju 2029
Jika ditarik ke depan, pola ini tampak seperti strategi yang matang. Ada beberapa hal yang bisa dibaca:
- Menjaga pengaruh Jokowi setelah lengser. Dengan Gibran sebagai wapres, ia tetap punya “tangan” dalam pemerintahan.
- Membuka jalan bagi dinasti yang lebih kuat. Jika Gibran sukses, Kaesang dan keluarga lainnya punya jalur lebih mudah.
- Menyiapkan peta politik 2029. Banyak yang memperkirakan Gibran akan maju sebagai capres, sementara Kaesang mengamankan mesin partai.
- Mengendalikan narasi publik. Geng Solo menampilkan citra “pemimpin muda merakyat” untuk menutupi stigma dinasti, terutama di mata pemilih muda.
- Menggunakan jaringan lama. Relawan dan pengusaha yang dulu mendukung Jokowi kini diarahkan untuk menopang Gibran dan Kaesang.
Inilah mengapa banyak yang khawatir. Yang kita lihat bukan sekadar regenerasi politik, melainkan konsolidasi keluarga dalam politik.
2029: Pesta Demokrasi atau Pesta Keluarga?
Jika Gibran benar maju sebagai capres di 2029, dengan Kaesang menguasai partai dan Jokowi tetap menjadi aktor di balik layar, maka kita menghadapi dua kemungkinan. Pertama, rakyat menerima, dan politik dinasti akan semakin mengakar, menjadikan Indonesia mirip kerajaan modern dengan baju demokrasi. Kedua, rakyat menolak, dan bisa lahir gelombang koreksi besar—entah lewat suara di bilik pemilu, atau lewat tekanan sosial.
Yang dipertaruhkan bukan hanya soal satu keluarga, melainkan masa depan demokrasi kita. Apakah republik ini milik seluruh rakyat? Atau hanya milik segelintir keluarga? Jika jawabannya yang kedua, maka 2029 bukan pesta demokrasi, melainkan pesta keluarga. Dan kita, rakyat, hanya jadi tamu undangan yang tak punya suara nyata.
Menjelang 2029, inilah pertanyaan besar: apakah kita akan menerima arah ini sebagai sesuatu yang wajar, atau justru melahirkan gelombang penolakan terhadap politik dinasti? Jawabannya akan menentukan wajah demokrasi Indonesia di masa depan.
Penulis: Amyra Noor El Fadhila, Mahasiswa semester I, Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)