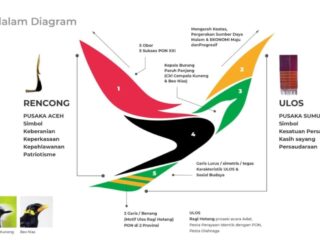Anomali Pergeseran Iklim di Indonesia
 Anomali pergeseran iklim di Indonesia membawa dampak yang luas dalam segala bidang. Tekanan ekonomi dan sosial dapat timbul karena gagal panen dan lonjakan harga kebutuhan sehari-hari yang menyulitkan masyarakat. (Foto: Freepik)
Anomali pergeseran iklim di Indonesia membawa dampak yang luas dalam segala bidang. Tekanan ekonomi dan sosial dapat timbul karena gagal panen dan lonjakan harga kebutuhan sehari-hari yang menyulitkan masyarakat. (Foto: Freepik)IKLIM | TD – Tidak terasa kini kita telah memasuki awal bulan Juli 2025, namun demikian hujan masih kerap turun bahkan dengan intensitas yang cukup tinggi pada berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini tentunya bertolak belakang dengan pola iklim klasik yang seharusnya menandai akhir musim hujan pada bulan April yang lalu. Dengan ini dapat dikatakan telah terjadi anomali pergeseran iklim di Indonesia.
Ketidakselarasan antara prediksi dan realitas ini menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar. Yakni apa yang menyebabkan pergeseran musim semakin sulit dipetakan? Dan, bagaimana dampaknya terhadap tatanan sosial serta ketahanan ekosistem lokal?
1. Letak Geografis Negara Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang dilewati oleh garis khatulistiwa dengan tepat mengenai kota Pontianak. Letaknya yang strategis karena diapit oleh 2 benua (Asia & Australia) dan 2 samudera (Pasifik & Hindia) menjadikan Indonesia memiliki pola iklim yang khas dengan dua musim utama, yaitu musim musim kemarau dan musim penghujan. Selama berabad-abad lamanya kestabilan pola iklim ini menjadi pondasi berbagai sistem kehidupan, termasuk pertanian, ekonomi, dan tradisi lokal.
Namun sejak awal abad ke-21, pola iklim dan cuaca yang dulu dapat diprediksi mulai menunjukkan gejala-gejala anomali. Musim penghujan datang lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya, dan musim kemarau pun tak lagi menjamin kering (jarang hujan). Hal ini menandai terjadinya pergeseran iklim secara sistemik di wilayah Indonesia.
Fenomena tersebut menjadi perhatian para peneliti dari BMKG, BRIN, hingga IPCC. Mereka mengidentifikasi bahwa ketidakteraturan ini bukan hanya variasi tahunan, melainkan indikasi nyata dari perubahan iklim global. Efeknya tidak hanya berdampak nyata secara fisik, tapi juga menyentuh sistem sosial, produksi pangan, dan perubahan perilaku sosial masyarakat akibat fenomena yang dialami.
2. Karakteristik Iklim Tropis di Indonesia
Indonesia memiliki iklim tropis basah yang didominasi oleh dua angin musiman, yaitu Muson Barat dan Muson Timur. Muson Barat membawa uap air dari Samudra Hindia yang menyebabkan musim penghujan (Oktober-Maret), sementara Muson Timur membawa angin kering dari Australia yang memicu musim kemarau (April-September).
Saat musim penghujan suhu udara berkisar antara 25-29°C dengan kelembaban di atas 80%. Sedangkan musim kemarau di ditandai dengan suhu udara lebih tinggi (30-34°C), kelembapan rendah, dan curah hujan minim. Siklus ini dahulu telah menjadi dasar sistem penanggalan petani seperti pranoto mongso di Jawa. Namun perubahan iklim global telah merusak prediktabilitas ini sehingga menyebabkan kerancuan dalam mengenali awal musim secara lokal.
Dampaknya terasa di berbagai sektor, khususnya pertanian dan perikanan. Ketika musim tidak sesuai dengan prediksi, atau terjadi anomali pergeseran iklim di Indonesia, maka waktu tanam dan panen pun menjadi tidak tepat. Begitu pula pola migrasi ikan yang ikut bergeser akibat perubahan suhu permukaan laut, membuat nelayan kesulitan menentukan waktu melaut yang ideal.
3. Pergeseran Pola Musiman dan Anomali Sejak 2000-an
BMKG mencatat fenomena ‘kemarau basah’ yang semakin sering terjadi sejak awal 2000-an. Ini adalah kondisi ketika musim kemarau tetap disertai curah hujan yang cukup tinggi. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan NTT, curah hujan tinggi masih terjadi pada bulan Juli dan Agustus.
Petani bawang merah di Brebes misalnya, mengalami gagal panen akibat ladangnya tergenang air saat seharusnya musim kering. Tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan bawang sangat rentan terhadap kelebihan air. Akibatnya, kerugian ekonomi dan krisis pasokan pangan lokal menjadi risiko nyata.
Masyarakat tidak lagi bisa mengandalkan tanda-tanda alam tradisional seperti arah angin, suara serangga, atau warna langit sebagai acuan musim. Kalender tanam bergeser secara tidak seragam antar wilayah, membuat manajemen pertanian menjadi lebih kompleks dan tidak sinkron.
4. Identifikasi Fenomena dan Peran BMKG
BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) merupakan lembaga utama yang pertama kali mencatat deviasi musiman sebagai anomali iklim. Dengan dukungan teknologi satelit dan sistem pemantauan, BMKG mendeteksi bahwa pola hujan, suhu, dan arah angin mengalami ketidakteraturan sejak awal 2000-an.
Laporan BMKG pada tahun 2023 menyebutkan bahwa musim kemarau pada beberapa dekade terakhir terjadi lebih pendek sekitar 20–30 hari dari keadaan normalnya. Selain itu frekuensi hujan ekstrem justru malah meningkat pada bulan-bulan transisi musim. Fenomena ini juga diamati oleh IPB, BRIN, dan pusat studi iklim lainnya.
Kerja kolaboratif antara BMKG dan perguruan tinggi kini makin penting untuk menciptakan prakiraan yang responsif terhadap perubahan iklim mikro. Beberapa wilayah mulai membentuk stasiun cuaca komunitas agar data lokal lebih akurat supaya adaptasi lebih cepat untuk diterapkan.
5. Penyebab Anomali Pergeseran Iklim
Pergeseran iklim tidak hanya disebabkan oleh faktor lokal, tetapi juga oleh dinamika global yang kompleks. Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca seperti CO₂, CH₄, dan N₂O telah meningkatkan suhu permukaan bumi secara signifikan dalam 50 tahun terakhir.
Fenomena El Niño dan La Niña turut memperburuk pola iklim Indonesia. Ketika El Niño aktif, suhu laut Pasifik meningkat dan menyebabkan kekeringan di Asia Tenggara. Sebaliknya, La Niña memperkuat curah hujan hingga menyebabkan banjir di wilayah Indonesia bagian barat.
El Niño dan La Niña adalah dua fenomena iklim global yang berkaitan dengan perubahan suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, dan keduanya sangat memengaruhi pola cuaca di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
- El Niño adalah kondisi di mana suhu permukaan laut di Pasifik tengah-timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Efeknya di Indonesia biasanya adalah musim kemarau yang lebih panjang, curah hujan berkurang, dan potensi kekeringan meningkat.
- La Niña adalah kebalikan dari El Niño, yaitu suhu permukaan laut di wilayah tersebut lebih dingin dari biasanya. Efek di Indonesia umumnya adalah musim hujan yang lebih panjang, curah hujan meningkat, dan potensi banjir atau tanah longsor lebih tinggi.
Kedua fenomena ini merupakan bagian dari siklus alami yang disebut ENSO (El Niño Southern Oscillation) dan menjadi faktor utama variabilitas iklim tahunan di kawasan tropis.
MJO (Madden-Julian Oscillation) dan IOD (Indian Ocean Dipole) juga memengaruhi pola konveksi dan distribusi hujan di wilayah tropis. Ketika dua fenomena ini berinteraksi dengan El Niño atau La Niña, hasilnya adalah ketidakpastian iklim yang sangat tinggi dan sulit diprediksi.
6. Dampak terhadap Alam dan Pertanian
Dampak anomali pergeseran iklim di Indonesia ini menjadi sangat nyata dirasakan di sektor pertanian. Selain berpotensi menyebabkan gagal panen, beberapa petani terpaksa mengganti jenis tanaman karena tanaman lama tidak cocok lagi dengan pola hujan baru. Lahan pertanian juga lebih rentan terhadap erosi dan banjir.
Ekosistem alami seperti hutan hujan tropis juga mengalami gangguan. Perubahan suhu dan kelembaban mempengaruhi keanekaragaman hayati, termasuk migrasi burung, pola kawin satwa liar, dan penyebaran hama baru.
Di sektor sosial, ketidakstabilan iklim menyebabkan lonjakan harga pangan, meningkatnya risiko kesehatan akibat penyakit tropis, dan tekanan psikologis pada petani dan nelayan yang kehilangan kepercayaan pada pola musim. Ketahanan pangan masyarakat menjadi lebih rapuh jika tidak diimbangi dengan sistem adaptasi yang responsif.
“Jika prediktabilitas musim telah goyah, lalu bagaimana dengan strategi adaptasi yang perlu dikembangkan agar sistem pertanian, perikanan, peternakan, sosial, ekonomi, kesehatan dan ketersediaan air bersih tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian iklim?”
Penulis: Sugeng Prasetyo
Editor: Patricia
Referensi Sumber:
- https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/musim-kemarau-2025-mundur-dan-berdurasi-lebih-pendek-bmkg-perubahan-pola-iklim-harus-disikapi-dengan-adaptasi-bijak
- https://gaw-bariri.bmkg.go.id/index.php/karya-tulis-dan-artikel/artikel/265-musim-kemarau-basah-fenomena-penyebab-dan-dampaknya-di-indonesia
- https://news.detik.com/berita/d-6224181/perubahan-iklim-nyata-sentra-bawang-di-brebes-terdampak
- https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7111435/450-hektare-bawang-merah-brebes-gagal-panen-asosiasi-rugi-rp-27-m
- https://www.mdpi.com/2073-4433/15/9/1036
- https://www.mdpi.com/2073-4433/13/4/537