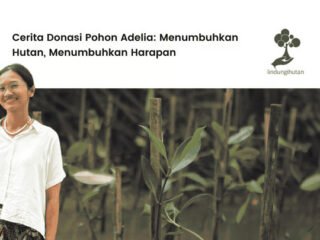Fasisme: Musuh Demokrasi yang Nyaris Terlupakan
 Fasisme Musuh Demokrasi
Fasisme Musuh DemokrasiOPINI | TD — Dalam sejarah modern, fasisme menjadi simbol kegelapan abad ke-20. Nama-nama seperti Benito Mussolini dan Adolf Hitler melekat pada kekuasaan totaliter yang menindas, penuh kekerasan, dan berbalut nasionalisme ekstrem. Dunia mengutuknya setelah perang usai, seolah-olah fasisme telah terkubur selamanya. Namun, sejarah tidak pernah benar-benar berakhir.
Umberto Eco, dalam esainya Ur-Fascism (1995), mengingatkan bahwa fasisme tidak mati—ia bertransformasi. Bentuknya berubah, bahasanya berganti, tetapi semangatnya tetap sama: mengkultuskan kekuasaan, menindas perbedaan, dan mematikan nalar kritis. Hari ini, fasisme hadir tanpa seragam militer atau simbol elang. Ia menyusup ke ruang-ruang digital, ke dalam retorika politik, bahkan ke hati masyarakat yang lelah dan putus asa terhadap demokrasi.
Fasisme dalam Wajah Baru
Demokrasi yang kita banggakan ternyata bisa melahirkan bayangan kelamnya sendiri. Fasisme modern tidak lagi ditandai oleh parade militer atau propaganda satu partai, tetapi oleh praktik politik yang menebar kebencian dan menolak perbedaan. Ia hidup melalui ujaran-ujaran yang memecah, politik identitas yang membakar emosi, serta pengkultusan terhadap figur pemimpin yang dianggap “penyelamat bangsa”.
Robert Paxton dalam The Anatomy of Fascism (2004) menjelaskan bahwa fasisme tumbuh ketika kepercayaan terhadap demokrasi melemah. Dalam situasi krisis, masyarakat cenderung mencari sosok kuat yang dianggap bisa memberi kepastian. Di titik itulah, demokrasi berubah menjadi ladang subur bagi lahirnya fasisme baru—lebih lembut, tetapi tetap berbahaya.
Bibit Fasisme di Tanah Demokrasi
Indonesia tidak kebal terhadap fenomena itu. Politik identitas yang menguat sejak Pemilu 2019 memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi toleransi kita. Polarisasi antara kubu “nasionalis” dan “religius” memecah masyarakat menjadi dua kelompok besar yang saling menaruh curiga.
Data LIPI (2020) menunjukkan, lebih dari 40 persen kampanye digital saat pemilu memuat narasi berbasis SARA. Agama dan etnis dijadikan senjata politik, bukan lagi sumber nilai moral. Di sinilah muncul apa yang disebut proto-fasisme—tahapan awal menuju sistem otoriter yang tumbuh dari kebencian identitas dan ketundukan terhadap figur pemimpin.
Ketika ruang publik dipenuhi ujaran kebencian dan politik sektarian, demokrasi kehilangan ruhnya: dialog, musyawarah, dan penghargaan terhadap keberagaman. Kita menyaksikan demokrasi yang secara formal hidup, tapi secara moral perlahan sekarat.
Ketimpangan dan Oligarki: Akar yang Tak Pernah Selesai
Namun, fasisme tidak lahir hanya dari konflik identitas. Ia berakar pada ketimpangan ekonomi dan frustrasi sosial. Dalam masyarakat yang tercekik ketidakadilan, elite politik mudah memanipulasi kemarahan publik dengan narasi identitas dan populisme murahan.
Kesenjangan sosial yang melebar menciptakan ruang bagi oligarki untuk memainkan peran ganda: tampil seolah pembela rakyat, sambil memperkuat cengkeraman ekonomi-politiknya. Ketika keadilan ekonomi absen, rakyat mudah dimobilisasi oleh janji-janji palsu yang membungkus ide otoritarian dalam selubung nasionalisme atau agama.
Karena itu, melawan bibit fasisme tidak bisa berhenti pada literasi politik. Ia harus diiringi perjuangan struktural untuk menegakkan keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi panggung yang bisa dibajak oleh siapa pun yang lihai memainkan emosi publik.
Langkah-Langkah Melawan Proto-Fasisme
Mencegah fasisme tumbuh berarti memperkuat akar demokrasi—mulai dari warga, bukan dari elite. Ada empat langkah penting yang bisa dilakukan.
- Pertama, regulasi kampanye harus diperketat, agar isu SARA tidak digunakan untuk meraih suara. Politik seharusnya kembali pada adu gagasan, bukan adu kebencian.
- Kedua, literasi politik dan digital harus diperluas, terutama di kalangan muda. Masyarakat perlu memahami cara kerja propaganda digital dan dampaknya terhadap demokrasi.
- Ketiga, ruang dialog antar-identitas harus diperkuat. Perbedaan tidak boleh dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai modal sosial yang memperkaya bangsa.
- Keempat, media massa harus kembali ke fungsi idealnya. Media tidak boleh ikut memperuncing polarisasi demi rating. Ia harus berani netral, menyajikan berita berbasis fakta, dan menjadi arena edukasi publik.
Tentu, semua langkah itu sulit dilakukan tanpa penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran publik yang kuat terhadap nilai-nilai toleransi. Namun, pelarangan total terhadap isu SARA juga bukan solusi. Ia justru bisa mengebiri kebebasan berekspresi. Jalan terbaik adalah mendidik masyarakat agar tahan terhadap provokasi dan mampu berpikir rasional di tengah gempuran informasi.
Demokrasi yang Waspada
Fasisme tidak selalu datang dengan kekerasan. Ia bisa hadir lewat kata-kata, simbol, dan kebijakan yang diskriminatif. Demokrasi bisa runtuh bukan karena kudeta, tetapi karena rakyatnya berhenti berpikir kritis.
Menjaga demokrasi berarti menjaga kewarasan publik. Masyarakat yang berpikir jernih, menghargai perbedaan, dan tidak mudah dimanipulasi adalah benteng terakhir dari kebebasan. Pendidikan politik yang inklusif, pemerataan ekonomi, dan media independen harus berjalan beriringan untuk mencegah demokrasi berubah menjadi sekadar formalitas tanpa substansi.
Penutup
Fasisme memang musuh lama, tetapi ancamannya tetap nyata. Ia menyamar dalam bahasa moral, nasionalisme, bahkan agama. Bahayanya bukan hanya pada kekuasaan yang menindas, tetapi pada masyarakat yang diam—yang lupa bahwa demokrasi hidup dari kesadaran dan partisipasi warganya.
Republik ini akan tetap berdiri jika rakyatnya terus berpikir kritis, berani berbeda, dan menolak politik kebencian. Selama kesadaran itu hidup, fasisme dalam bentuk apa pun tidak akan pernah menemukan tempat untuk tumbuh di tanah Indonesia.
Penulis: Anindya Angres Ramadhianti
Mahasiswa Semester 1, Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA). (*)