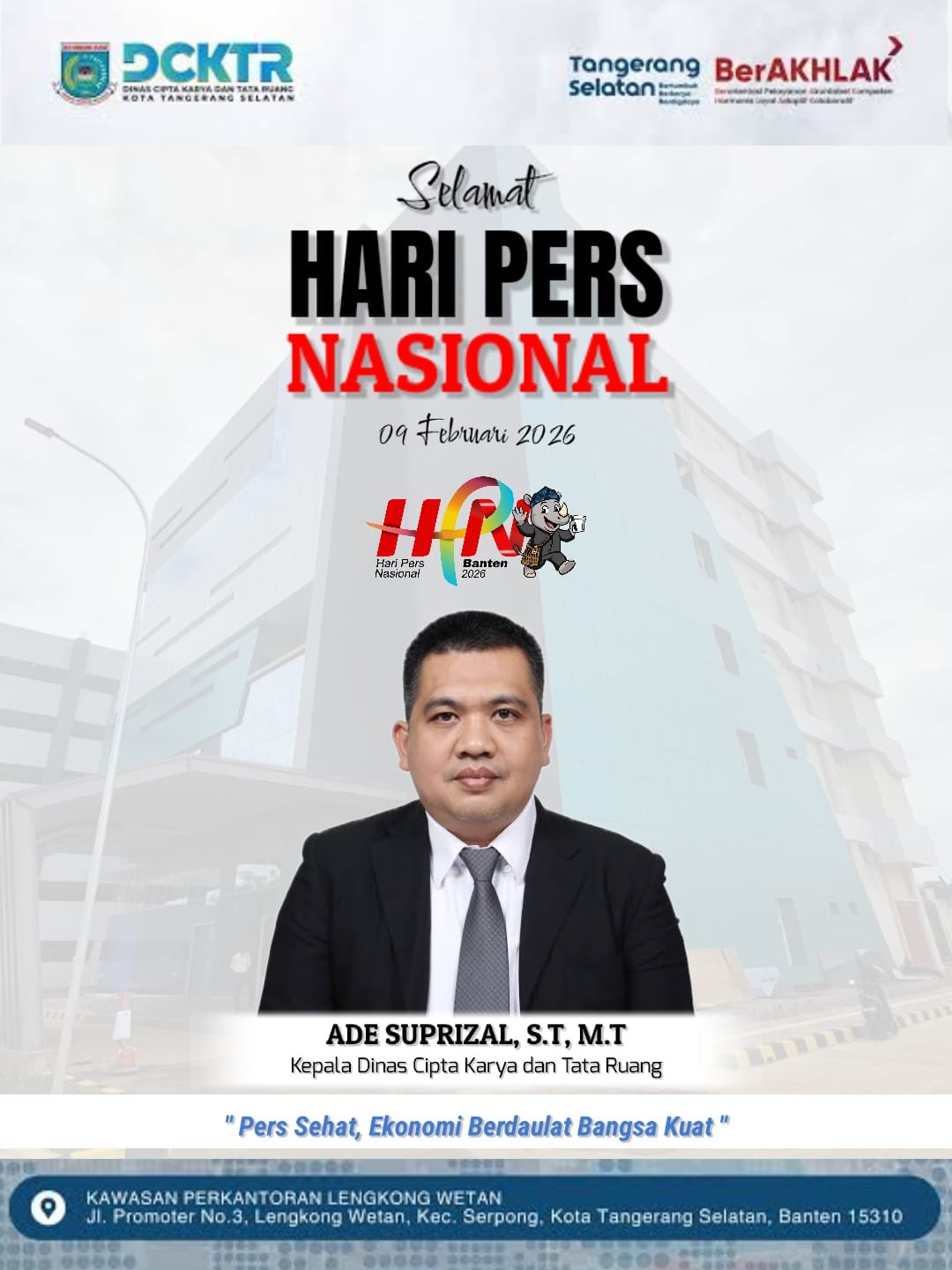Kemiskinan Perempuan di Indonesia: Mengapa Kebijakan Pengentasan Gagal Menjawab Kebutuhan Gender
 Yasmin Widad Prasetya Darma (Foto: Dok. Pribadi)
Yasmin Widad Prasetya Darma (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD — Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, perempuan Indonesia tetap menjadi kelompok yang paling rentan dan paling tertinggal. Mengapa program pengentasan kemiskinan selama ini gagal menyentuh kebutuhan spesifik perempuan? Jawabannya terletak pada kebijakan yang masih buta gender dan struktur sosial yang tidak adil.
Pada Maret 2025, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan nasional menurun menjadi 8,47 persen, sebuah capaian yang secara makro terlihat positif (Statistik, 2025). Namun, di balik statistik tersebut tersembunyi kenyataan yang jauh lebih kompleks: perempuan mengalami kemiskinan dalam bentuk yang lebih dalam, lebih sistemik, dan lebih sulit diatasi dibandingkan laki-laki.
Data menunjukkan bahwa hanya 44 persen rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan berhasil keluar dari kemiskinan, dibandingkan 50,6 persen rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki. Kesenjangan ini bukan sekadar angka—ia menandakan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia masih gagal merespons realitas dan kebutuhan berbasis gender.
Feminisasi Kemiskinan: Ketika Sistem Tidak Memihak Perempuan
Fenomena ini dikenal sebagai feminisasi kemiskinan, yakni kondisi di mana perempuan secara sistematis lebih rentan terhadap kemiskinan akibat struktur sosial, politik, dan ekonomi yang patriarkal dan diskriminatif. Dalam banyak kasus, perempuan tidak miskin karena pilihan atau kurang usaha, melainkan karena sistem yang menutup akses dan peluang secara struktural.
Studi Kasus: Perempuan Miskin di Tengah Industrialisasi Banten
Contoh konkret dari feminisasi kemiskinan dapat ditemukan di Desa Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten—daerah yang seharusnya sejahtera karena berada di pusat industrialisasi. Namun di wilayah ini, perempuan kepala rumah tangga tetap terjebak dalam kemiskinan struktural yang multidimensional.
Lima dimensi kemiskinan mereka mencakup:
- Ketiadaan akses terhadap pengambilan keputusan ekonomi,
- Keterasingan dari layanan publik,
- Kerentanan terhadap guncangan ekonomi,
- Kekurangan material, dan
- Keterbatasan terhadap sumber daya produktif.
Yang mencolok, penyebab utamanya bukan lokasi geografis atau keterisolasian, melainkan relasi gender yang timpang dalam keluarga dan masyarakat.
Narasi Pendidikan Saja Tidak Cukup
Pendidikan sering disebut sebagai kunci pengentasan kemiskinan. Namun narasi ini gagal memahami realitas perempuan miskin. Akses terhadap pendidikan justru dibatasi oleh kondisi ekonomi mereka sendiri.
Dalam keluarga miskin, ketika harus memilih siapa yang bersekolah, anak laki-laki sering diutamakan. Perempuan dianggap tidak membawa “keuntungan” ekonomi jangka panjang karena akan menikah dan “menjadi tanggung jawab keluarga suami”. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada rendahnya kesadaran, tetapi pada sistem ekonomi dan budaya yang tidak adil.
Maka, menyederhanakan solusi kemiskinan perempuan hanya lewat pendidikan mengaburkan tanggung jawab negara dalam menciptakan akses ekonomi yang setara dan jaring pengaman sosial yang efektif.
Ketimpangan Politik dan Representasi Perempuan
Kebijakan yang tidak sensitif gender juga mencerminkan minimnya representasi perempuan dalam politik. Indonesia hanya menempati posisi ke-7 di Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.
Akibatnya, program pengentasan kemiskinan seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman spesifik perempuan. Studi menunjukkan bahwa tingkat ketidaksetaraan gender secara signifikan memperburuk kemiskinan (Setiawan & Jamaliah, 2023).
Walaupun kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif sudah diatur, implementasinya masih lemah. Banyak perempuan hanya dijadikan “pelengkap daftar”, bukan aktor politik yang didukung penuh untuk menang.
Program Pemerintah: Kurang Sensitif, Kurang Efektif
Program seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) hanya melihat perempuan sebagai penerima manfaat pasif, bukan sebagai agen perubahan ekonomi. Tidak ada pelatihan keterampilan, akses modal, atau dukungan ekonomi yang cukup untuk mendorong kemandirian perempuan miskin.
Selain itu, banyak program gagal memahami beban ganda perempuan. Waktu pelatihan sering tidak ramah terhadap peran domestik yang dijalankan perempuan, dan tanpa dukungan seperti penitipan anak, perempuan sulit berpartisipasi.
Perempuan Profesional ≠ Perempuan Sejahtera
Meskipun statistik menunjukkan peningkatan jumlah perempuan profesional, mayoritas perempuan pekerja masih berada di sektor informal dengan keterampilan rendah. Sekitar 26 persen bekerja sebagai pekerja rumah tangga, tanpa perlindungan dan jaminan sosial.
Peningkatan jumlah perempuan profesional tidak mencerminkan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan, melainkan hanya peningkatan kesejahteraan sebagian kecil kelompok menengah-atas. Kesenjangan antarperempuan justru semakin melebar.
Pernikahan Dini: Strategi Bertahan yang Mematikan Masa Depan
Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dalam jumlah pernikahan anak, dengan 25,53 juta perempuan menikah di bawah usia 18 tahun (Purwanti, 2024). Di banyak daerah, pernikahan dini bukan sekadar tradisi, melainkan strategi bertahan hidup dalam kemiskinan.
Keluarga miskin memandang anak perempuan sebagai “beban” yang lebih baik dinikahkan daripada dibiayai. Namun, ini justru menciptakan siklus kemiskinan baru yang ditandai oleh tingginya risiko kesehatan, ketergantungan ekonomi, dan hilangnya potensi perempuan secara permanen.
Kesimpulan: Butuh Transformasi Politik, Bukan Sekadar Program Sosial
Kemiskinan perempuan di Indonesia adalah manifestasi dari ketidakadilan struktural. Selama kebijakan pengentasan kemiskinan tidak didesain dengan perspektif gender, perempuan akan terus menjadi kelompok yang paling tertinggal.
Kesetaraan gender bukanlah nilai tambahan, melainkan prasyarat utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi politik dan sosial harus dimulai dengan memberikan ruang representasi yang nyata bagi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi dan sosial menjawab kebutuhan nyata perempuan miskin.
Tanpa itu, angka kemiskinan bisa saja turun—tetapi perempuan akan tetap tertinggal di belakang.
Penulis: Yasmin Widad Prasetya Darma
Mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA. (*)