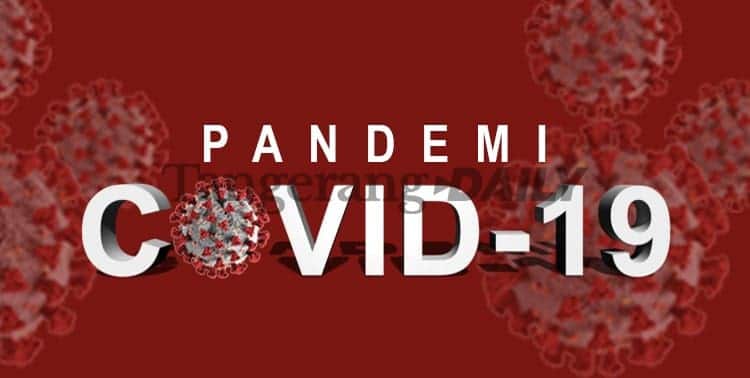Keracunan MBG: Saat Nasionalisme Membutakan Sikap Kritis
 Ilustrasi anak-anak yang khawatir menghadapi makanan, mencerminkan dampak keracunan pada program Makan Bersama Gratis (MBG). (Foto: Freepik @pressfoto)
Ilustrasi anak-anak yang khawatir menghadapi makanan, mencerminkan dampak keracunan pada program Makan Bersama Gratis (MBG). (Foto: Freepik @pressfoto)OPINI | TD — Program Makan Bersama Gratis (MBG) yang digagas pemerintah lahir dari niat mulia: memastikan rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah, bisa mendapatkan gizi yang cukup. Dalam konsepnya, MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan simbol kepedulian negara terhadap rakyat.
Di tengah harga bahan pokok yang kian mahal dan tingginya angka gizi buruk, program ini sempat dianggap sebagai angin segar. Namun, kasus keracunan yang menimpa sejumlah warga akibat makanan MBG justru membuka sisi lain: ketika program mulia berubah menjadi masalah serius.
Sayangnya, alih-alih dijadikan momentum untuk evaluasi, sebagian pihak justru sibuk membela pemerintah dengan alasan nasionalisme. “Kalau cinta Indonesia, jangan merusak nama baik program. Semua demi bangsa,” begitu kira-kira argumen yang muncul. Narasi ini membuat kritik yang mestinya wajar menjadi seolah pengkhianatan.
Banal Nasionalisme: Cinta Buta pada Kebijakan
Inilah yang disebut banal nasionalisme—nasionalisme dangkal yang diwujudkan lewat slogan, simbol, dan seruan cinta tanah air. Masalahnya, banal nasionalisme sering membuat masyarakat percaya semua kebijakan pemerintah pasti benar hanya karena dibungkus dengan semangat kebangsaan.
Kasus MBG menjadi contohnya. Padahal pertanyaan kritis wajib diajukan:
- Mengapa bisa terjadi keracunan?
- Apakah ada standar pengawasan kualitas makanan?
- Bagaimana mekanisme distribusinya?
- Apakah vendor yang ditunjuk kompeten?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk kebencian, melainkan justru wujud cinta tanah air yang lebih nyata: memastikan rakyat selamat dan sejahtera.
Cinta sejati kepada bangsa bukan membenarkan semua tindakan pemerintah, melainkan berani mengoreksi ketika ada yang salah. Namun, banal nasionalisme sering dipakai untuk membungkam kritik. Mereka yang bersuara dianggap tidak nasionalis, bahkan anti-negara. Akibatnya, masalah nyata pun dibiarkan tanpa solusi.
Populisme dalam Bungkus MBG
Kasus MBG juga memperlihatkan wajah lain politik Indonesia: populisme. Program makan gratis adalah janji politik sederhana yang terdengar “pro-rakyat” dan mudah diterima. Pemimpin tampil seolah dekat dengan rakyat, peduli dengan kebutuhan dasar mereka.
Namun, ciri khas populisme adalah janji instan tanpa perencanaan matang. Makanan memang dibagikan, tetapi bagaimana kualitasnya? Bagaimana transparansi anggarannya? Apakah ada audit independen? Pertanyaan itu sering tak terjawab, karena populisme lebih sibuk membangun kesan simpatik ketimbang solusi jangka panjang.
Keracunan MBG bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan cermin dari kelemahan gaya politik populis: program yang seharusnya bermanfaat justru berbalik merugikan.
Demokrasi dalam Paradoks
Demokrasi mestinya memberi ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan. Namun, dalam kasus MBG, kritik justru memicu polarisasi. Ada yang berani bersuara tapi segera dicap anti-pemerintah. Ada pula yang memilih diam karena takut dicap tidak nasionalis.
Fenomena ini terlihat jelas di media sosial. Ketika kasus keracunan mencuat, sebagian warganet menuntut evaluasi serius. Tetapi banyak pula yang menyerang balik dengan narasi: “Kalau benar cinta bangsa, jangan ikut-ikutan merusak citra program.” Alih-alih diskusi sehat, ruang publik berubah menjadi arena saling tuding.
Padahal demokrasi sehat menuntut akuntabilitas: pemerintah wajib menjelaskan mengapa keracunan terjadi dan bagaimana mencegahnya terulang. Rakyat berhak mendapat jawaban, bukan sekadar slogan nasionalisme.
Media dan Peran Kontrol
Dalam isu ini, media massa memegang peran penting. Sebagian media menyoroti kasus keracunan sebagai alarm, tetapi ada juga yang justru lebih menekankan sisi positif program, bahkan menganggap keracunan sebagai “insiden kecil”.
Jika media terlalu dekat dengan kekuasaan dan hanya menjaga citra pemerintah, banal nasionalisme akan semakin menguat. Masyarakat dijejali slogan cinta tanah air tanpa diajak berpikir kritis. Padahal, fungsi utama media adalah kontrol sosial—memberi informasi jernih, objektif, dan mendorong solusi.
Belajar dari India
Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi masalah ini. India pernah meluncurkan program makan siang gratis di sekolah untuk mengurangi kelaparan anak-anak miskin. Tujuannya mulia, tetapi beberapa kali terjadi keracunan massal karena lemahnya standar kebersihan.
Awalnya, banyak yang membela program tersebut dengan alasan nasionalisme. Namun, setelah korban berjatuhan, evaluasi serius dilakukan, mulai dari memperbaiki rantai distribusi hingga melibatkan pengawasan lembaga independen.
– Pelajaran penting: program populis yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan profesionalisme tinggi, bukan hanya semangat nasionalisme semu.
– Jalan Keluar: Nasionalisme Kritis, Populisme Rasional
Apa yang bisa dilakukan? Ada tiga langkah penting:
- Pemerintah harus membuka ruang evaluasi. Setiap kasus keracunan wajib diusut tuntas dengan transparansi penuh, bukan ditutup demi menjaga citra.
- Rakyat perlu membangun nasionalisme kritis. Cinta tanah air berarti berani mengoreksi, bukan sekadar membela.
- Media dan akademisi harus berperan aktif. Bukan sekadar menyebar sensasi, tetapi memberi masukan berbasis riset dan fakta agar program benar-benar bermanfaat.
Jika langkah-langkah ini ditempuh, banal nasionalisme bisa berubah menjadi nasionalisme kritis; populisme bisa diarahkan menjadi populisme rasional; dan demokrasi kembali pada tujuannya: melindungi rakyat.
Penutup
Keracunan MBG harus menjadi alarm keras. Pemerintah perlu berbenah, rakyat harus kritis, dan media wajib objektif. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam nasionalisme buta, populisme instan, dan demokrasi paradoks.
Cinta tanah air bukan membenarkan semua kebijakan, melainkan memastikan tidak ada rakyat yang menjadi korban karena program dijalankan tanpa pengawasan matang. Nasionalisme sejati adalah keberanian memperjuangkan keselamatan rakyat.
Penulis: Alya Fauziyah, Mahasiswi Semester I, Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)