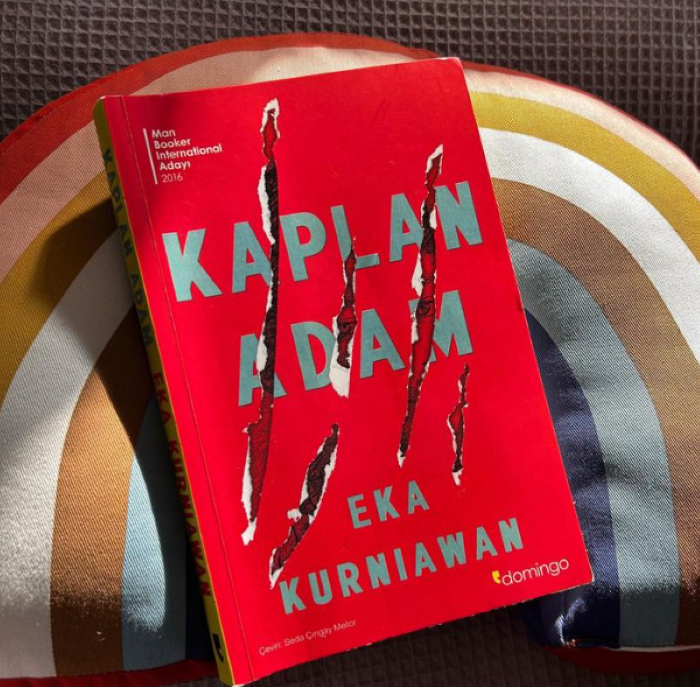“Sehidup Semati” Film Perempuan
 Salah satu adegan dalam film Sehidup Semati, film yang mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga. (Foto: instagram @sehidupsematifilm)
Salah satu adegan dalam film Sehidup Semati, film yang mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga. (Foto: instagram @sehidupsematifilm)HIBURAN | TD – Film “Sehidup Semati” yang dibintangi Laura Basuki terus mendapat sorotan di antara para pemerhati masalah perempuan di berbagai media.
Film yang dirilis pada 2024 ini menceritakan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Renata dan juga tentang kesetaraan hak.
Pernikahan yang Berubah Menjadi Mimpi Buruk
Awalnya, pernikahan Renata dengan Edwin terlihat indah, terutama saat perayaan pernikahan mereka. Namun, kehidupan pasangan tersebut berubah menjadi mimpi buruk.
Renata, selain menerima perlakuan kekerasan dari suami, ternyata juga mengalami teror dari seorang perempuan asing. Sementara itu, hanya satu orang saja yang memberikan dukungan baginya untuk keluar dari lingkaran setan tersebut, yaitu tetangganya yang bernama Asmara. Tetapi, Asmara bukanlah perempuan baik-baik, dan Renata masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya.
Ketegangan Berintensitas Tinggi
Upi Avianto, sang sutradara, dapat disebut cukup berhasil mengangkat isu KDRT dan kesetaraan gender dalam film bergenre psychological thriller yang dibalut adegan-adegan horor. Ketegangan demi ketegangan yang dibangun pun memberikan kesan mendalam mengenai kedua isu yang terus menghangat tersebut.
Kepiawaian Laura Basuki berakting, bersama Ario Bayu (Edwin) dan Asmara Abigail (Asmara), juga merupakan kunci dari keberhasilan film ini memikat mata penonton dan ikut menenggelamkannya ke dalam emosi dan keterkejutan.
Bahkan ada adegan dengan ketegangan berintensitas tinggi saat Renata dan Edwin berada dalam satu ruangan. Selain itu, kesan yang kuat dan saling melengkapi timbul justru dari perbedaan sifat yang begitu kontras antara Renata dan Asmara yang bersahabat.
Ulasan Mengenai Ketertindasan
Salah satu media yang concern dengan permasalahan perempuan menuliskan bahwa dasar permasalahan ketertindasan perempuan adalah dukungan dari kultur atau budaya religius tertentu. Budaya ini mengandung norma-norma yang mengharuskan perempuan untuk selalu diam dan menerima, bahkan ketika harus menghadapi tekanan keras dari suami.
Budaya seperti demikian akan mendorong korban untuk menerima tekanan tersebut sebagai ‘cobaan’, ‘konsekuensi’, ‘aib yang tak boleh tersebar’, atau bahkan ‘hukuman’.
Sebagai akibat dari berlakunya norma dan budaya yang menekan tersebut, perempuan akan menjadi sangat sulit membuka diri bahkan tidak mungkin bicara ketika ia mengalami kekerasan.
Selain itu, perempuan yang menjadi korban kekerasan, dalam lingkungan budaya yang demikian, justru akan menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang ia alami.
Yang perlu disadari, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah bumbu pernikahan. Justru KDRT perlu disikapi sebagai masalah bersama, dan bukan persoalan privat. Mengatasi persoalan KDRT memerlukan bantuan pihak lain yang tepat.
Pihak-pihak yang tepat dan dapat membantu, seperti Yayasan Rifka Annisa dengan Women’s Crisis Centre misalnya, dapat menjadi pihak yang tepat untuk berkonsultasi dan memberikan advokasi. Sedangkan di sisi lain, regulasi seperti Undang-Undang mengenai kekerasan rumah tangga dapat menjadi support system yang baik untuk melindungi perempuan dari kekerasan. (Pat)