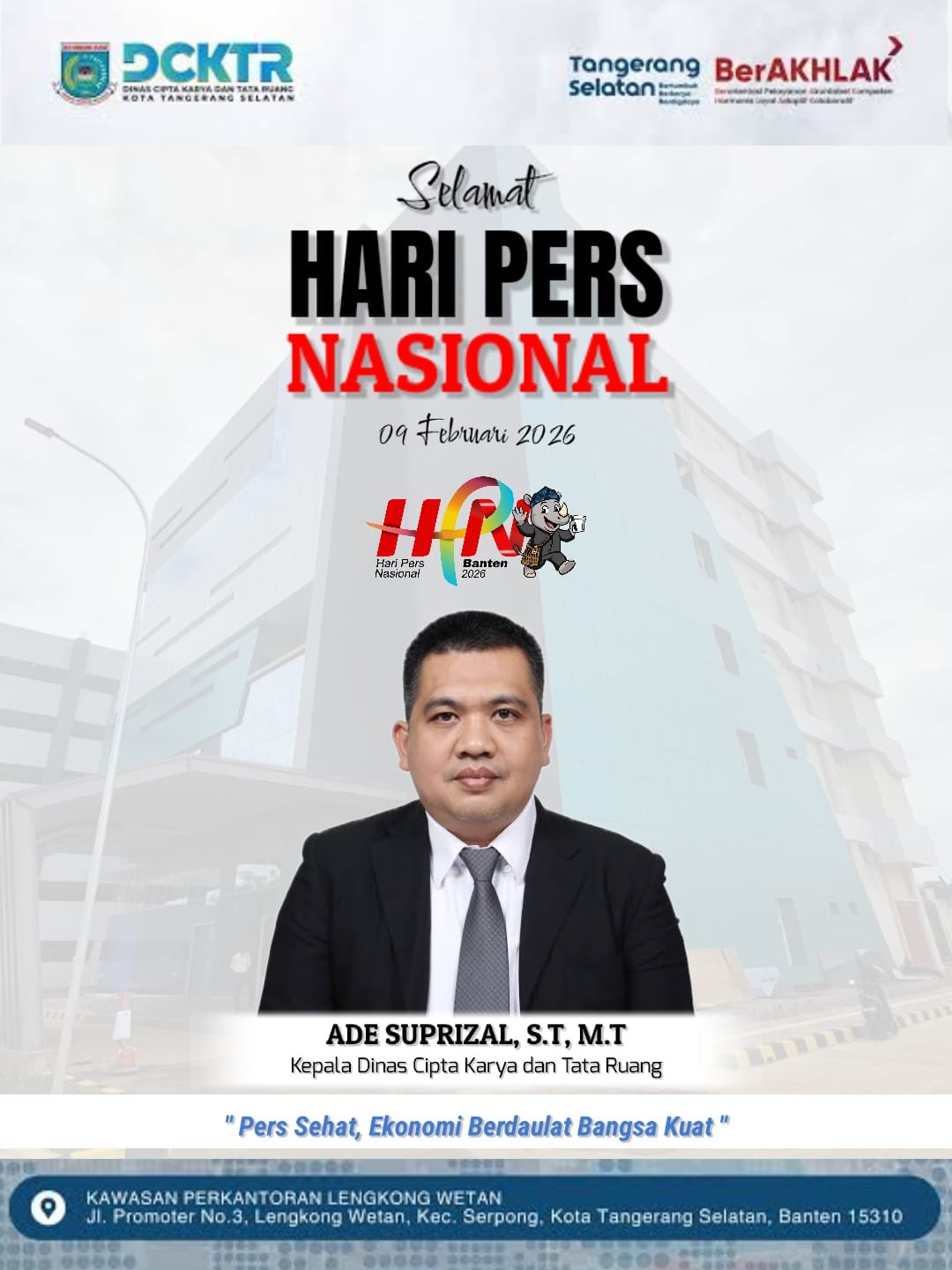Strategi Pengendalian dan Penguatan Ketahanan Pangan Berbasis Lokal di Nusa Tenggara Timur
 Amalia Rizky Arrosa. (Foto: Dok. Pribadi)
Amalia Rizky Arrosa. (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD — Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai salah satu provinsi dengan potensi alam luar biasa, namun juga menghadapi tantangan besar dalam hal ketahanan pangan. Kekurangan pasokan bahan makanan, kegagalan panen, hingga kasus gizi buruk masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah. Kondisi geografis yang kering dan curah hujan rendah membuat sebagian besar masyarakat NTT bergantung pada pertanian lahan kering, yang rentan terhadap perubahan iklim dan kekeringan panjang (Trigutomo, 2019).
Tantangan Ketahanan Pangan di Tengah Keterbatasan
Meski pemerintah telah menggulirkan beragam program ketahanan pangan, realisasinya belum sepenuhnya optimal. Hanya sekitar 45% lahan pertanian yang saat ini dimanfaatkan secara efektif (Trigutomo, 2019). Rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, kurangnya pembinaan rumah produksi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga turut memperlambat kemajuan. Akibatnya, kerawanan pangan masih kerap terjadi, bahkan berdampak pada tingginya angka kekurangan gizi pada balita di beberapa daerah.
Menghidupkan Potensi Lokal: Ubi Kayu sebagai Sumber Harapan
Salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan lokal di NTT adalah memanfaatkan potensi tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi alam setempat. Di antara berbagai tanaman pangan, ubi kayu muncul sebagai komoditas andalan. Tanaman ini mudah tumbuh di lahan kering dan dapat dipanen dalam waktu relatif singkat.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ubi kayu berperan besar dalam mendukung program diversifikasi pangan dan menjadi alternatif pengganti beras di wilayah NTT, khususnya di Kabupaten Sikka yang menjadi sentra produksi terbesar di Pulau Flores (Ngaku et al., 2024). Selain menyediakan sumber karbohidrat utama setelah padi dan jagung, pengembangan ubi kayu juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani lokal.
Sinergi Kebijakan Nasional dan Kearifan Lokal
Upaya memperkuat ketahanan pangan di NTT tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat lokal. Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah mutlak diperlukan. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah mendorong program lumbung pangan nasional (food estate) dengan menekankan penggunaan bahan pangan lokal sebagai solusi mengatasi krisis beras di NTT (Rahmawati & Mahadri, 2024).
Namun di sisi lain, kekuatan terbesar justru datang dari bawah—dari masyarakat sendiri. Di Flores Timur, petani masih mempertahankan sistem pertanian tradisional yang berlandaskan pada kearifan lokal. Mereka menanam, mengolah, dan memasarkan hasil panennya di pasar-pasar regional tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya. Gerakan pangan lokal ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menjaga identitas dan keharmonisan dengan alam (Nugraha et al., 2016).
Pangan Lokal Sebagai Identitas dan Ketahanan Budaya
Bagi masyarakat NTT, pangan lokal tidak hanya soal kebutuhan perut, tetapi juga simbol identitas budaya dan kemandirian. Umbi-umbian seperti ubi kayu, talas, dan ubi jalar bukan sekadar variasi menu, melainkan juga cadangan penting saat musim paceklik atau bencana melanda (Naisali et al., 2023).
Dengan menghidupkan kembali pangan lokal, masyarakat tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga melestarikan pengetahuan tradisional dan cara hidup yang ramah lingkungan. Pangan lokal menjadi jembatan antara tradisi dan inovasi—antara masa lalu dan masa depan.
Langkah Menuju Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan
Ketahanan pangan di NTT dapat diperkuat melalui empat langkah utama:
1. Meningkatkan produksi pangan lokal, dengan fokus pada komoditas yang adaptif terhadap iklim kering.
2. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, terutama petani muda melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Menjaga konsistensi kebijakan dan implementasi, agar program pemerintah berjalan berkelanjutan, bukan sporadis.
4. Melestarikan keanekaragaman pangan lokal, dengan inovasi pengolahan dan edukasi gizi di tingkat masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, NTT dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional. Ketahanan pangan lokal bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih mandiri, berdaulat, dan lestari.
Daftar Pustaka
Naisali, H., Utoro, P. A. R., & Witoyo, J. E. (2023). Review keragaman dan metode pengolahan umbi-umbian lokal Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pangan dan Gizi, 13(2), 1–17. https://doi.org/10.26714/jpg.13.2.2023.1-17
Ngaku, M. A., Dea, A. Y., & Kaleka, M. U. (2024). Pengembangan pangan lokal berbasis ubi kayu dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agribios, 22(2), 213–220. https://doi.org/10.36841/agribios.v22i2.5327
Nugraha, A., Hestiawan, M. S., & Supyandi, D. (2016). Refleksi paradigma kedaulatan pangan di Indonesia: Studi kasus gerakan pangan lokal di Flores Timur. Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad, 1(2), 101–112. https://doi.org/10.24198/agricore.v1i2.22717
Rahmawati, N., & Mahadri, M. A. R. (2024). Sinergitas kebijakan pangan negara anggota ASEAN dengan prioritas kebijakan pemerintah Indonesia menangani krisis pangan di Nusa Tenggara Timur. Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS), 3(1), 162–170. https://doi.org/10.36722/psn.v3i1.2503
Trigutomo, W. H. (2019). Strategi pembangunan ketahanan dan ketersediaan pangan tingkat lokal Nusa Tenggara Timur di tengah perubahan iklim melalui pendidikan di SMK-PP Negeri Kupang. Edutech, 18(1), 37–45. https://doi.org/10.17509/e.v18i1.4081
Penulis: Amalia Rizky Arrosa
Mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)