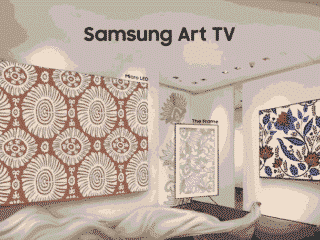Politik Uang: Pilar Kelima yang Merusak Demokrasi Indonesia
 Ilustrasi: Rekayasa gambar menggunakan kecerdasan buatan (AI)
Ilustrasi: Rekayasa gambar menggunakan kecerdasan buatan (AI)OPINI | TD — Demokrasi Indonesia berdiri di atas empat pilar: kebebasan, kedaulatan rakyat, konstitusi, dan supremasi hukum. Namun, ada satu “pilar bayangan” yang diam-diam ikut menopang—bukan untuk menguatkan, tetapi justru untuk merusak: politik uang.
Politik Uang: Bukan Pilar, Tapi Penyakit Demokrasi
Secara ideal, demokrasi adalah sistem politik yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat secara jujur dan adil. Namun realitanya, demokrasi Indonesia sedang dirongrong oleh praktik transaksional yang menjadikan uang sebagai alat utama meraih kekuasaan. Dari pemilihan kepala desa hingga pemilu nasional, praktik “serangan fajar”, pembagian sembako, atau bahkan transfer dompet digital menjadi hal yang “lumrah”.
Dalam konteks ini, politik uang seolah menjelma menjadi pilar kelima demokrasi. Ia tidak tertulis di konstitusi, tidak diajarkan di bangku sekolah, namun begitu nyata dalam setiap siklus pemilu. Ironisnya, sebagian masyarakat pun menganggap ini wajar. Bagi mereka, pemilu adalah momen langka untuk “memanen” keuntungan sesaat. Ketika kondisi ekonomi sulit, uang Rp50.000 pun bisa menggoyahkan idealisme.
Kandidat politik pun tidak kalah pragmatis. Dalam sistem yang minim pendidikan politik dan pengawasan, cara termudah meraih suara adalah “membeli” suara. Cepat, praktis, dan—sayangnya—efektif.
Dampak Politik Uang: Demokrasi Tanpa Arah
Politik uang tidak hanya mencederai moralitas demokrasi, tapi juga berdampak langsung pada kualitas pemerintahan. Ketika suara dibeli, pemimpin yang terpilih bukanlah yang paling kompeten atau bermoral, melainkan yang paling kaya. Janji kampanye hanyalah alat formalitas. Setelah menang, kepentingan rakyat digeser oleh kepentingan balik modal.
Lebih parah lagi, politik uang menciptakan siklus korupsi yang tak berujung. Uang yang dikeluarkan saat kampanye harus dikembalikan—biasanya melalui cara-cara tidak etis. Maka tak heran jika korupsi anggaran, proyek siluman, dan birokrasi transaksional menjadi pemandangan sehari-hari di negeri ini.
Evaluasi kinerja pun menjadi kabur. Masyarakat yang suaranya “dibeli”, tidak punya ekspektasi tinggi terhadap pemimpinnya. Akibatnya, kontrol sosial melemah, dan ruang publik dipenuhi apatisme politik.
Harapan Masih Ada: Tiga Langkah Menuju Demokrasi Bersih
Apakah politik uang bisa dihentikan? Jawabannya tidak mudah, tapi bukan mustahil. Ada tiga langkah strategis yang bisa ditempuh untuk menekan dominasi pilar kelima ini:
- Pendidikan Politik Berkelanjutan
Masyarakat harus disadarkan bahwa hak suara bukan barang dagangan. Pendidikan politik harus dimulai sejak dini, masuk ke kurikulum sekolah, dan terus digaungkan melalui media, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan. Demokrasi sejati hanya bisa lahir dari pemilih yang sadar, bukan pemilih yang lapar. - Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten
Regulasi tentang politik uang sudah ada, tetapi implementasinya masih lemah. Banyak pelanggaran yang berujung pada impunitas. Bawaslu dan lembaga penegak hukum harus berani menindak pelaku politik uang, siapa pun dia—tanpa pandang bulu. - Perubahan Budaya Politik di Tingkat Elite
Partai politik harus berhenti menjadikan uang sebagai senjata utama. Mereka harus kembali pada fungsi sejatinya: mendidik kader, menyusun program, dan mengadvokasi aspirasi rakyat. Kampanye harus berbasis gagasan, bukan amplop.
Kesimpulan: Demokrasi Butuh Rakyat yang Berani Menolak
Politik uang adalah racun bagi demokrasi. Ia bukan pilar kelima, melainkan lubang kelima yang perlahan meruntuhkan bangunan demokrasi kita. Selama praktik ini dibiarkan, demokrasi Indonesia hanya akan menjadi teater—penuh sorak di permukaan, tetapi kosong di dalam.
Masa depan demokrasi ada di tangan kita semua. Rakyat yang berani menolak, media yang konsisten mengawasi, aparat hukum yang tegas, dan elite politik yang sadar bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup jika suara rakyat tak ternoda oleh transaksi.
Jika semua elemen bangsa bersatu, maka politik uang bisa dikikis, dan demokrasi Indonesia akan kembali berdiri tegak di atas empat pilar sejatinya: kebebasan, kedaulatan rakyat, konstitusi, dan hukum yang adil.
Penulis: Najwa Fitria Ramadani, Mahasiswa Semester 1, Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)