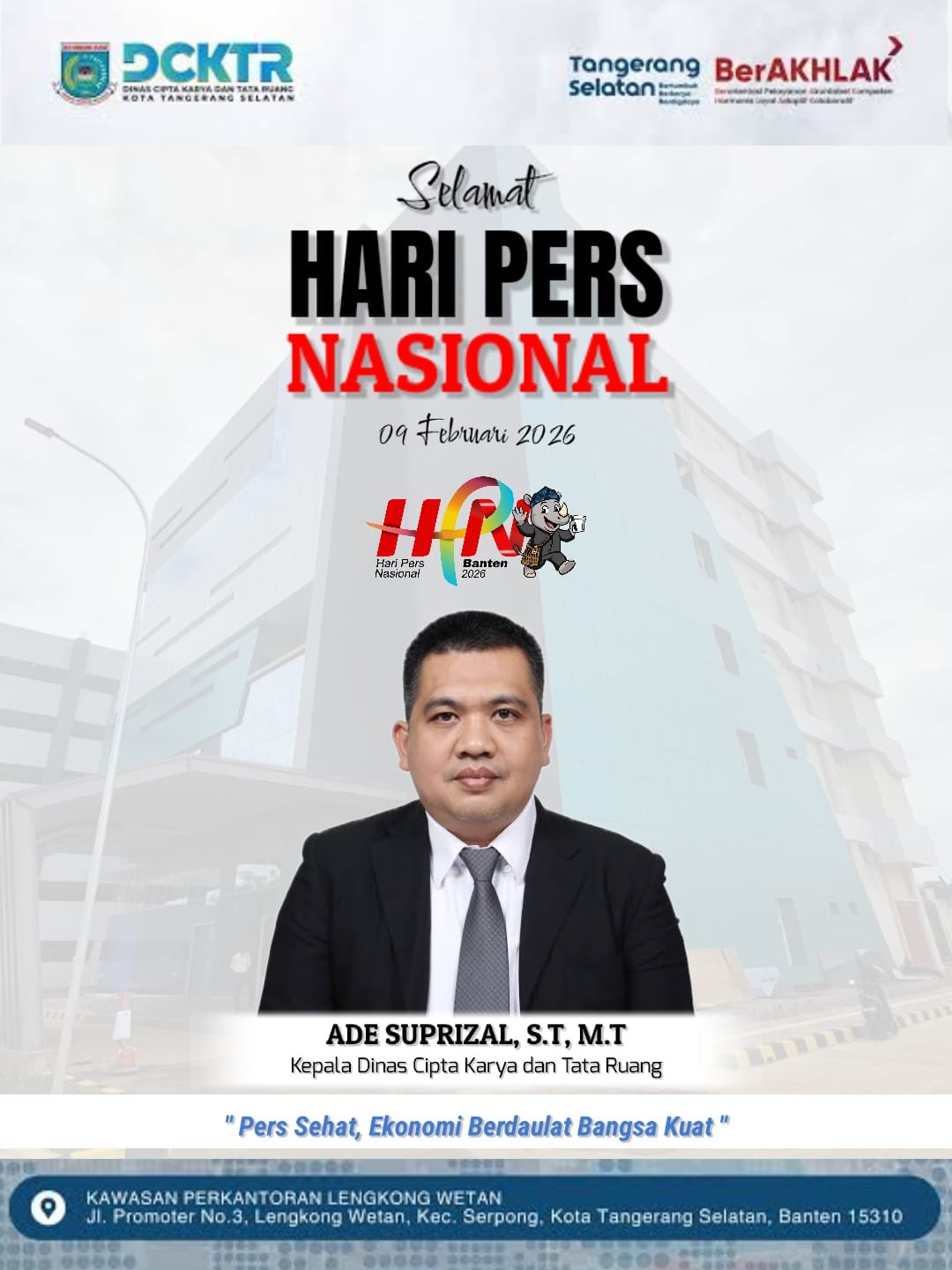Politik dan Generasi Z: Tantangan dan Harapan Menuju 2029
 Ilustrasi: Rekayasa gambar menggunakan kecerdasan buatan (AI)
Ilustrasi: Rekayasa gambar menggunakan kecerdasan buatan (AI)OPINI | TD — Menjelang Pemilu 2029, Generasi Z diprediksi akan menjadi kelompok pemilih paling dominan di Indonesia. Lahir dan tumbuh di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang deras, generasi ini memiliki keunggulan dalam hal akses informasi, keberanian menyuarakan pendapat, dan kepekaan terhadap isu-isu sosial. Namun, di balik potensi besar itu, Generasi Z juga menghadapi tantangan serius: apatisme, krisis kepercayaan terhadap institusi politik, serta keterbatasan ruang untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam sistem demokrasi. Di sinilah letak pertanyaannya—apakah generasi ini akan menjadi agen perubahan nyata, atau justru terjebak dalam peran simbolik yang tidak berdampak?
Bukan Sekadar Pemilih, Tapi Penentu Arah Politik
Selama ini, keterlibatan politik generasi muda, termasuk Generasi Z, masih sering dipahami sebatas pada aktivitas pemungutan suara. Padahal, dalam sistem demokrasi yang sehat, partisipasi politik tidak boleh berhenti di bilik suara. Generasi muda seharusnya dilibatkan secara aktif dalam diskusi publik, pengambilan keputusan, hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Berbagai isu besar—seperti pengangguran, perubahan iklim, ketidakadilan sosial, hingga kesehatan mental—lebih dekat dengan realitas hidup Generasi Z. Namun sayangnya, isu-isu ini kerap dipinggirkan dalam perdebatan politik arus utama. Ini bukan hanya soal ketidakterlibatan, tetapi juga tentang kurangnya ruang yang inklusif bagi pemuda untuk menyuarakan perspektif mereka.
Kekuatan Generasi Z sebagai Agen Perubahan
Generasi Z memiliki sejumlah keunggulan strategis yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Pertama, mereka melek teknologi dan sangat adaptif terhadap perubahan. Kedua, mereka memiliki akses luas ke informasi serta kemampuan menyebarkan pesan secara cepat melalui media sosial. Ketiga, mereka dikenal kritis dan tidak mudah tunduk pada narasi tunggal, sesuatu yang sangat penting dalam era post-truth dan polarisasi politik saat ini.
Gerakan-gerakan sosial seperti #ReformasiDikorupsi atau #BersamaPemuda menunjukkan bahwa ketika Generasi Z bersatu dalam satu isu, mereka bisa menggerakkan opini publik, menekan pemerintah, bahkan mengubah arah kebijakan. Namun, potensi ini hanya akan maksimal jika didukung oleh sistem yang memberi ruang, bukan justru membungkam atau mempolitisasi mereka.
Cara Nyata Generasi Z Berkontribusi dalam Politik
Partisipasi aktif Generasi Z dalam politik tidak harus selalu dilakukan dari dalam sistem (misalnya lewat partai politik atau pencalonan legislatif), tetapi bisa juga melalui jalur-jalur alternatif yang konstruktif dan berdampak:
1. Meningkatkan Literasi Politik Digital
Generasi Z perlu membekali diri dengan pemahaman politik yang kritis—tidak hanya tentang siapa yang harus dipilih, tapi juga bagaimana sistem bekerja, bagaimana kebijakan dibuat, dan siapa yang diuntungkan. Hal ini dapat dimulai dari platform edukatif di media sosial hingga keterlibatan dalam diskusi komunitas.
2. Berperan dalam Gerakan Sosial dan Komunitas
Keterlibatan dalam gerakan lingkungan, keadilan sosial, HAM, atau ekonomi kreatif dapat menjadi cara untuk mendorong perubahan nyata dari akar rumput. Banyak perubahan kebijakan besar dimulai dari tekanan publik yang dimotori anak muda.
3. Mengawasi dan Mengawal Proses Politik
Menjadi pemantau pemilu, membuat inisiatif advokasi digital, atau menciptakan platform transparansi anggaran daerah adalah bentuk keterlibatan politik yang konkret. Generasi Z bisa menjadi pengawas aktif agar politik tidak dikuasai elite semata.
Tantangan yang Harus Diselesaikan
Meski potensinya besar, Generasi Z tidak lepas dari tantangan serius yang bisa menghambat keterlibatan politik mereka:
- Apatinya sebagian kalangan muda, yang merasa politik itu membosankan atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari.
- Minimnya ruang dialog politik yang sehat, yang sering kali dibayang-bayangi polarisasi dan ujaran kebencian.
- Kurangnya representasi generasi muda dalam struktur kekuasaan, yang membuat aspirasi mereka sulit diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak—pemerintah, institusi pendidikan, media, dan masyarakat sipil—untuk menciptakan ekosistem politik yang sehat, inklusif, dan memberdayakan.
Kesimpulan: Politik Masa Depan Ada di Tangan Generasi Z
Generasi Z bukan hanya tumpuan harapan, tapi juga penentu masa depan politik Indonesia. Dengan kekuatan teknologi, keberanian bersuara, dan semangat perubahan, mereka bisa memecah kebuntuan politik lama dan membawa narasi baru yang lebih segar, adil, dan inklusif.
Namun, untuk benar-benar menjadi agen perubahan, Generasi Z tidak cukup hanya menjadi pemilih yang cerdas. Mereka harus terlibat aktif, kritis, dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sejati.
Jika tantangan dihadapi dengan strategi, dan harapan ditopang dengan aksi nyata, maka 2029 bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi tentang bagaimana generasi muda merebut ruangnya dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Penulis: Fitri Sindi
Mahasiswa Semester 1 Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)