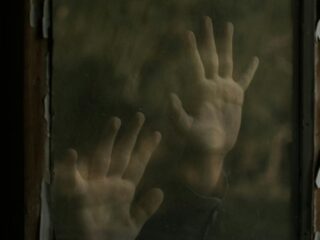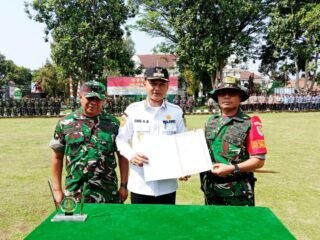Perempuan dan Kemiskinan Struktural: Suara yang Sering Tak Didengar
 Ilustrasi gambar oleh penulis
Ilustrasi gambar oleh penulisOPINI | TD — Kemiskinan di Indonesia sering kali dibicarakan dalam angka—berapa persen menurun, berapa juta orang masih tercatat miskin. Namun, di balik angka-angka itu, jarang sekali muncul pertanyaan yang paling penting: siapa yang paling merasakan dampaknya?
Jawabannya sederhana namun menyakitkan: perempuan.
Di banyak daerah, perempuan menjadi kelompok yang berjuang paling keras untuk bertahan hidup. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, sering kali di sektor informal tanpa upah layak, tanpa jaminan sosial, dan tanpa pengakuan. Dalam banyak kasus, kemiskinan perempuan bukan sekadar soal “tidak punya uang”, melainkan hasil dari sistem sosial dan ekonomi yang sejak awal tidak berpihak pada mereka.
Sistem yang Tidak Pernah Netral
Pandangan umum sering menilai kemiskinan sebagai akibat dari kurangnya kerja keras individu. Padahal, kemiskinan juga bisa lahir dari struktur sosial yang timpang—sebuah kondisi yang disebut kemiskinan struktural.
Dalam sistem ini, perempuan tidak miskin karena malas, tetapi karena hidup dalam struktur yang tidak adil: akses pendidikan terbatas, kesempatan kerja sempit, dan kebijakan publik yang lebih berpihak pada pasar daripada manusia.
Di dunia kerja, perempuan masih dihadapkan pada pilihan yang sempit. Banyak yang bekerja di sektor informal seperti buruh pabrik, pedagang kecil, atau pekerja rumah tangga dengan upah rendah dan tanpa perlindungan hukum. Bahkan ketika mereka bekerja di sektor formal, kesenjangan upah dan ketidakamanan kerja masih menjadi masalah yang menahun.
Neoliberalisme dan Beban Ganda Perempuan
Ketika sistem ekonomi bergeser ke arah neoliberalisme—yang menekankan kebebasan pasar dan mengurangi peran negara—perempuan miskin menjadi korban paling nyata. Negara melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, sementara pasar tidak peduli pada mereka yang tertinggal.
Akibatnya, perempuan miskin menanggung beban ganda: bekerja keras untuk bertahan hidup sekaligus menanggung beban sosial di rumah tangga.
Dalam kerangka neoliberalisme, pembangunan sering kali diukur dari pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemerataan kesejahteraan. Padahal, jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka perempuan miskin akan semakin terpinggirkan dari sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Kondisi Perempuan Miskin di Indonesia
Realitas di lapangan menunjukkan, perempuan masih mendominasi kelompok rentan. Ketimpangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Akibatnya, banyak perempuan bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial dan rentan terhadap eksploitasi.
Masalah ini membuktikan bahwa kemiskinan perempuan tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi, tetapi juga dari kebijakan pembangunan yang masih bias gender dan belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial.
Pemberdayaan Perempuan: Kunci Mengubah Struktur
Pemberantasan kemiskinan perempuan tidak cukup hanya dengan bantuan ekonomi sesaat. Diperlukan perubahan struktural melalui kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang.
Pemerintah harus memastikan perempuan memiliki akses setara terhadap pendidikan, pelatihan kerja, modal usaha, dan perlindungan sosial.
Program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelatihan keterampilan, literasi keuangan, serta dukungan bagi usaha mikro, dapat menjadi langkah awal menuju kemandirian. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan organisasi perempuan perlu terus mengawal agar kebijakan publik benar-benar mempertimbangkan kepentingan perempuan miskin, bukan sekadar menjadi jargon pembangunan.
Kesimpulan: Dari Objek Menjadi Subjek Pembangunan
Kemiskinan perempuan bukanlah masalah individu, melainkan produk dari sistem sosial yang timpang dan kebijakan yang gagal menjamin keadilan. Perempuan tidak boleh terus diposisikan sebagai “penanggung beban”, melainkan sebagai penggerak perubahan.
Pendidikan yang merata, pekerjaan yang layak, dan jaminan sosial yang inklusif adalah kunci agar perempuan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan struktural. Ketika perempuan berdaya, maka masyarakat secara keseluruhan ikut maju.
Sudah saatnya negara mendengar suara yang selama ini terpinggirkan—suara perempuan miskin yang menjadi saksi nyata ketidakadilan sosial di negeri sendiri.
Penulis: Siti Nita Rohayati
Mahasiswa Semester 1, Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA. (*)