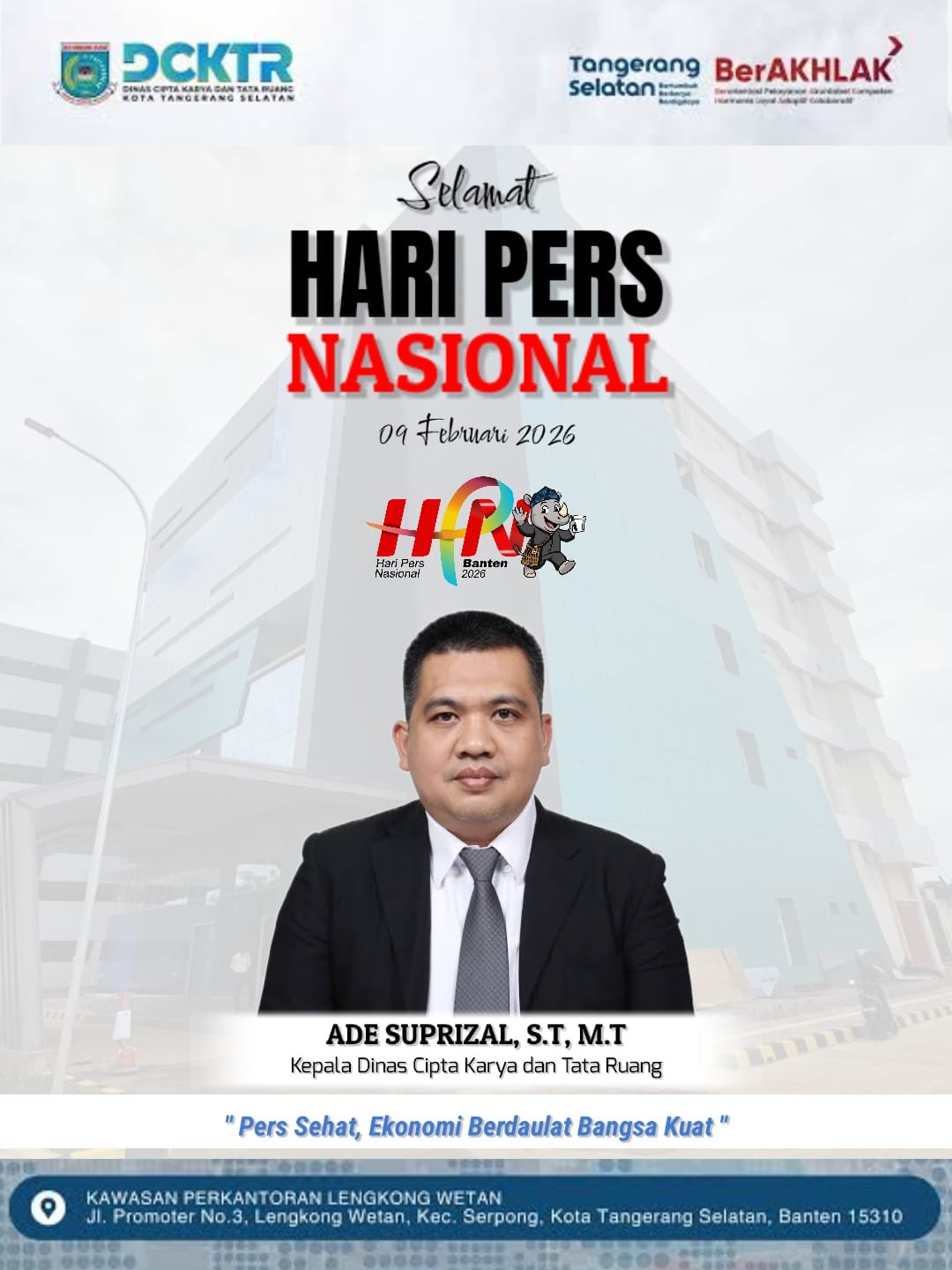Neo-Salafisme: Jalan Tengah Menghadapi Politisasi Agama di Indonesia
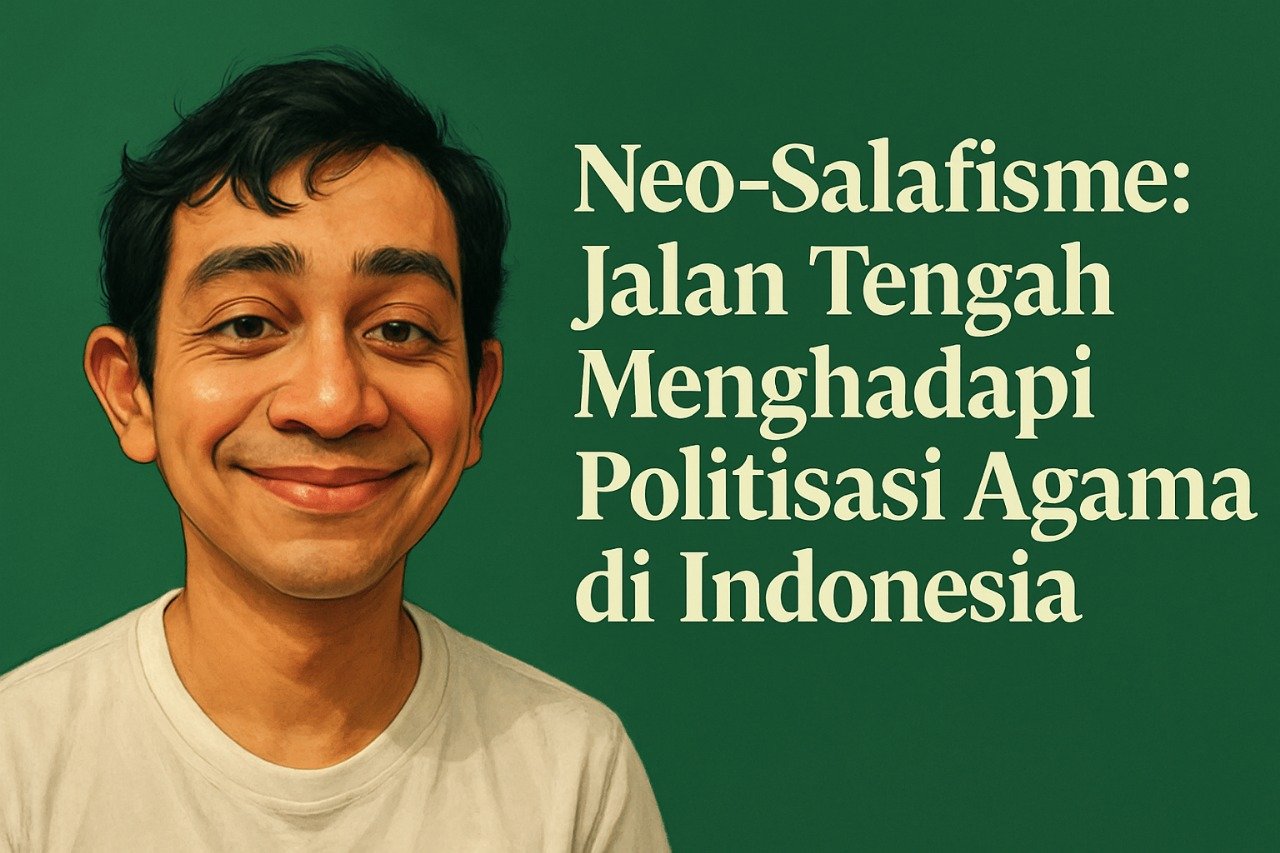 Ilustrasi: Rekayasa gambar menggunakan kecerdasan buatan (AI)
Ilustrasi: Rekayasa gambar menggunakan kecerdasan buatan (AI)OPINI | TD — Di tengah meningkatnya politisasi agama dalam kontestasi demokrasi Indonesia, muncul kebutuhan akan sebuah pendekatan keagamaan yang mamp u menjaga kemurnian ajaran sekaligus menegakkan rasionalitas publik. Neo-Salafisme hadir sebagai jalan tengah: bukan gerakan politik, melainkan upaya intelektual dan spiritual untuk memisahkan kesucian agama dari kepentingan elektoral tanpa menolak pentingnya partisipasi politik umat Islam.
Politik Identitas dan Krisis Rasionalitas Publik
Dalam dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi gelombang besar politisasi agama. Agama, yang seharusnya menjadi sumber etika dan moralitas publik, justru dijadikan alat politik praktis. Narasi seperti “memilih kandidat tertentu akan masuk surga, sementara yang menolak akan masuk neraka” mencerminkan betapa dangkalnya pemahaman politik sebagian elite. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik identitas telah mengikis rasionalitas publik.
Bagi sebagian politisi, agama adalah modal politik yang mudah dijual. Mereka memanfaatkan simbol, jargon, dan figur ulama untuk meraih legitimasi. Akibatnya, masyarakat sering terjebak dalam polarisasi semu di mana pilihan politik dianggap sebagai cerminan keimanan. Padahal, Islam menegaskan bahwa memilih pemimpin adalah urusan duniawi yang harus dilandasi pertimbangan maslahat, keadilan, dan kapasitas — bukan janji spiritual palsu yang menentukan surga dan neraka.
Neo-Salafisme sebagai Gerakan Pemurnian dan Rasionalisasi Agama
Dalam konteks tersebut, Neo-Salafisme hadir bukan sebagai ideologi politik, melainkan sebagai gerakan pemikiran yang berupaya memurnikan agama dari distorsi kepentingan duniawi. Neo-Salafisme menekankan pentingnya kembali kepada sumber utama ajaran Islam — Al-Qur’an dan Sunnah yang sahih — serta rasionalitas dalam memahami keduanya.
Pendekatan ini menempatkan agama sebagai pedoman moral, bukan instrumen politik. Neo-Salafisme berfungsi sebagai filter epistemologis yang membantu umat membedakan antara ajaran Islam yang autentik dan narasi politik yang manipulatif. Dengan prinsip tabayyun (klarifikasi) dan dalil sahih, umat didorong untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh propaganda berbasis agama.
Lima Tantangan dan Jawaban Neo-Salafisme
- Politik Identitas yang Mengikis Rasionalitas
Studi Marcus Mietzner (2018) menunjukkan bahwa politik identitas memperlemah nalar publik. Neo-Salafisme menanggapi hal ini dengan menegaskan bahwa ukuran pemimpin adalah keadilan dan amanah, bukan klaim keagamaan. Meski begitu, pendekatan ini harus dijaga agar tidak berubah menjadi eksklusif. - Manipulasi Teologis dalam Kampanye
Narasi “memilih calon tertentu sebagai jalan ke surga” merupakan bentuk penyimpangan (Van Bruinessen, 2013). Neo-Salafisme menawarkan kritik berbasis ilmu dan nash yang sahih agar umat lebih rasional dalam memahami teks agama. - Degradasi Demokrasi oleh Sentimen Agama
Fealy & White (2022) menegaskan bahwa Islam politik cenderung mempersempit ruang demokrasi. Neo-Salafisme justru mengingatkan bahwa politik adalah urusan maslahat duniawi, bukan perihal iman atau keselamatan akhirat. - Komersialisasi Simbol Agama
Prof. Noorhaidi Hasan (2021) memperingatkan bahaya komersialisasi simbol agama seperti jilbab, masjid, atau majelis taklim. Neo-Salafisme menolak praktik tersebut dengan mengembalikan nilai-nilai agama kepada kesucian aslinya. - Kebingungan dalam Memilah Otoritas
Banyak umat sulit membedakan otoritas religius dan politik (Jamhari & Van Bruinessen, 2018). Neo-Salafisme mengajarkan prinsip tabayyun agar umat tidak mudah tertipu oleh otoritas yang mengatasnamakan agama demi kepentingan kekuasaan.
Solusi dan Relevansi Neo-Salafisme di Indonesia
Neo-Salafisme tidak menolak demokrasi, tetapi menolak politisasi agama yang menyesatkan. Relevansinya di Indonesia sangat kuat, karena masyarakat Muslim sering menjadi target manipulasi elektoral. Untuk menjaga keseimbangan antara kemurnian ajaran dan keterbukaan sosial, gerakan ini perlu mengembangkan strategi dakwah dan pendidikan politik yang inklusif.
Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:
- Mendorong majelis taklim Neo-Salafi yang mengajarkan literasi politik Islam berbasis dalil sahih.
- Mengembangkan gerakan literasi digital untuk menangkal hoaks dan propaganda agama dalam kampanye.
- Menyuarakan kritik terbuka terhadap politisasi agama melalui ulama dan akademisi Muslim.
- Memperkuat kolaborasi antara ulama dan intelektual untuk menjaga rasionalitas publik dan keutuhan umat.
Kesimpulan
Neo-Salafisme menawarkan paradigma baru bagi umat Islam Indonesia: mengembalikan agama pada fungsi moralnya tanpa menafikan realitas politik. Dengan menolak politisasi agama, gerakan ini menjaga kesakralan Islam sekaligus memperkuat rasionalitas publik dalam berdemokrasi.
Indonesia membutuhkan pemilih yang cerdas, bukan fanatik buta. Pemimpin yang baik dipilih karena kapasitas, integritas, dan keadilan, bukan karena retorika religius yang menyesatkan. Neo-Salafisme, jika dijalankan secara bijak, dapat menjadi jalan tengah yang memadukan kemurnian ajaran dengan komitmen kebangsaan, menjaga harmoni sosial, dan memperkuat kualitas demokrasi di negeri yang plural ini.
Penulis: Raden Raja Arya Rahman Natakusumah, mahasiswa semester 1 mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta. (*)