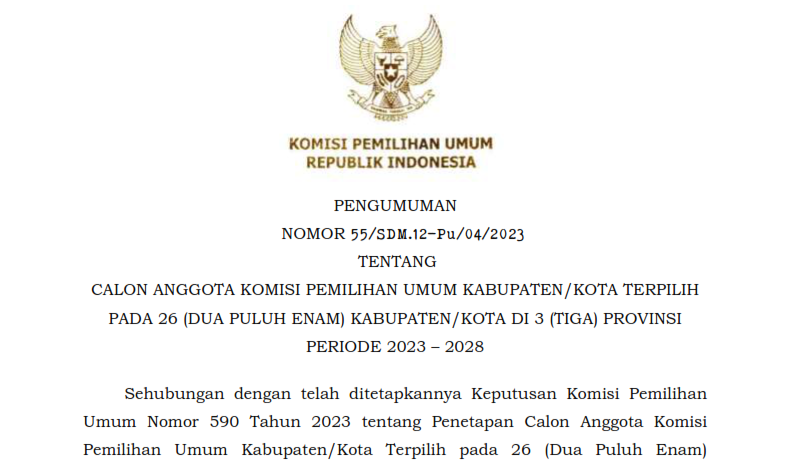Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas
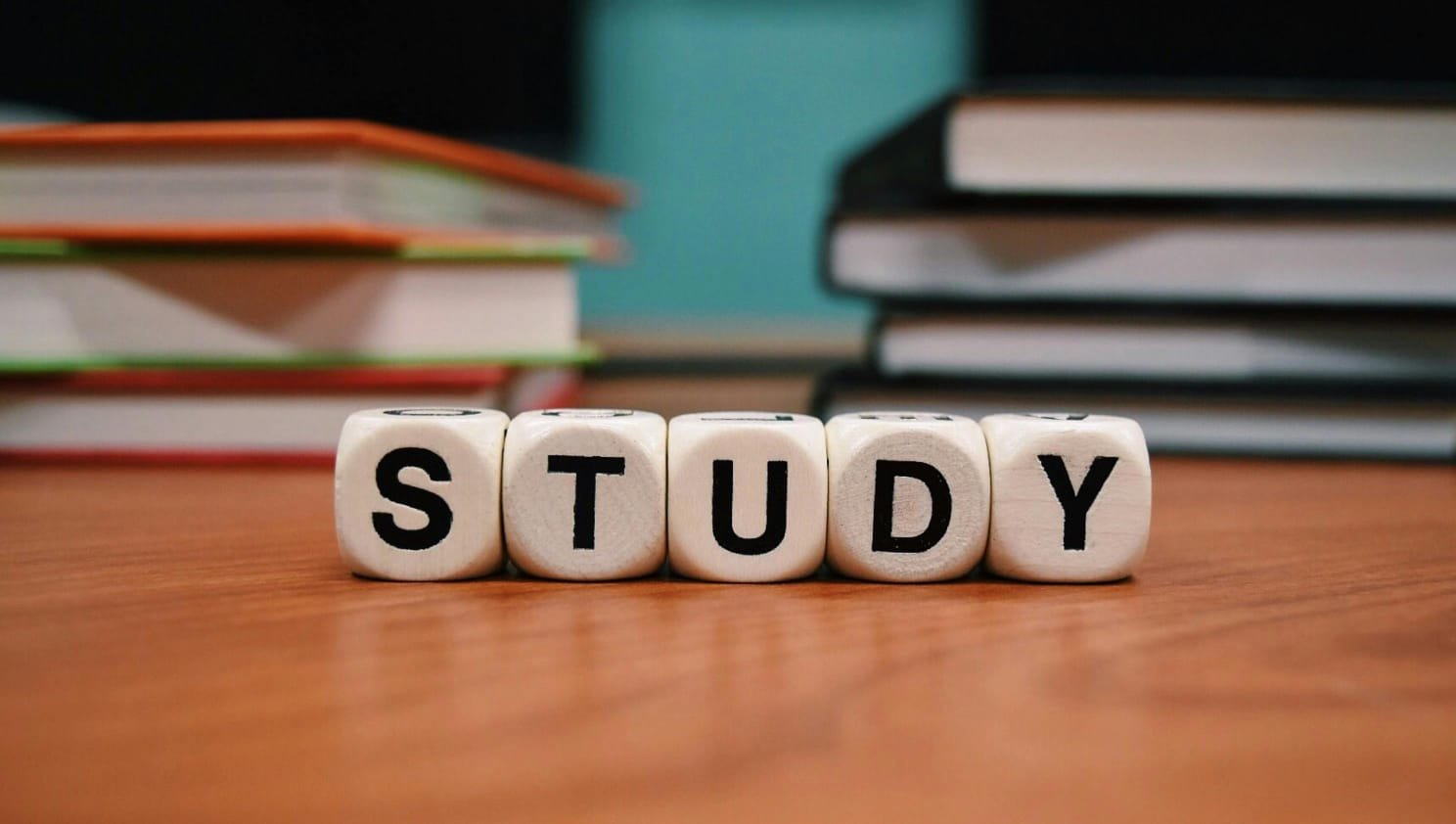 Ilustrasi (Foto: Pixabay)
Ilustrasi (Foto: Pixabay)OPINI | TD — Indonesia memiliki kerangka hukum pendidikan yang cukup komprehensif, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah. Namun, keberadaan regulasi yang melimpah ini belum cukup menjamin terwujudnya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Artikel opini ini akan mengkaji kesenjangan antara landasan hukum yang ideal dengan realitas implementasinya di lapangan, serta mengusulkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
UUD 1945, sebagai hukum tertinggi, mengamanatkan negara untuk memajukan pendidikan nasional. Amanat ini diperinci lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pendidikan, mulai dari jenjang, kurikulum, hingga pendanaan. Namun, keberadaan regulasi yang detail ini seringkali terbentur oleh realitas sosial dan ekonomi yang kompleks.
Salah satu permasalahan krusial adalah implementasi wajib belajar 9 tahun. Meskipun UU No. 20 Tahun 2003 mewajibkan pendidikan dasar bagi anak usia 5-7 tahun, realitasnya masih banyak anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Faktor kemiskinan, lokasi geografis yang terpencil, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi beberapa penyebab utama. Wajib belajar semata-mata hanya akan menjadi slogan jika tidak diiringi dengan upaya konkrit untuk mengatasi akar permasalahan tersebut.
Bukankah ironis jika sebuah negara memiliki regulasi yang baik, tetapi masyarakatnya masih kekurangan akses terhadap pendidikan?
Permasalahan lain muncul dari lemahnya penegakan hukum. Sanksi yang kurang tegas bagi pihak-pihak yang menghambat akses pendidikan, seperti pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur, membuat regulasi menjadi kurang efektif. Keberadaan peraturan yang “ompong” ini membuat upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi setengah hati.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak semata-mata terletak pada revisi undang-undang, melainkan pada pendekatan holistik yang melibatkan berbagai stakeholder.
Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Kampanye edukasi yang efektif mampu menumbuhkan kesadaran dan mengubah persepsi masyarakat tentang nilai pendidikan.
Kedua, koordinasi antar lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil sangat penting. Kerjasama yang sinergis akan memudahkan dalam pendistribusian sumber daya dan pengawasan implementasi program pendidikan.
Ketiga, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pendidikan harus ditegakkan. Sanksi yang berat akan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba melanggar aturan.
Keempat, pemerintah perlu fokus pada pemerataan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil. Program beasiswa, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan pelatihan guru di daerah terpencil merupakan beberapa langkah yang dapat diambil.
Kelima, pembinaan mental dan karakter peserta didik harus menjadi prioritas. Pendidikan karakter yang baik akan membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.
Penutup
Kesimpulannya, landasan hukum pendidikan di Indonesia sudah cukup memadai. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasinya di lapangan.
Keberhasilan pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada komitmen dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hanya dengan demikian, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud.
Penulis: Meisya Ratu Arifia, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)