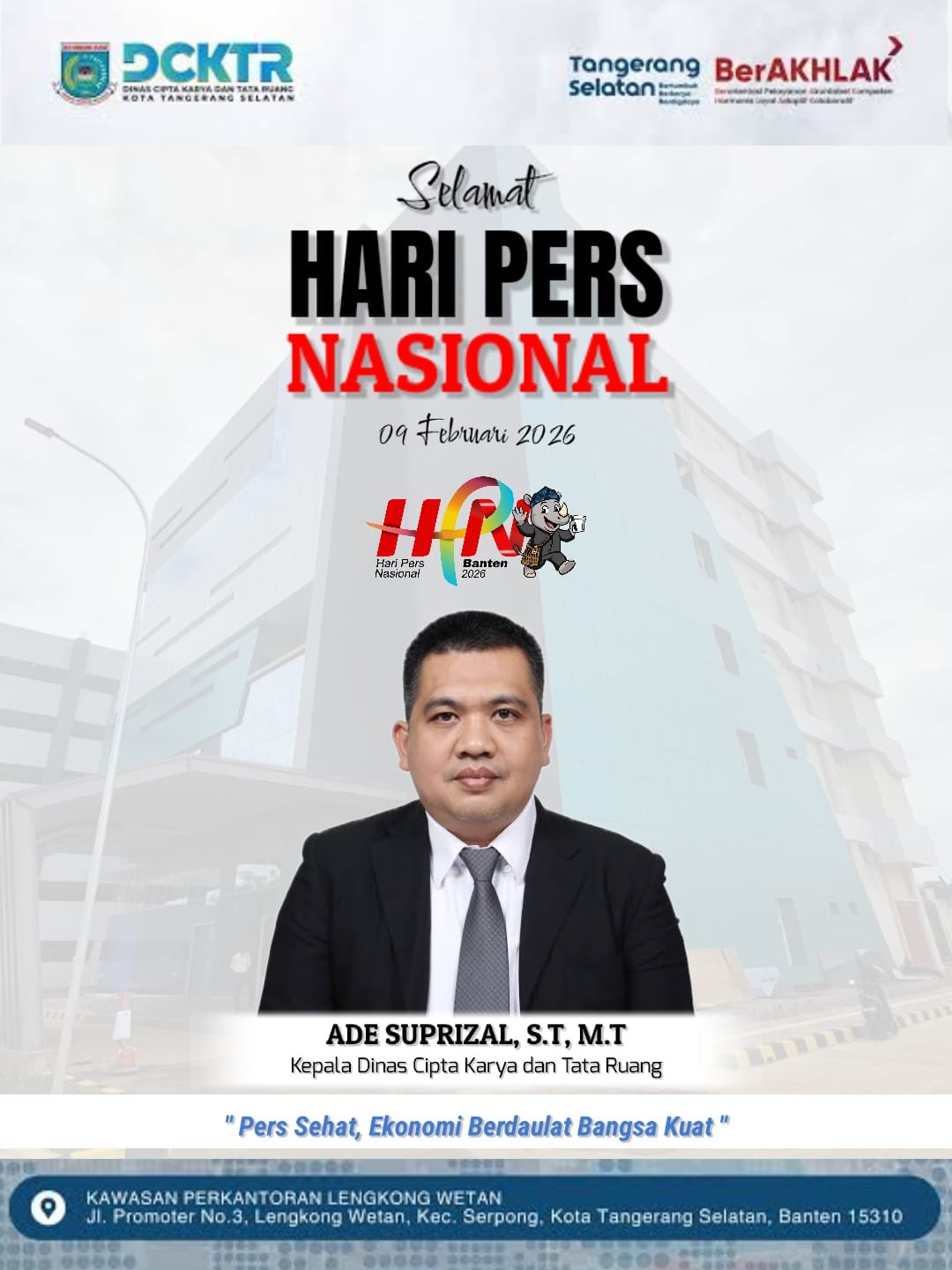Ketika Kekuasaan Jadi Warisan: Analisis Politik Indonesia Pasca 2024
 Ilustrasi: gambar dibuat dengan rekayasa menggunakan kecerdasan buatan.
Ilustrasi: gambar dibuat dengan rekayasa menggunakan kecerdasan buatan.OPINI | TD — Pemilu 2024 seharusnya menjadi momentum konsolidasi demokrasi Indonesia setelah satu dekade pemerintahan yang kuat. Namun realitas politik berkata lain. Alih-alih menghasilkan transisi kepemimpinan yang segar dan terbuka, kita justru menyaksikan bagaimana kekuasaan mulai diperlakukan layaknya warisan—diturunkan secara sistematis melalui jaringan politik, afiliasi keluarga, dan pengaruh personal seorang presiden yang belum sepenuhnya bersedia melepas panggung.
Fenomena ini menandai fase baru dalam dinamika demokrasi Indonesia: ketika proses elektoral tetap berjalan, tetapi esensinya mulai digerogoti oleh praktik-praktik elitis. Pasca 2024, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara kontinuitas pemerintahan dan komitmen terhadap demokrasi yang inklusif, adil, dan akuntabel.
Jokowi sebagai Kingmaker: Melepas Jabatan, Mempertahankan Pengaruh
Pasca berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, perannya dalam panggung politik nasional justru tidak meredup. Sebaliknya, ia tampil sebagai kingmaker—aktor yang secara aktif menentukan arah kekuasaan, termasuk dengan mendukung pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.
Dukungan Jokowi terhadap Gibran bukanlah sekadar soal kekeluargaan, melainkan bagian dari strategi politik yang lebih besar: menjaga kesinambungan agenda kekuasaan, memperluas pengaruh, dan memastikan posisi tawar dalam konfigurasi pasca-kepemimpinan. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pengaruh pribadi boleh memainkan peran dalam sistem politik yang mengaku demokratis?
Politik Dinasti: Mewarnai Demokrasi atau Mencemari?
Pencalonan Gibran memicu diskursus nasional tentang politik dinasti. Meski tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini mereduksi demokrasi menjadi permainan akses dan koneksi—di mana kekuasaan tidak lagi diperebutkan secara terbuka oleh warga negara, tetapi diwariskan dalam lingkaran keluarga dan elite tertentu.
Kondisi ini mempersempit ruang kompetisi, menghambat regenerasi politik yang sehat, dan merusak prinsip meritokrasi. Demokrasi seharusnya membuka jalan bagi siapa saja yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk memimpin. Namun, politik dinasti menciptakan lapisan eksklusif yang hanya dapat ditembus oleh mereka yang “bernama besar”.
Warisan IKN: Ambisi Modernisasi di Tengah Kritik Demokratis
Salah satu warisan paling ambisius dari era Jokowi adalah proyek pemindahan ibu kota negara (IKN). Proyek ini digadang-gadang sebagai simbol transformasi menuju Indonesia yang lebih modern dan terdesentralisasi. Namun, pelaksanaannya justru menampilkan wajah lama pembangunan: minim partisipasi, tertutup terhadap kritik, dan rawan konflik kepentingan.
IKN adalah cermin bagaimana kebijakan strategis dirancang dan dijalankan dengan logika kekuasaan yang sentralistik. Ketika aspirasi masyarakat sipil terpinggirkan, dan proses pengambilan keputusan dikuasai oleh elite, maka proyek sebesar apa pun kehilangan legitimasi sosial.
Polarisasi dan Penyempitan Ruang Demokrasi
Situasi politik pasca 2024 juga ditandai oleh polarisasi tajam dan penyempitan ruang demokrasi. Koalisi penguasa memanfaatkan kekuatan institusional dan media untuk mempertahankan dominasi, sementara oposisi mengalami pelemahan politik dan marjinalisasi.
Ruang debat publik menyusut, kritik sering kali dibungkam, dan jurnalisme independen menghadapi tekanan. Dalam kondisi ini, demokrasi prosedural tetap berjalan—pemilu tetap diselenggarakan—tetapi demokrasi substansial yang menjamin kebebasan berpikir dan partisipasi bermakna, semakin menipis.
Kesimpulan: Menimbang Masa Depan Demokrasi Indonesia
Pasca 2024, Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan. Di sisi lain, ada tuntutan untuk memperbaiki kualitas demokrasi, memperluas partisipasi, dan mengakhiri dominasi elite politik yang terus-menerus memonopoli ruang kekuasaan.
Ketika kekuasaan mulai diperlakukan sebagai warisan, demokrasi kehilangan ruhnya. Maka tantangan ke depan bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana sistem ini dijaga agar tetap memberi ruang yang adil bagi semua warga negara. Demokrasi sejati bukan hanya tentang menang dalam pemilu, tetapi tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab, keterbukaan, dan kesetaraan.
Penulis: Rini Septiani, Mahasiswa Semester 1, Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)