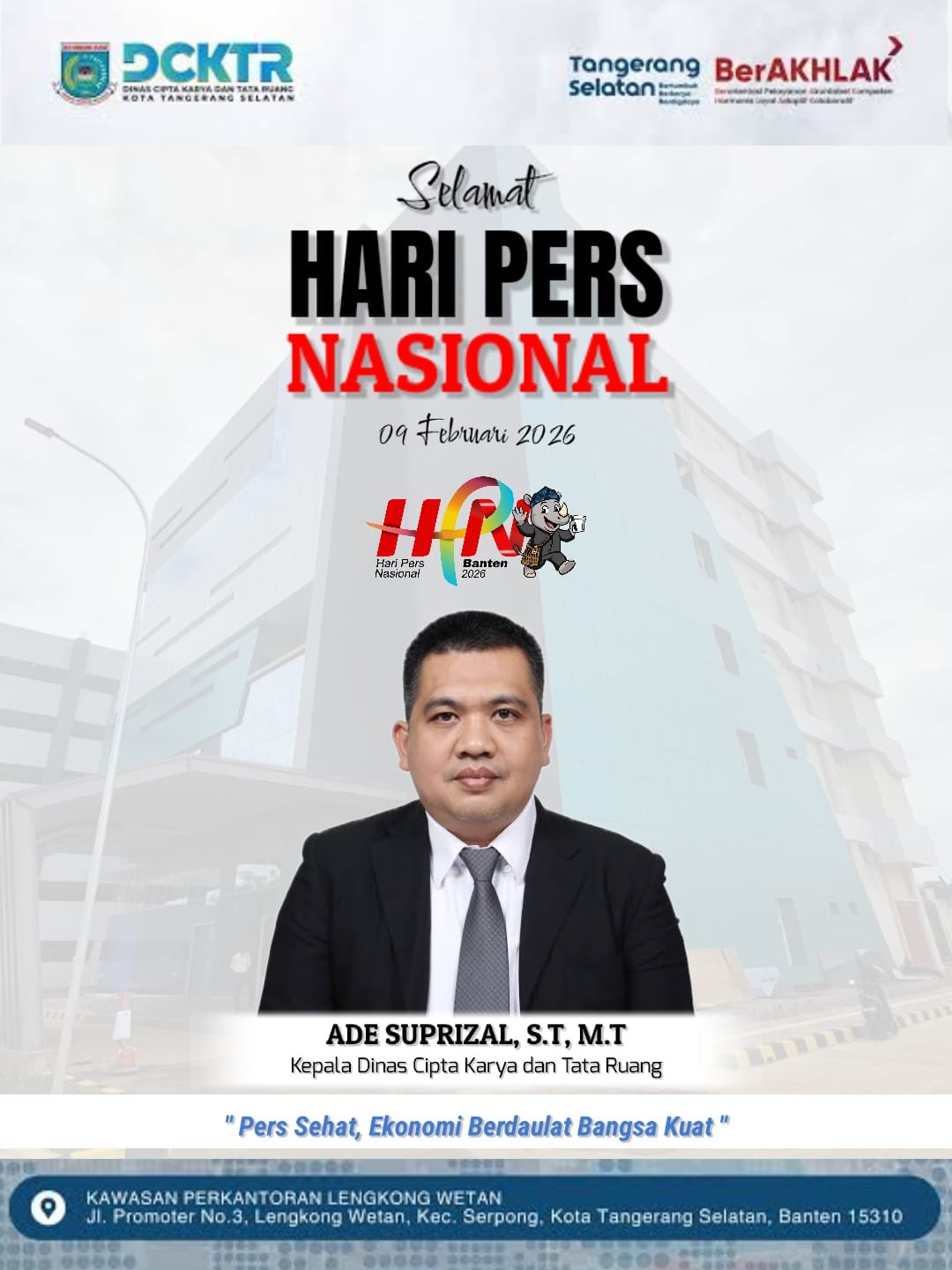Hegemoni Narasi Elite dalam Sistem Media dan Implikasinya
 Ilustrasi untuk hegemoni narasi elit. (Foto: Freepik)
Ilustrasi untuk hegemoni narasi elit. (Foto: Freepik)OPINI | TD — Pers yang bebas seharusnya menjadi fondasi demokrasi. Namun, bagaimana jika ruang kebebasan itu dikendalikan oleh segelintir pemilik modal dan elite politik? Di Indonesia, peta kepemilikan media menunjukkan konsentrasi yang semakin mengkhawatirkan. Alih-alih menyampaikan informasi netral, media kini menjadi alat kepentingan bagi mereka yang berkuasa.
Laporan SAFEnet tahun 2023 mencatat bahwa enam konglomerat menguasai lebih dari 90 persen media televisi nasional. Tokoh-tokoh seperti Surya Paloh (Metro TV), Hary Tanoesoedibjo (MNC Group), dan Chairul Tanjung (Trans Media) menjadi contoh bahwa media bukan sekadar alat komunikasi massa, tetapi juga senjata politik. Ini membuktikan bahwa narasi publik kini sangat mungkin dibentuk dari balik ruang rapat korporasi, bukan dari aspirasi masyarakat luas.
John D. H. Downing dalam The Handbook of Political Economy of Communications menyebut kondisi ini sebagai bentuk “konsentrasi kepemilikan media,” sebuah mekanisme di mana akses atas informasi dikendalikan oleh segelintir pihak, dan itu berdampak langsung pada cara publik melihat realitas. Ketika informasi hanya lahir dari sumber terbatas, maka perspektif pun ikut menyempit. Ini berbahaya dalam demokrasi.
Media Jadi Alat Pengaruh
Konsentrasi media memiliki implikasi langsung terhadap kualitas demokrasi. Misalnya, pada momentum Pemilu 2024, tampak jelas bagaimana media cenderung mengangkat tokoh atau koalisi tertentu. Objektivitas jurnalistik menjadi komoditas langka; yang dominan justru adalah pencitraan, penggiringan opini, dan pengaburan fakta.
Graham Murdock, dalam kajian ekonomi-politik komunikasi, menyebut bahwa relasi antara media dan kekuasaan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal moral. Ketika informasi dijadikan komoditas, maka nilai yang dominan bukan lagi kebenaran atau kepentingan publik, melainkan kepentingan ekonomi dan politik pemiliknya. Masyarakat pun tereduksi hanya sebagai konsumen, bukan warga negara yang memiliki hak deliberatif dalam wacana publik.
Faktanya, praktik ini membuat demokrasi berjalan pincang. Proses politik yang seharusnya melibatkan warga secara aktif malah berubah menjadi tontonan yang dikendalikan dari balik layar. Analisis kritis di sini menunjukkan bahwa dominasi media bukan hanya persoalan kepemilikan, tetapi juga tentang monopoli atas makna.
Buzzer, Algoritma, dan Disinformasi
Di era digital, kendali atas wacana publik tak hanya berlangsung di ruang redaksi, tetapi juga di media sosial. Buzzer politik menjadi instrumen baru yang memperluas kontrol elite atas persepsi publik. Mereka menyebarkan narasi-narasi yang bias dan kadang mengandung disinformasi, dibungkus seolah sebagai opini organik warga.
Penelitian Boy Anugerah (2020) menunjukkan bahwa sejak 2014, buzzer sudah menjadi bagian dari strategi politik formal, terutama dalam pemilu. Bahkan, beberapa dari mereka digandeng oleh pemerintah dalam agenda komunikasi resmi. Namun hingga kini, tak ada regulasi yang mengatur keberadaan dan aktivitas mereka. Ini membuka ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan.
Dampaknya, ruang digital yang seharusnya menjadi arena demokratis justru berubah menjadi ruang gaduh yang penuh manipulasi. Informasi bohong menyebar lebih cepat dari klarifikasi. Suara kritis dibungkam oleh amplifikasi buzzer. Dalam konteks ini, media sosial bukannya menjadi sarana demokratisasi informasi, tetapi justru memperkuat dominasi elite.
Perlu Jalur Alternatif
Supaya situasi ini tidak semakin parah, perlu ada langkah serius. Pertama, pemerintah harus membenahi regulasi kepemilikan media. Jangan ada lagi satu grup yang bisa memiliki banyak saluran sekaligus. Transparansi juga penting, agar masyarakat mengetahui siapa di balik layar pemberitaan. Kedua, komunitas media dan independen harus didukung. Mereka bisa menjadi penyeimbang sekaligus ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini tidak terwakili.
Selain itu, masyarakat juga harus semakin melek media. Bukan hanya soal bisa membaca berita, tetapi juga paham bagaimana framing dibentuk, bisa mengenali bias, dan tahu bedanya antara berita asli dan propaganda.
Karena pada akhirnya, media bukan hanya saluran informasi tetapi juga arena pertarungan makna. Jika medan ini hanya dikuasai oleh elit dan buzzer, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung pura-pura. Pertanyaannya sekarang: siapa yang punya suara, dan siapa yang sengaja dibungkam?
Saatnya masyarakat mengambil bagian. Dukung media yang independen, lawan narasi yang berat sebelah, dan terus kritis. Karena, demokrasi sejatinya bukan milik segelintir orang, tetapi milik kita bersama.
Penulis: Irene Cantika Siahaan, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Editor: Patricia
—-
Daftar Pustaka
1. Anugerah, B. (2020). Buzzer politik dan disinformasi dalam kontestasi elektoral di Indonesia.
2. Downing, J. D. H. (Ed.). (2011). The Handbook of Political Economy of Communications. Wiley-Blackwell.
3. Murdock, G., & Golding, P. (2005). Culture, communications and political economy. Dalam J. Curran & M. Gurevitch (Eds.), Mass Media and Society (hal. 60–83). Hodder Arnold.
4. SAFEnet. (2023). Laporan tahunan: Konsentrasi kepemilikan media dan ancaman terhadap demokrasi. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).