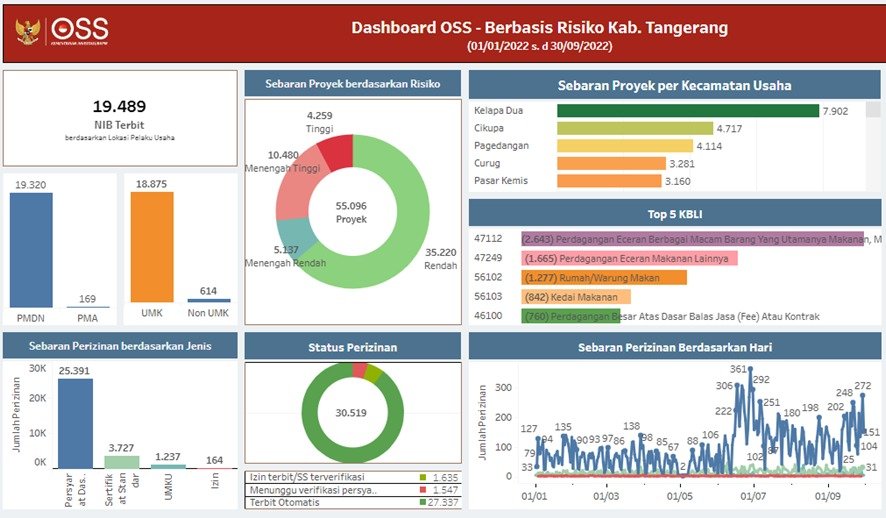Catatan Pertandingan Seorang Hamba
 Ilustrasi foto dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan oleh TangerangDaily.
Ilustrasi foto dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan oleh TangerangDaily.PRISMA | TD — Aku ini cuma seorang pemain di lapangan hidup:
tugasnya sederhana—
menyentuh bola, mengoper, menendang seperlunya.
Aku bukan pemilik lapangan,
bukan pengatur jam dan skor.
Aku hanya diberi kesempatan
bermain sebentar di antara dua peluit:
awal dan akhir.
Kadang tugasku terdengar sepele,
tapi rasanya berat di dada:
berusaha mencetak “gol-gol kebaikan”
di waktu yang sempit,
atau setidaknya bertahan
supaya gawang hatiku
tidak jebol oleh serangan keburukan
yang datang diam-diam
dari hal-hal kecil:
komentar, pilihan, kebiasaan,
yang sering kusangka remeh.
Di tengah pujian yang bikin lupa diri
dan hinaan yang bikin goyah,
aku sering keliru mengira:
kupikir stadion ini milikku,
padahal aku hanya numpang lewat.
Kupikir orang-orang yang menonton hidupku
harus selalu senang padaku,
padahal mereka juga sibuk
dengan pertandingan mereka sendiri.
Kupikir bola yang sedang kugenggam
akan selalu bersamaku,
padahal ia bisa saja pindah
ke kaki orang lain
kapan saja Tuhan menghendaki.
Pelan-pelan aku sadar:
tak ada yang benar-benar kugenggam di dunia ini.
Lapangan, penonton, bola, suara sorak,
semua hanya titipan sementara.
Yang tetap hanyalah Dia
yang mengizinkan aku bermain
dan suatu hari nanti
akan memanggilku keluar dari lapangan.
Dan pada akhirnya,
peluit terakhir akan ditiup juga.
Pertandinganku selesai.
Lampu-lampu stadion dimatikan,
satu per satu bangku penonton kosong,
nama-nama besar di punggung kaos
tak ada artinya lagi.
Saat itu aku pulang,
tanpa membawa bola,
tanpa kaos bernomor nama besar,
tanpa sorak-sorai siapa pun.
Yang tersisa hanya satu pertanyaan penting:
seperti apa catatan pertandinganku di sisi-Nya?
Bukan berapa banyak aku dipuji,
bukan seberapa sering aku disorot,
tapi:
berapa kali aku menahan diri saat bisa membalas?
berapa kali aku memilih jujur saat mudah untuk curang?
berapa kali aku tetap baik
saat tak ada yang melihat?
Aku membayangkan datang kepada-Nya
dengan seragam yang kotor,
napas yang tersengal,
kaki yang penuh luka,
lalu berkata pelan dalam hati:
“Tuhan, beginilah aku pulang.
Bukan sebagai pemain terbaik,
bukan sebagai juara yang dielu-elukan.
Aku pulang sebagai hamba
yang banyak salah,
sering lalai,
tapi sungguh ingin Kau maafkan.
Jika tak layak diberi piala,
setidaknya izinkan aku
Engkau terima
sebagai pemain lelah
yang ingin hatinya bersih
ketika akhirnya
sampai di hadapan-Mu.”
Tangerang, 24 November 2025
Al Faqir (*)