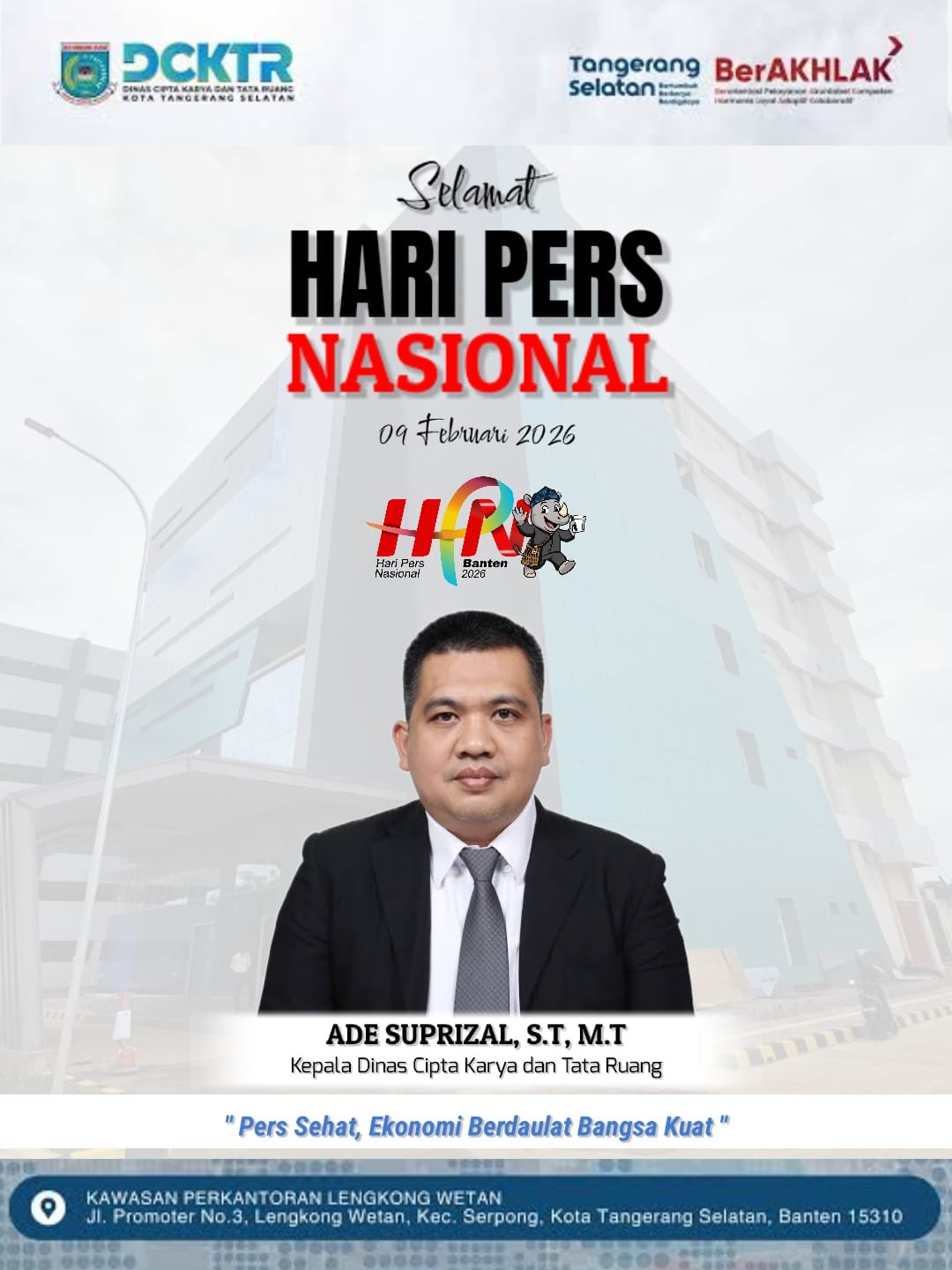Bansos: Mensejahterakan Rakyat atau Melanggengkan Kemiskinan Struktural?
 Adam Arsyad, Mahasiswa Semester 1, Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA. (Foto: Dok. Pribadi)
Adam Arsyad, Mahasiswa Semester 1, Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA. (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD – Bantuan sosial (bansos) sejatinya dirancang sebagai instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat, terutama kelompok miskin dan rentan. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini kerap menuai perdebatan: apakah bansos benar-benar mengentaskan kemiskinan, atau justru menciptakan ketergantungan baru yang melanggengkan kemiskinan struktural? Pertanyaan ini menjadi penting di tengah meningkatnya politisasi bansos dalam dinamika kebijakan publik di Indonesia.
Bansos sebagai Instrumen Kesejahteraan
Secara konseptual, bansos memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Pertama, ia berfungsi sebagai social safety net bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana. Bantuan tunai, sembako, hingga subsidi kebutuhan pokok menjadi penyelamat bagi banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Kedua, bansos berperan menjaga daya beli masyarakat, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa program bansos berkontribusi dalam menahan lonjakan angka kemiskinan ekstrem serta menjaga perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Ketiga, bansos juga menjadi sarana redistribusi keadilan sosial. Pajak yang dikumpulkan dari kelompok mampu disalurkan kembali kepada masyarakat kurang mampu—sebuah wujud konkret dari fungsi negara sebagai agen kesejahteraan dan pemerataan.
Ketika Bansos Menjadi Alat Politik
Namun, realitas di lapangan menunjukkan sisi lain yang problematik. Dalam praktik politik, bansos sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen pencitraan dan legitimasi kekuasaan. Fenomena ini umumnya meningkat menjelang pemilu, ketika penyaluran bantuan kerap disertai simbol dan narasi politik tertentu.
Alih-alih berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat, distribusi bansos kadang ditentukan oleh kedekatan politik. Dampaknya, bansos tidak lagi menjadi alat pemberdayaan, melainkan alat ketergantungan. Masyarakat miskin ditempatkan sebagai penerima pasif, bukan pelaku aktif pembangunan.
Lebih parah lagi, berbagai kasus korupsi bansos yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi dalam program sosial bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menodai nilai moral dari keadilan sosial itu sendiri.
Pisau Bermata Dua
Bansos adalah ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi sarana kesejahteraan jika dijalankan dengan adil, transparan, dan berkelanjutan. Namun, ia juga bisa menjadi alat pemiskinan struktural jika disalurkan tanpa pemberdayaan dan hanya berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek.
Dalam perspektif teori dependency, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang bersifat konsumtif justru memperlemah kemampuan mereka untuk mandiri. Ketika negara hanya “memberi ikan” tanpa “mengajarkan cara memancing”, kemiskinan akan terus direproduksi dari generasi ke generasi.
Reformasi Kebijakan Bansos
Agar bansos benar-benar membawa kesejahteraan, beberapa langkah reformasi perlu ditempuh:
- Transparansi dan Akuntabilitas – Penyaluran bansos harus berbasis data yang valid, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi.
- Integrasi dengan Pemberdayaan Ekonomi – Bantuan perlu dikaitkan dengan pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses kerja agar masyarakat mampu mandiri.
- Penguatan Ekonomi Lokal – Bansos produktif seperti modal usaha mikro jauh lebih berdampak dibanding bantuan konsumtif jangka pendek.
- Depolitisasi Bansos – Penyaluran bantuan sosial wajib steril dari kepentingan politik elektoral. Negara hadir untuk rakyat, bukan untuk elite.
Penutup
Politik bansos adalah kenyataan yang tak terhindarkan dalam sistem demokrasi. Namun, apakah ia menjadi sarana kesejahteraan atau alat pemiskinan sangat bergantung pada integritas dan niat politik penguasa. Bila dijalankan dengan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan, bansos akan menjadi pijakan menuju masyarakat sejahtera. Sebaliknya, jika terus dipolitisasi, ia hanya akan memperpanjang rantai kemiskinan dan ketimpangan.
Masa depan bansos seharusnya diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian rakyat—agar masyarakat tidak sekadar “dibantu untuk bertahan hidup”, tetapi diberdayakan untuk hidup lebih baik.
Penulis: Adam Arsyad
Mahasiswa Semester 1, Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA. (*)