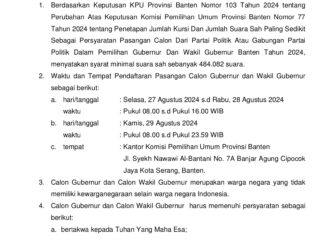Artis dan Politisi: Ketika Panggung Hiburan Menjadi Panggung Kekuasaan
 Ilustrasi dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) oleh penulis.
Ilustrasi dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) oleh penulis.OPINI | TD — Reformasi 1998 membuka lebar pintu politik bagi siapa pun, termasuk kalangan selebritas. Demokrasi memberi ruang bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang, untuk maju sebagai pemimpin. Artis pun melihat peluang ini dan memanfaatkan popularitas sebagai modal politik.
Contoh suksesnya cukup banyak. Rano Karno membangun citra politik lewat karakter “Si Doel” yang sederhana dan jujur. Dede Yusuf tampil sebagai tokoh muda yang energik, sementara Desy Ratnasari dikenal santun dan berpendidikan. Citra-citra ini membantu mereka mendapat kepercayaan publik tanpa perlu banyak bicara tentang visi atau program.
Dalam politik modern Indonesia, popularitas sering kali lebih kuat dari ideologi partai. Banyak pemilih lebih mengenal figur yang mereka lihat di layar kaca daripada politisi yang muncul hanya saat kampanye. Akibatnya, politik berubah menjadi ajang pencitraan, bukan pertarungan gagasan.
Media dan Logika Politainment: Politik yang Menghibur
Media massa memiliki peran besar dalam mengubah wajah politik menjadi hiburan. Sejak awal 2000-an, program infotainment kerap menampilkan kehidupan pribadi artis yang masuk ke dunia politik. Politik pun menjadi bagian dari narasi gosip selebritas.
Fenomena ini dikenal sebagai “politainment” — gabungan dari politics dan entertainment. Seperti dijelaskan Heryanto (2018), politik di Indonesia telah menjadi “sinetron publik”, di mana politisi tampil sebagai karakter yang harus menarik simpati penonton.
Kini, media sosial memperluas panggung itu. Melalui Instagram, TikTok, dan YouTube, politisi bisa membangun “panggung pribadi” dengan menampilkan keseharian, kegiatan sosial, atau momen keluarga. Publik mengenal tokoh secara emosional, tapi sering kali tidak memahami isi pikirannya atau kinerjanya. Politik menjadi tontonan yang memikat, namun dangkal.
Dari Substansi ke Sensasi: Politik Emosi di Era Digital
1. Dominasi Citra dan Slogan Kosong
Kampanye politik kini mirip dengan iklan produk. Slogan seperti “Perubahan Sekarang” atau “Untuk Rakyat” mudah diingat, tapi sering tanpa makna konkret. Artis-politisi yang terbiasa tampil di depan kamera memahami bahwa gestur dan gaya bicara lebih efektif daripada argumentasi. Akibatnya, kampanye berubah menjadi pertunjukan visual, bukan debat ide.
2. Politik Emosi dan Cerita Pribadi
Banyak artis-politisi membangun narasi personal tentang perjuangan hidup atau masa kecil yang sulit untuk menarik simpati publik. Strategi ini dikenal sebagai emotional branding, yaitu membangun kedekatan emosional dengan pemilih.
Namun, pendekatan ini berisiko mengurangi nalar kritis masyarakat. Survei Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (2020) menunjukkan bahwa 70 persen pemilih muda memilih calon berdasarkan “kesukaan pribadi”, bukan karena memahami programnya. Politik pun beralih dari ruang gagasan menjadi ajang ekspresi emosional.
Dampak bagi Demokrasi dan Komunikasi Politik
1. Pendangkalan Isu dan Hilangnya Kesadaran Kritis
Ketika politik menjadi hiburan, masyarakat kehilangan minat pada isu substansial. Debat politik di televisi lebih sering berubah menjadi ajang sindiran dan drama, sementara media sosial dipenuhi meme politik tanpa konteks kebijakan. Publik menjadi penonton pasif — terhibur, tapi tidak sadar bahwa kebijakan publik seharusnya menjadi urusan mereka juga.
2. Popularitas Menggeser Akuntabilitas
Politisi populer sering kebal kritik karena memiliki basis penggemar yang fanatik. Setiap kritik dianggap serangan pribadi, bukan evaluasi kebijakan. Media pun memperkuat situasi ini dengan memberitakan gaya hidup dan penampilan, bukan kinerja. Akibatnya, politik kehilangan maknanya sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti yang diingatkan Heryanto (2018) dalam konsep “politik layar”.
Menjaga Demokrasi dari Politik Hiburan
1. Literasi Politik untuk Publik Kritis
Cara paling efektif untuk menghadapi politik hiburan adalah meningkatkan literasi politik masyarakat. Publik perlu belajar membedakan antara citra dan kinerja, antara janji dan tanggung jawab. Diskusi kampus, kelas kewarganegaraan, hingga analisis media sosial bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran politik kritis.
2. Etika Media dan Peran Jurnalis
Media memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan politik ke substansi. Pemberitaan seharusnya fokus pada kebijakan, bukan gosip. Jurnalis harus menjadi penjaga nalar publik, bukan sekadar penyambung suara elite politik.
3. Partisipasi Publik yang Bermakna
Partisipasi politik tidak boleh berhenti di komentar media sosial. Warga harus aktif mengawasi kebijakan, mengikuti forum publik, dan berani menyampaikan kritik. Demokrasi yang hidup bergantung pada partisipasi rakyat yang sadar dan berani bersuara.
Kesimpulan: Politik Bukan Sekadar Panggung, tapi Pengabdian
Fenomena artis menjadi politisi adalah cerminan perubahan besar dalam budaya politik Indonesia. Demokrasi yang terbuka memang memberi ruang luas, tetapi juga membawa risiko politik yang bergantung pada citra dan popularitas.
Popularitas bisa menjadi modal positif untuk menjangkau masyarakat, namun tanpa integritas dan kapasitas, politik kehilangan maknanya. Demokrasi yang sehat memerlukan pemimpin yang bekerja nyata dan masyarakat yang berpikir kritis.
Media pun memegang peran penting sebagai penjaga keseimbangan informasi. Politik seharusnya bukan pertunjukan untuk menghibur, melainkan ruang pengabdian bagi kepentingan rakyat.
Penulis: Yusuf
Mahasiswa Semester 1, Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UNTIRTA. (*)