Amnesti dan Abolisi: Antara Kemanusiaan dan Politik Kekuasaan
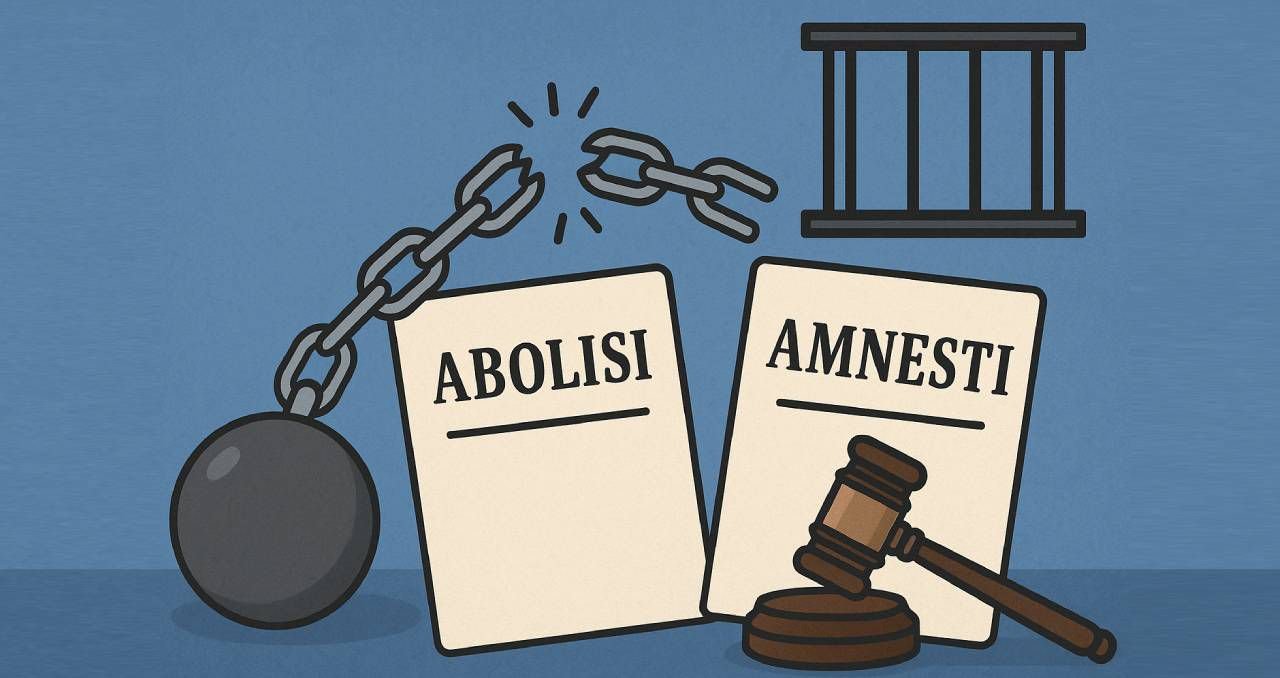 Sumber Gambar: Pixabay
Sumber Gambar: PixabayOPINI | TD — Beberapa waktu lalu, media ramai membahas isu politik hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peristiwa ini memantik refleksi penulis mengenai amnesti dan abolisi, dua konsep hukum yang kerap muncul dalam dinamika politik Indonesia.
Secara definisi, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan semua akibat hukum dari tindak pidana tertentu, biasanya bersifat politik, yang membuat konsekuensi hukumnya seolah tidak pernah ada. Sementara abolisi berarti penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang dalam penyelidikan, penyidikan, atau persidangan. Meski pelaku tidak diproses lebih lanjut, hal ini tidak serta-merta menegaskan bahwa ia bebas dari kesalahan.
Dari perspektif hukum murni, amnesti dan abolisi adalah instrumen legal. Namun, dalam praktik politik Indonesia, penulis melihat keduanya lebih dari sekadar hukum; mereka sering digunakan sebagai strategi politik untuk menjaga stabilitas negara. Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi disalahgunakan, jika hanya dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan elit politik tertentu. Bila hal itu terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan runtuh.
Sejarah Amnesti dan Abolisi di Indonesia
Amnesti dan abolisi bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, mekanisme ini telah digunakan dalam berbagai konteks politik hukum. Namun, pertanyaan yang muncul selalu sama: Apakah kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan bangsa atau hanya untuk melindungi pihak tertentu? Pengalaman sejarah menunjukkan, tanpa transparansi dan alasan yang jelas, publik mudah menilai bahwa hukum menjadi instrumen politik.
Perspektif Global
Negara lain juga menggunakan mekanisme serupa. Contohnya, Afrika Selatan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memberi amnesti kepada pelaku pelanggaran HAM era apartheid, dengan syarat mereka mengakui perbuatannya secara terbuka. Contoh ini menegaskan bahwa amnesti dan abolisi dapat berhasil jika dijalankan dengan keterbukaan dan tanggung jawab moral.
Pro dan Kontra
Argumentasi mendukung amnesti dan abolisi:
1. Menjaga stabilitas nasional: Mekanisme ini dapat menjadi alat untuk meredam konflik dan menjaga keamanan negara.
2. Menunjukkan fleksibilitas hukum: Hukum tidak hanya soal menghukum, tetapi juga tentang menyelesaikan masalah bangsa secara menyeluruh.
3. Dasar konstitusional kuat: Berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1954, presiden berhak menggunakan amnesti dan abolisi sebagai kebijakan hukum.
Argumentasi menentang amnesti dan abolisi:
1. Potensi politisasi hukum: Kebijakan ini bisa disalahgunakan untuk melindungi kelompok tertentu yang berkuasa, menimbulkan kesan hukum hanya alat politik sesaat.
2. Melemahkan sanksi hukum: Penghapusan hukuman dapat memberi pesan negatif bahwa pelanggaran hukum bisa dinegosiasikan melalui politik.
3. Mengabaikan keadilan bagi korban: Korban menjadi pihak yang dirugikan karena pelaku tidak menjalani hukuman yang semestinya.
Pendekatan yang Ideal
Agar amnesti dan abolisi tidak menjadi alat politisasi, pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip:
- Membedakan kasus: Jangan gunakan untuk kasus serius seperti korupsi, terorisme, narkotika, atau pelanggaran HAM.
- Transparansi: Alasan pemberian amnesti atau abolisi harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kesimpulan
Amnesti dan abolisi dapat menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, tetapi jika tidak dijalankan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, alat hukum ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Pemerintah harus berhati-hati, memastikan politik hukum berpihak pada rakyat, dan menegakkan keadilan. Dengan begitu, amnesti dan abolisi tetap menjadi instrumen yang bermanfaat, bukan ancaman bagi hukum dan kepercayaan masyarakat.
Penulis: Dianti Elma Fitriyah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Sultan Ageng Tirtayasa. (*)










