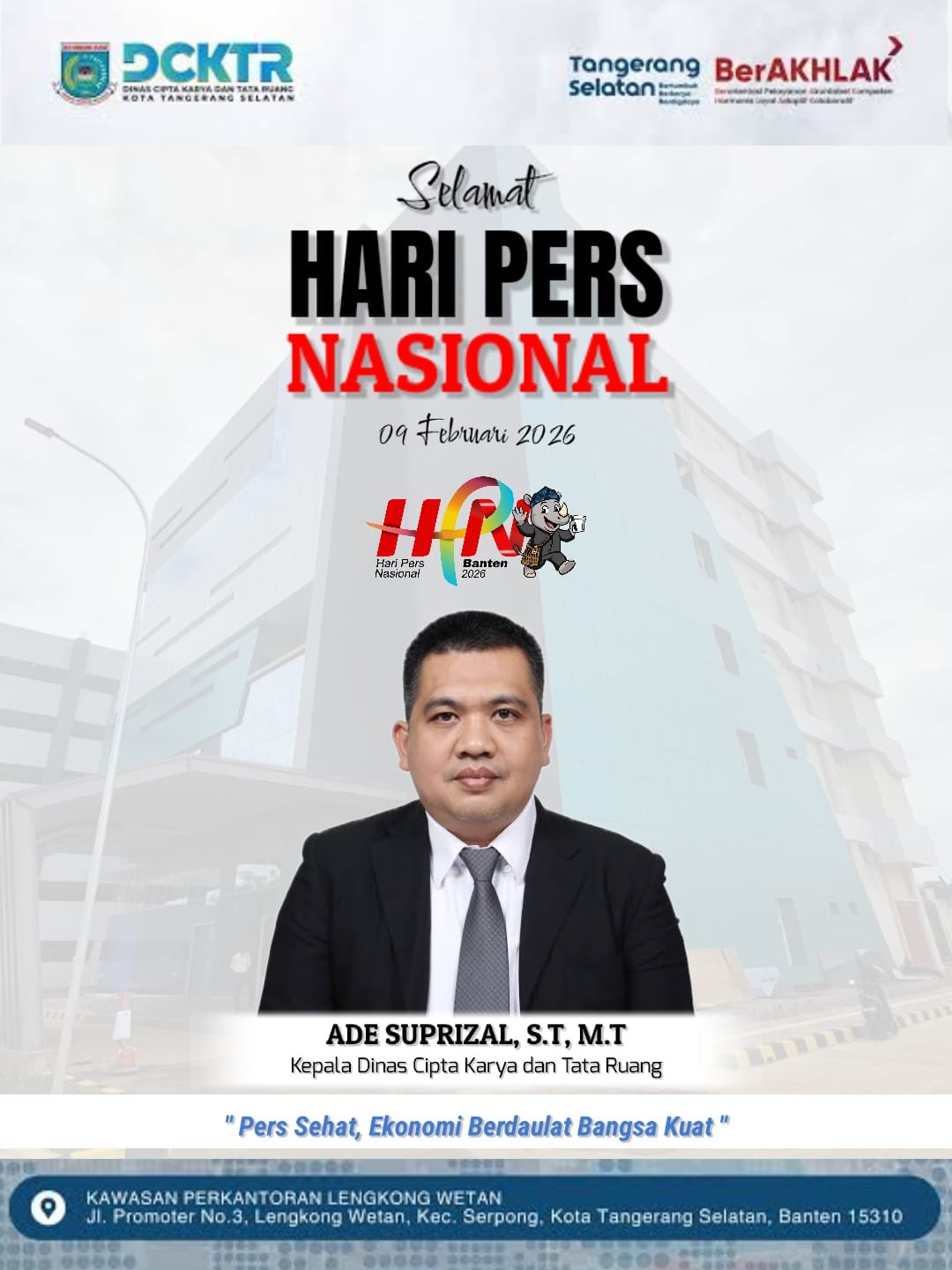Bahaya Flexing bagi Generasi Z: Konsumerisme, FOMO, dan Hilangnya Nilai Pancasila
 Namira Dara Soliha. (Foto: Dok. Pribadi)
Namira Dara Soliha. (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD — Dalam dua tahun terakhir, media sosial seolah berubah menjadi ruang pertarungan citra yang tak pernah tidur. Indonesia memang sedang menikmati masifnya transformasi digital, tetapi di balik manfaatnya, muncul masalah etik baru yang jauh lebih rumit daripada sekadar persoalan teknologi. Salah satunya adalah budaya flexing—kebiasaan memamerkan barang mewah, prestasi berlebihan, atau gaya hidup glamor untuk mendapatkan validasi publik.
Bagi sebagian orang, flexing mungkin terlihat sebagai hiburan visual. Namun bagi generasi Z, fenomena ini telah menjadi semacam kompetisi simbolik yang menentukan harga diri, struktur pertemanan, hingga identitas pribadi. Masalahnya, kompetisi ini tidak dibangun dari nilai, melainkan dari ilusi.
Kasus Mario Dandy Satriyo menjadi titik ekstrem yang membuka mata publik. Flexing bukan lagi sekadar konten “pamer”, tetapi bisa berubah menjadi kekerasan simbolik dan bahkan fisik. Mobil Rubicon, motor gede, fasilitas hidup mewah—semua itu bukan hanya pajangan di Instagram, tetapi simbol dominasi yang kemudian dibawa ke dunia nyata.
Kasus tersebut mengungkap satu hal: ketika flexing dinormalisasi, moralitas ikut bergeser. Kekayaan dianggap legitimasi kekuasaan. Empati memudar. Integritas dikorbankan demi citra. Dan sayangnya, di tengah hiruk-pikuk budaya pamer, nilai-nilai Pancasila justru semakin kehilangan tempat.
Flexing sebagai Krisis Identitas Generasi Z
Generasi Z adalah generasi pertama yang tumbuh bersamaan dengan TikTok, Instagram, dan YouTube. Sejak usia sekolah dasar, mereka sudah terbiasa memperkenalkan diri lewat unggahan visual. Tidak heran, identitas dan rasa percaya diri mereka sangat ditentukan oleh bagaimana orang lain menanggapi apa yang mereka posting.
Di sinilah flexing menemukan momentumnya.
Bagi banyak remaja, hidup “seharusnya” terlihat estetik, glamor, dan menarik di kamera. Hidup sederhana dianggap tidak cukup. Akibatnya, banyak yang memaksakan citra yang sebenarnya tidak sejalan dengan realitas hidup mereka. Ada yang meminjam barang mewah, memotret di tempat mahal, hingga menyusun narasi palsu demi terlihat “setara” dengan tren digital.
Tekanan psikologis ini memunculkan tiga dampak utama:
1. Rasa kurang yang tak berkesudahan
Remaja terus membandingkan hidupnya dengan unggahan orang lain, padahal banyak dari unggahan itu sebenarnya rekayasa. Namun perbandingan yang tidak sehat ini tetap terasa nyata di benak mereka.
2. FOMO sebagai kecemasan sosial baru
Ketakutan dianggap “tidak update” membuat remaja membeli barang-barang di luar kemampuan, hanya agar tidak dianggap tertinggal oleh teman-temannya.
3. Konsumerisme impulsif
Belanja dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi demi konten. Cicilan, paylater, hingga pinjaman sengaja diambil untuk membangun citra di media sosial.
Kasus Mario Dandy adalah versi ekstrem dari krisis identitas ini. Ketika identitas dibangun dari simbol harta, bukan nilai moral, maka kekerasan tidak lagi sulit muncul. Flexing bukan hanya soal gaya hidup—ia adalah gejala dari identitas rapuh yang dibangun hampir sepenuhnya dari ilusi.
Pancasila: Hadir dalam Buku, Hilang dalam Praktik Digital
Fenomena flexing memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Pancasila makin tersingkir dari kehidupan generasi muda, terutama di ruang digital.
Sila Pertama: Ketakwaan dan kesederhanaan
Nilai kesederhanaan dan integritas tergeser karena budaya pamer menempatkan harta sebagai tolok ukur martabat.
Sila Kedua: Kemanusiaan
Flexing menciptakan ketimpangan simbolik. Mereka yang “miskin secara visual” rentan dihina, direndahkan, atau dianggap tidak layak masuk circle tertentu.
Sila Ketiga: Persatuan
Alih-alih menyatukan, media sosial kini memperlebar jurang sosial digital antara yang bisa menunjukkan kemewahan dan yang tidak.
Sila Keempat: Kebijaksanaan
Keputusan impulsif demi pencitraan menunjukkan bahwa remaja kini lebih mengikuti tren daripada pertimbangan etis atau rasional.
Sila Kelima: Keadilan sosial
Flexing memperburuk ketidakadilan simbolik. Mereka yang tidak mampu mengikuti standar glamor sering merasa inferior secara sosial.
Dengan kata lain, budaya flexing adalah bukti nyata bahwa Pancasila masih dipelajari, tetapi belum benar-benar dihidupkan dalam keseharian generasi digital.
Mengapa Pancasila Penting untuk Mengatasi Krisis Ini?
Masalah flexing bukan hanya soal belanja impulsif atau citra palsu, tetapi tentang hilangnya orientasi moral. Maka, pendidikan Pancasila sebenarnya masih sangat relevan. Sayangnya, di sekolah ia lebih sering diajarkan sebagai hafalan daripada refleksi hidup.
Padahal, jika diajarkan melalui pendekatan yang kontekstual—misalnya lewat analisis konten viral, kasus nyata, atau dinamika media sosial—Pancasila dapat menjadi kompas moral yang menyadarkan remaja bahwa nilai diri tidak berasal dari barang yang dipamerkan, tetapi dari karakter, empati, dan kontribusi sosial.
Rekomendasi Solusi Konkret
1. Kampanye Anti-Flexing dan Literasi Digital Kreatif
Konten edukatif dari kreator muda dapat menantang narasi glamor dengan menunjukkan nilai kesederhanaan, keaslian, dan potret hidup yang lebih manusiawi.
2. Pendidikan Pancasila Berbasis Studi Kasus
Guru perlu menggunakan fenomena aktual seperti kasus Mario Dandy untuk membangun diskusi moral. Metode ini lebih relevan bagi remaja.
3. Literasi Keuangan Remaja
Agar remaja tidak terjerat gaya hidup palsu yang memiskinkan, mereka perlu mempelajari dasar keuangan, risiko utang, dan pengelolaan prioritas kebutuhan.
4. Aktivitas Komunitas yang Membentuk Interaksi Nyata
Seni, olahraga, atau kegiatan sosial dapat mengurangi ketergantungan pada validasi digital.
5. Pendampingan Psikologis di Sekolah
Konselor harus tersedia untuk membantu remaja menghadapi kecemasan identitas, FOMO, dan tekanan sosial akibat budaya flexing.
Kesimpulan
Fenomena flexing di kalangan generasi Z bukan sekadar tren media sosial, tetapi krisis moral yang semakin mengakar. Kasus Mario Dandy hanyalah puncak gunung es dari budaya pamer yang merusak empati, integritas, dan kesadaran sosial.
Di tengah budaya digital yang semakin individualistik dan konsumtif, nilai-nilai Pancasila menjadi terasa asing, padahal justru inilah fondasi moral yang diperlukan untuk menghadapi era penuh ilusi ini. Revitalisasi Pancasila harus dilakukan secara kreatif dan kontekstual, terutama melalui pendidikan yang dekat dengan pengalaman remaja.
Jika generasi muda bisa kembali memaknai Pancasila, mereka tidak hanya akan terhindar dari jebakan gaya hidup bohongan, tetapi juga mampu membangun identitas yang lebih kuat, autentik, dan bertanggung jawab—baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
Penulis: Namira Dara Soliha
Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)