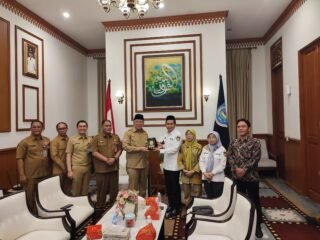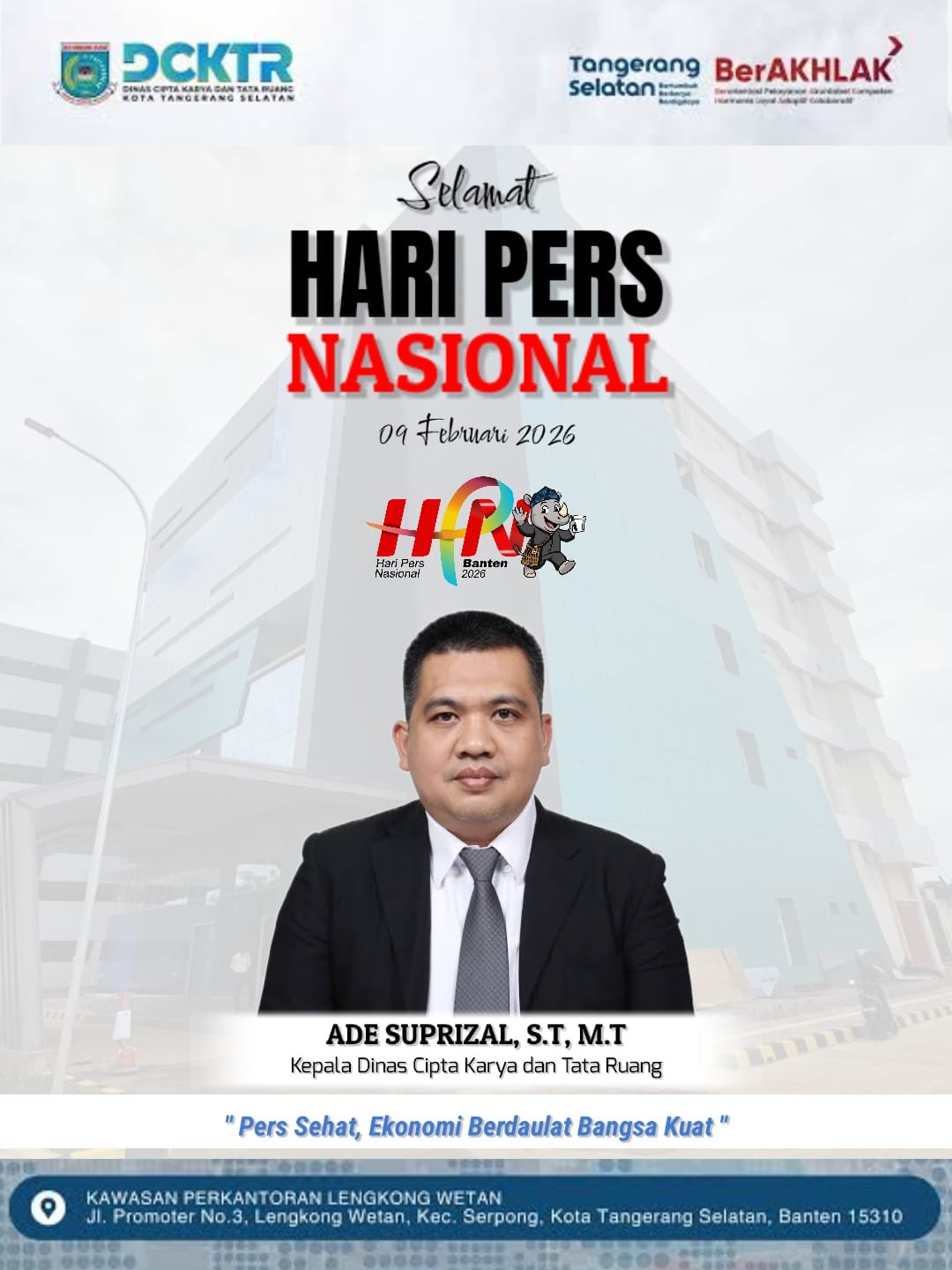Dampak Gagalnya Pendidikan Karakter terhadap Implementasi Sila Kelima di Era Digital
 Najla Al-Nadiah Ekawanti. (Foto: Dok. Pribadi)
Najla Al-Nadiah Ekawanti. (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD — Fenomena TikTok Live Gift belakangan ini menjadi cermin paling terang dari perubahan cara masyarakat memaknai keadilan sosial di era digital. Di balik hiburan dan interaksi real-time yang tampak spontan, kita sesungguhnya sedang menyaksikan gejala sosial yang jauh lebih dalam: bagaimana sebagian kreator rela merendahkan diri demi mendapatkan gift virtual yang nantinya dapat diuangkan. Alih-alih menjadi wadah kreatif bagi generasi muda, platform digital justru sering kali berubah menjadi arena eksploitasi, ketimpangan, dan hilangnya martabat manusia.
Fenomena ini sangat ironis bagi bangsa yang menjunjung tinggi nilai Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Apa yang kita lihat hari ini menunjukkan bahwa implementasi nilai tersebut di ruang digital tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Masalahnya bukan semata soal fitur atau mekanisme TikTok. Masalah utamanya jauh lebih mendasar, yaitu gagalnya pendidikan karakter dalam menginternalisasi nilai empati, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia kepada generasi muda. Akibatnya, ruang digital tumbuh menjadi lahan subur bagi eksploitasi baru, ketidakadilan baru, serta cara-cara baru dalam merendahkan sesama demi popularitas dan keuntungan ekonomi.
Eksploitasi Kemiskinan sebagai Hiburan Digital
Tren “pengemis digital” menjadi contoh paling mencolok tentang bagaimana kemiskinan dapat berubah menjadi komoditas hiburan. Banyak kreator menampilkan kondisi rumah yang memprihatinkan, melakukan aksi ekstrem seperti berendam di selokan, menahan sakit, atau menari tanpa henti, demi memperoleh gift dari penonton. Bahkan, sebagian kreator dengan sengaja merancang konten keterpurukan agar memancing simpati—atau lebih tepatnya, memancing “uang”.
Fadhilah & Sutrisno (2022) menyebut fenomena ini sebagai eksploitasi simbolik, yaitu ketika kemiskinan tidak hanya dipertontonkan, tetapi dijadikan komoditas yang dapat dijual untuk keuntungan finansial. Di titik ini, gift bukan lagi simbol solidaritas atau bantuan, melainkan “harga tontonan”. Semakin menyedihkan sebuah konten, semakin besar kemungkinan kreator mendapatkan hadiah virtual.
Ini jelas bertentangan dengan nilai dasar Sila Kelima. Keadilan sosial menuntut penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, tanpa kecuali. Namun di ruang digital, martabat itu dijual murah. Kemiskinan yang seharusnya menjadi problem sosial malah dinormalisasi sebagai hiburan, sebagai panggung drama demi monetisasi.
Hierarki Baru: Relasi Kuasa antara Penonton dan Kreator
Salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari sistem gift adalah hadirnya relasi kuasa yang tidak sehat. Mekanisme gift menciptakan struktur sosial baru:
- Penonton yang memberi gift merasa memiliki kekuasaan.
- Kreator yang menerima gift merasa wajib menghibur, bahkan ketika diminta melakukan hal yang merendahkan.
Prasetyo & Ananda (2021) mencatat bahwa budaya digital yang kompetitif memperkuat relasi kuasa semacam ini, terutama bagi kreator dari ekonomi lemah. Penonton merasa berhak memerintah, mempermalukan, atau memberi tantangan ekstrem. Tak sedikit kreator yang akhirnya menuruti, karena itu adalah satu-satunya cara agar live mereka “ramai”.
Keadilan sosial seharusnya meletakkan manusia sebagai subjek yang sederajat. Namun di ruang digital, nilai kesetaraan itu hilang. Yang tersisa adalah hubungan transaksional yang timpang: siapa yang punya gift, dialah yang berkuasa; siapa yang membutuhkan gift, dialah yang tunduk.
Normalisasi Kekerasan Simbolik di Kolom Komentar
Ruang komentar dalam live streaming sering kali menjadi arena kekerasan verbal. Komentar seperti ejekan, hinaan, body shaming, bahkan serangan psikologis, muncul tanpa kendali. Karena interaksi berlangsung cepat dan tanpa tatap muka, pengguna merasa lebih bebas melakukan kekerasan simbolik.
Wibowo (2020) menyebut ini sebagai kekerasan simbolik digital—kekerasan yang dilakukan dengan bahasa, tetapi memiliki dampak nyata menghancurkan harga diri seseorang. Banyak kreator mengabaikan komentar kasar demi mempertahankan engagement, namun secara emosional mereka sering kali terpukul.
Jika kekerasan verbal dianggap wajar, bagaimana mungkin nilai keadilan sosial bisa tumbuh? Ketika sesama manusia tidak lagi saling menghormati, kita sedang kehilangan prasyarat moral dari Sila Kelima.
Ketidakadilan Algoritmik: Ketimpangan Baru di Era Digital
Ketidakadilan digital bukan hanya berasal dari penonton atau kreator. Sistem platform digital—yang kita sebut “algoritma”—turut memiliki peran besar dalam menciptakan ketimpangan baru.
Kreator besar mendapat eksposur lebih luas, sehingga lebih mudah memperoleh gift. Sementara kreator kecil harus bekerja jauh lebih keras untuk tampil di layar penonton.
Abrar & Setiawan (2022) menyebut kondisi ini sebagai ketidaksetaraan algoritmik, yaitu ketika sistem platform memperlebar jurang ekonomi antar-kreator. Bahkan pada level tertentu, algoritma dapat menciptakan ketimpangan yang tidak dapat dikontrol oleh pengguna.
Ketidakadilan ini menunjukkan bahwa Sila Kelima belum masuk ke kesadaran digital kita. Kita menjadi pengguna pasif tanpa kemampuan kritis membaca struktur ketidakadilan yang dibentuk teknologi. Padahal, keadilan sosial bukan hanya urusan manusia ke manusia, tetapi juga bagaimana sistem digital memengaruhi distribusi kesempatan, akses, dan keuntungan.
Akar Masalah: Pendidikan Karakter yang Berbasis Hafalan
Dari eksploitasi, relasi kuasa toksik, hingga kekerasan simbolik, semuanya memiliki akar yang sama: kegagalan pendidikan karakter.
Pendidikan karakter kita masih terlalu fokus pada hafalan, bukan pada penghayatan. Banyak generasi muda hafal Pancasila, tetapi tidak menghayati Pancasila. Mereka tahu “Keadilan Sosial” sebagai kalimat, tetapi tidak melihat relevansinya dengan dunia TikTok atau Instagram.
Padahal, nilai moral tidak bekerja hanya di atas kertas. Nilai moral bekerja pada “pilihan kecil sehari-hari”, termasuk pilihan ketika menonton atau membuat konten digital.
Putri & Abdullah (2022) menegaskan bahwa regulasi digital tidak akan efektif tanpa fondasi etika yang kuat. Mau seketat apa pun UU ITE atau sistem moderasi, jika empati dan kesadaran moral tidak hadir, ketidakadilan digital akan terus berulang.
Mengapa Generasi Z Perlu Belajar Pancasila dengan Cara Baru?
Generasi Z tumbuh dalam dunia digital. Ruang itu bukan sekadar tempat interaksi, tetapi ruang pembentukan karakter. Ketika mereka disuguhi konten sensasional, eksploitasi gift, atau drama kemiskinan setiap hari, nilai yang terinternalisasi pun ikut terbentuk: nilai materialistis, pragmatis, dan kompetitif.
Lestari (2022) menunjukkan bahwa paparan konten ekstrem secara terus-menerus menurunkan sensitivitas moral. Ketika kemiskinan dianggap lucu, ketika penghinaan dianggap hiburan, ketika eksploitasi dianggap ‘trik kreator’, maka nilai keadilan sosial makin sulit tumbuh.
Maka belajar Pancasila bukan sekadar tugas formal di kelas, tetapi menjadi kebutuhan moral untuk hidup manusiawi di dunia digital.
Solusi Konkret: Cara Gen Z Menghidupkan Sila Kelima di Ruang Digital
1. Membuat dan Menyebarkan Konten Digital Beretika
Konten bermutu, edukatif, dan tidak eksploitatif dapat menandingi budaya gift yang merendahkan manusia. Kampanye seperti “Stop Eksploitasi Gift”, video edukasi tentang empati, atau konten yang mengangkat kisah perjuangan UMKM, dapat memperluas ruang positif di media sosial.
2. Membangun Komunitas Digital Berbasis Solidaritas
Komunitas seperti Digital Justice Movement dapat menjadi wadah untuk saling belajar, berdialog, dan mendukung korban kekerasan simbolik.
Suryani (2023) menunjukkan bahwa dialog nilai secara teratur terbukti mampu meningkatkan toleransi dan empati antar-pengguna muda.
3. Penerapan Pembelajaran Pancasila Berbasis Proyek
Alih-alih menghafal, siswa dapat diajak membuat proyek nyata: kampanye anti-eksploitasi digital, simulasi ketimpangan algoritmik, atau platform donasi berbasis skill. Pendekatan berbasis proyek menanamkan empati secara langsung, bukan sekadar teori.
4. Menjadi Konsumen Digital yang Etis
Tidak mendukung konten merendahkan, memberi gift secara etis, dan memilih mendukung kreator kecil adalah tindakan sederhana namun berdampak besar.
Penutup
Fenomena TikTok Live Gift hanyalah satu dari banyak tantangan moral di era digital. Ia membuka mata kita bahwa Sila Kelima tidak sedang hidup subur di ruang digital. Ketika kemiskinan menjadi konten hiburan, ketika martabat manusia ditukar dengan gift virtual, ketika kekerasan simbolik dianggap hal biasa, kita harus mengakui bahwa pendidikan karakter belum berhasil menyentuh hati generasi muda.
Karena itu, Pancasila harus kembali dipahami sebagai nilai hidup, bukan sekadar hafalan dalam upacara. Jika generasi muda mampu menghidupkan nilai empati, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam interaksi digital, maka era digital dapat menjadi ruang kemanusiaan yang adil dan beradab—bukan sekadar panggung hiburan yang mengorbankan martabat manusia.
Penulis: Najla Al-Nadiah Ekawanti
Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)