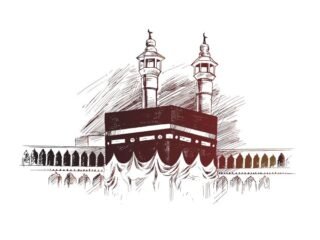Subsidi BBM dalam RAPBN 2025: Antara Kesejahteraan Rakyat dan Beban Fiskal Negara
 Alya Tri Paudiyah, Mahasiswa Semester 1, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA). (Foto: Dok. Pribadi)
Alya Tri Paudiyah, Mahasiswa Semester 1, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA). (Foto: Dok. Pribadi)OPINI | TD — Perdebatan tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM) selalu mengemuka setiap kali RAPBN dibahas. Dalam RAPBN 2025, pemerintah kembali mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk subsidi energi, termasuk BBM. Namun pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah subsidi ini benar-benar mencerminkan keberpihakan pada rakyat miskin, atau justru hanya menjadi kebijakan populis yang membebani fiskal negara?
Menurut penulis, dilema subsidi BBM adalah gambaran nyata dari pertarungan antara kepentingan ekonomi dan politik. Di satu sisi, harga BBM yang stabil memang penting untuk menjaga daya beli dan menahan inflasi. Namun, di sisi lain, anggaran subsidi yang sangat besar berisiko menyedot ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor strategis lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Subsidi BBM: Warisan Populisme yang Tidak Pernah Selesai
Sejak Orde Baru, subsidi BBM telah menjelma sebagai “instrumen politik murah meriah” bagi setiap rezim. Pemerintah mana pun selalu takut menyentuh harga BBM, sebab dampaknya bisa langsung dirasakan oleh rakyat dan berpotensi memicu gejolak sosial. Inilah yang membuat kebijakan ini sering kali lebih ditentukan oleh kalkulasi politik ketimbang pertimbangan rasional ekonomi.
Masalahnya, sebagian besar subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi. Sementara masyarakat miskin hanya mendapat porsi kecil dari subsidi tersebut. Jadi, apakah pantas uang rakyat ratusan triliun dialokasikan untuk memberi “diskon energi” kepada mereka yang sebenarnya mampu membayar harga keekonomian?
Legitimasi Kesejahteraan atau Sekadar Alat Politik?
Pemerintah baru 2025 tentu membutuhkan langkah konkret untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Menjaga harga BBM tetap rendah adalah cara tercepat meraih simpati publik. Tetapi legitimasi kesejahteraan tidak bisa dibangun di atas kebijakan populis jangka pendek.
Rakyat kini lebih kritis. Mereka tidak hanya menilai dari angka harga di pompa, tetapi juga dari keadilan distribusi, transparansi anggaran, dan arah kebijakan energi. Jika subsidi BBM ternyata lebih menguntungkan orang kaya, bukankah itu bentuk ketidakadilan baru? Bukankah hal itu justru akan menggerus legitimasi pemerintah sendiri?
Dilema Fiskal dan Jalan Tengah yang Mendesak
Bagi penulis, dilema subsidi BBM bisa dipadatkan dalam tiga persoalan pokok:
- Kebutuhan menjaga daya beli. Kenaikan harga BBM akan memicu inflasi dan memperberat beban masyarakat.
- Risiko beban fiskal. Anggaran subsidi yang terlalu besar mengurangi kemampuan negara membiayai program pembangunan lain.
- Kalkulasi politik. Pemerintah baru harus menunjukkan keberpihakan pada rakyat, sekaligus menjaga stabilitas sosial.
Ketiga kepentingan ini jelas saling bertabrakan. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa terus-menerus memilih jalan pintas populis. Jalan tengah yang paling rasional adalah memperketat subsidi agar tepat sasaran dan secara bertahap mengalihkan sebagian anggaran ke transisi energi berkelanjutan.
Dengan digitalisasi data dan integrasi sistem kesejahteraan sosial, subsidi seharusnya bisa diarahkan langsung ke kantong rakyat miskin dalam bentuk bantuan tunai. Skema ini lebih adil daripada “diskon BBM” yang justru lebih banyak dikonsumsi oleh kelompok mampu.
Selain itu, pemerintah perlu berani mengurangi ketergantungan pada BBM dengan mendorong transportasi publik, kendaraan listrik, serta energi terbarukan. Jika tidak dimulai sekarang, subsidi BBM hanya akan menjadi lingkaran setan: membakar anggaran tanpa menyelesaikan masalah struktural.
Penutup
Persoalan subsidi BBM dalam RAPBN 2025 bukan sekadar soal harga energi, melainkan soal keberanian politik. Apakah pemerintah berani keluar dari jebakan populisme, atau tetap memilih jalan mudah dengan mengorbankan keberlanjutan fiskal?
Subsidi BBM memang penting untuk menjaga stabilitas sosial. Tetapi jika terus dikelola secara boros dan tidak tepat sasaran, ia hanya akan menjadi alat politik sesaat. Legitimasi kesejahteraan seharusnya dibangun melalui kebijakan yang adil, efisien, dan visioner—bukan sekadar dengan menjaga harga BBM tetap murah.
Pemerintah baru memiliki momentum untuk mengubah wajah kebijakan energi di Indonesia. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Subsidi BBM harus diarahkan menjadi instrumen transformasi, bukan jebakan populisme abadi.
Penulis: Alya Tri Paudiyah, Mahasiswa Semester 1, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA). (*)