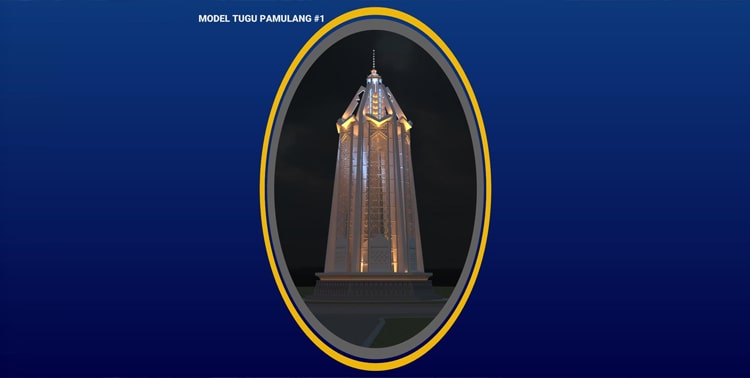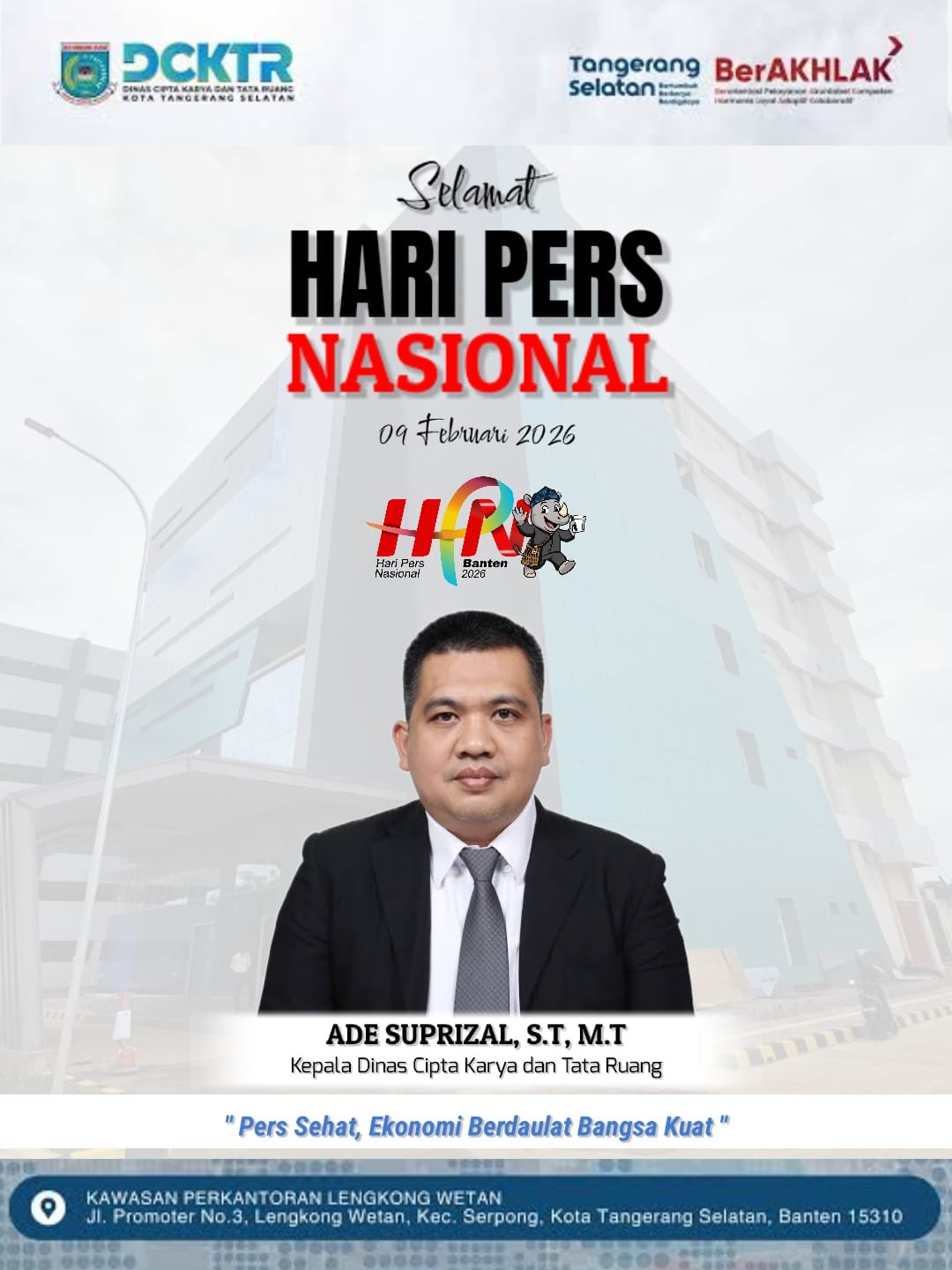Dilema Akut PPN 12 Persen: Solusi atau Beban?
 Kenaikan PPN 12% menjadi dilema antara kebutuhan fiskal negara dan beban masyarakat. Kebijakan ini perlu diimbangi dengan perlindungan sosial dan transparansi pajak agar adil dan diterima publik. (Foto: Ist)
Kenaikan PPN 12% menjadi dilema antara kebutuhan fiskal negara dan beban masyarakat. Kebijakan ini perlu diimbangi dengan perlindungan sosial dan transparansi pajak agar adil dan diterima publik. (Foto: Ist)OPIN| | TD — Kebijakan perpajakan selalu menjadi isu sensitif dalam kehidupan bernegara, karena menyangkut keseimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan beban ekonomi masyarakat. Pada tahun 2025, Indonesia kembali dihadapkan pada kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Kebijakan ini menjadi sorotan karena bertepatan dengan fase pemulihan ekonomi pasca pandemi serta dinamika politik nasional. Pemerintah menilai kenaikan PPN penting untuk memperkuat penerimaan negara, sementara masyarakat justru khawatir kebijakan tersebut menambah beban hidup.
Dengan demikian, PPN 12% menjadi sebuah “dilema akut”: di satu sisi, negara membutuhkan sumber penerimaan yang stabil untuk pembangunan dan program sosial; di sisi lain, masyarakat menghendaki kebijakan fiskal yang lebih adil dan tidak menekan daya beli. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dianalisis secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan politik.
Konteks Kebijakan PPN di Indonesia
Sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1984, tarif PPN di Indonesia bertahan lama di angka 10%. Stabilitas ini memberi kepastian bagi dunia usaha sekaligus menjaga harga tetap terkendali bagi masyarakat.
Namun, dinamika fiskal pasca pandemi Covid-19 membuat pemerintah perlu melakukan penyesuaian. Melalui UU HPP (2021), tarif PPN naik menjadi 11% pada April 2022, dan kembali dijadwalkan meningkat menjadi 12% pada 1 Januari 2025.
Kebijakan ini lahir dalam konteks defisit anggaran yang membesar akibat lonjakan belanja negara untuk kesehatan dan bantuan sosial, sementara penerimaan pajak tidak cukup menutup kebutuhan tersebut. PPN dipilih karena basis penerapannya luas dan relatif mudah dipungut, meski berisiko menimbulkan dampak politik dan sosial yang signifikan.
Alasan Pemerintah Menaikkan PPN
Bagi pemerintah, kenaikan PPN adalah strategi memperkuat kemandirian fiskal. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa Indonesia membutuhkan ruang fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, pemerintah berargumen bahwa tarif PPN Indonesia masih tergolong moderat. Filipina, misalnya, telah lama memberlakukan PPN 12%, sementara rata-rata tarif di Eropa berkisar 15–20%.
Untuk meredam gejolak, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah barang dan jasa penting seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum dikecualikan dari PPN, sehingga rakyat kecil tidak terlalu terbebani. Dengan demikian, beban kenaikan lebih diarahkan pada kelompok dengan daya beli lebih tinggi.
Kritik dan Dampak Sosial Ekonomi
Meski memiliki dasar rasional, kebijakan PPN 12% menuai banyak kritik. Masalah utama terletak pada sifat PPN yang regresif: tarifnya sama bagi semua orang, tanpa membedakan kemampuan ekonomi. Akibatnya, kelompok miskin justru menanggung beban lebih berat secara proporsional karena sebagian besar pendapatan mereka habis untuk konsumsi.
Kenaikan PPN juga berpotensi memicu inflasi. Harga barang dan jasa akan naik, sehingga konsumsi rumah tangga—motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia—bisa melemah. Hal ini berdampak serius pada UMKM yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Jika harga produk naik sementara konsumen menahan belanja, risiko kebangkrutan usaha kecil semakin tinggi.
Dari sisi sosial, kebijakan ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Kritik dari serikat buruh, LSM, hingga akademisi menegaskan bahwa kebijakan ini kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat yang baru pulih dari krisis.
Analisis Politik
Pajak tidak sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga keputusan politik yang sarat kepentingan. Kenaikan PPN 12% adalah ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan legitimasi politik dengan kebutuhan fiskal.
Bagi pemerintah, langkah ini mencerminkan keberanian melakukan reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, kebijakan ini adalah bukti lemahnya keberpihakan pada rakyat kecil. Respon keras dari oposisi maupun masyarakat sipil menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan memengaruhi stabilitas politik, terutama menjelang momentum politik penting.
Dengan demikian, PPN 12% tidak hanya soal angka, tetapi juga soal legitimasi kekuasaan di mata rakyat.
Perbandingan dengan Negara Lain
Untuk memperluas perspektif, perlu melihat kebijakan serupa di negara lain. Di banyak negara maju, tarif PPN/VAT berkisar 15–25%. Namun, daya beli masyarakat yang lebih tinggi serta sistem jaminan sosial yang kuat membuat kenaikan pajak tidak terlalu membebani.
Indonesia memang masih dalam kategori “moderat” dengan tarif 12%. Tetapi, tanpa perlindungan sosial yang memadai, dampaknya bisa lebih berat dibandingkan negara-negara tersebut. Misalnya, di Eropa, PPN 20% diimbangi dengan pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan jaminan sosial yang komprehensif.
Karena itu, kenaikan PPN di Indonesia sebaiknya diiringi peningkatan layanan publik, agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan.
Kesimpulan dan Solusi
Dilema PPN 12% berakar pada pertentangan antara kebutuhan fiskal negara dan beban masyarakat. Dari sisi pemerintah, kebijakan ini adalah langkah logis untuk memperkuat APBN. Namun dari sisi masyarakat, kenaikan ini dirasakan sebagai tambahan beban, terutama bagi kelompok rentan.
Untuk meredam dampak negatif, pemerintah perlu memastikan adanya kompensasi yang jelas: memperkuat bantuan sosial, subsidi pangan, serta memberikan insentif bagi UMKM. Transparansi penggunaan pajak juga mutlak diperlukan agar publik yakin setiap rupiah yang dibayarkan kembali dalam bentuk layanan publik berkualitas.
Dengan demikian, PPN 12% tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kontrak sosial antara negara dan rakyat. Pada akhirnya, kebijakan pajak hanya akan diterima bila masyarakat merasakan manfaat langsung dari kontribusi yang mereka berikan.
Penulis: Abielle Daffa Ananda, Mahasiswa Semester 1, Pengantar Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA. (*)