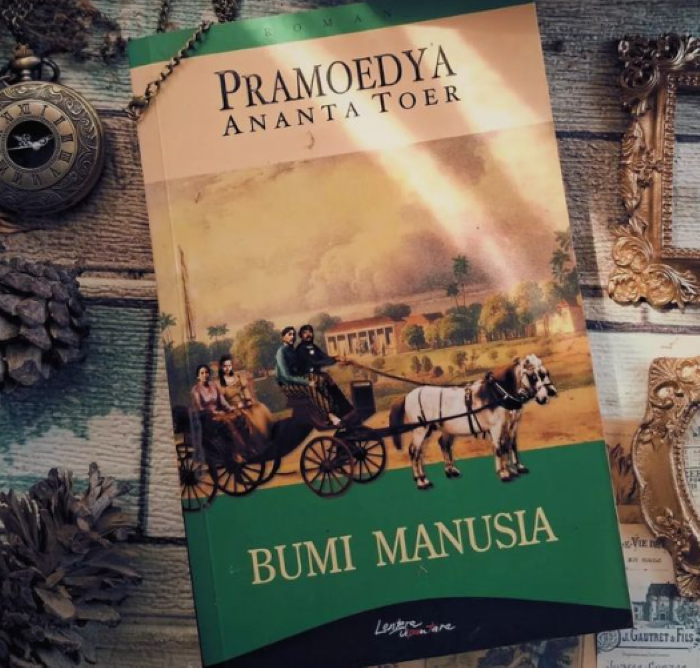Politik Identitas di Indonesia: Sejarah, Dampak, dan Tantangan Demokrasi
 Ilustrasi (Foto: Ist)
Ilustrasi (Foto: Ist)OPINI | TD — Politik identitas di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari perjalanan panjang demokrasi bangsa yang plural. Sejarah menunjukkan bahwa politik berbasis agama, etnis, ras, dan budaya selalu hadir dalam dinamika kebangsaan. Namun, praktik ini menghadirkan paradoks: di satu sisi mampu memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, tetapi di sisi lain berpotensi merusak persatuan dan kohesi sosial.
Sejarah Politik Identitas di Indonesia
Politik identitas muncul seiring keberagaman masyarakat Indonesia yang multikultural. Sejak masa kolonial, telah terbentuk dua arus besar pemikiran politik:
- Kelompok yang menghendaki pemisahan urusan spiritual dari administrasi negara.
- Kelompok yang mendorong institusionalisasi nilai-nilai Islam dalam pemerintahan.
Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto menekan ekspresi identitas partikular dengan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan homogenisasi ideologi tersebut membatasi ruang politik identitas selama lebih dari tiga dekade. Fakta ini menunjukkan bahwa politik identitas senantiasa menjadi bagian dari realitas sosial dan politik Indonesia.
Dampak Negatif Politik Identitas
- Memicu polarisasi sosial dan konflik horizontal.
- Melahirkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
- Menghasilkan kebijakan yang tidak adil bagi kelompok tertentu.
- Mengikis rasa kebersamaan dan kebanggaan nasional akibat penekanan pada perbedaan.
Dampak Positif Politik Identitas
Meski rawan konflik, politik identitas juga memiliki sisi konstruktif:
- Menjadi sarana perjuangan kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan penganut agama minoritas.
- Mengangkat isu-isu marginal ke dalam agenda kebijakan publik.
- Memperkuat solidaritas kelompok dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Contoh yang menonjol adalah Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno meraih kemenangan setelah mobilisasi politik identitas berbasis agama melalui Aksi 212.
Peran Media dalam Politik Identitas
Media, khususnya media sosial, memainkan peran sentral dalam menguatkan politik identitas. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok telah menjadi ruang kontestasi politik yang masif. Namun, media juga dituntut untuk:
– Menyajikan informasi yang berimbang.
– Menghindari pemberitaan provokatif.
– Mendorong dialog lintas kelompok untuk membangun pemahaman bersama.
Upaya Mengurangi Dampak Negatif Politik Identitas
- Memperkuat sistem politik yang melarang praktik diskriminatif.
- Mengembangkan pendidikan politik berbasis toleransi.
- Memberikan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas.
- Meneguhkan kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa.
Kesimpulan
Politik identitas di Indonesia adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Ia hadir sebagai bagian dari keberagaman bangsa, sekaligus tantangan bagi persatuan nasional. Politik identitas dapat menjadi perekat solidaritas, namun juga bisa menjadi sumber perpecahan. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana bangsa ini mampu mengelola politik identitas agar tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat, dengan menjadikan pluralitas sebagai kekuatan, bukan kelemahan.
Penulis: Nasrun Juniarta, mahasiswa semester 1 mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta. (*)