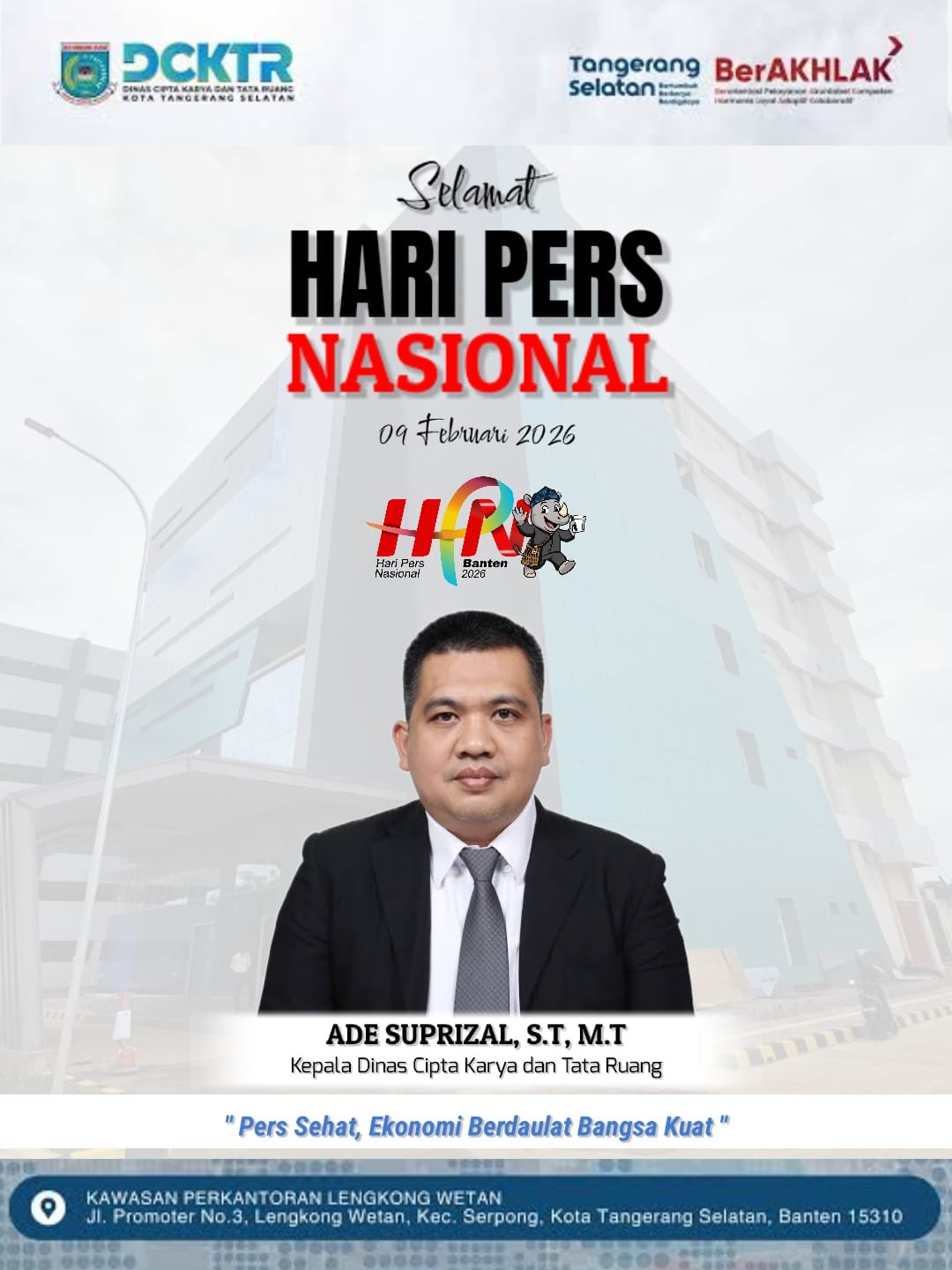Transformasi Figur: Dari Dunia Hiburan ke Dunia Pemerintahan
 Ilustrasi: Gambar direkayasa dengan kecerdasan buatan oleh Tangerangdaily.id
Ilustrasi: Gambar direkayasa dengan kecerdasan buatan oleh Tangerangdaily.idOPINI | TD — Dunia politik Indonesia terus mengalami pergeseran. Salah satu tren paling mencolok dalam dua dekade terakhir adalah masuknya figur publik dari dunia hiburan ke arena politik. Masyarakat sudah terbiasa melihat wajah-wajah artis terpampang di baliho kampanye atau tampil di panggung-panggung politik. Beberapa nama seperti Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, dan Eko Patrio bahkan berhasil terpilih menjadi anggota legislatif serta menjabat beberapa periode.
Yang dulu dianggap pengecualian kini seolah menjadi norma baru. Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat lebih dari 130 figur publik mendaftar sebagai calon legislatif, dan jumlah itu diperkirakan terus meningkat.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah ini tanda perluasan partisipasi demokrasi, atau justru cermin pragmatisme politik yang dangkal? Tidak bisa dipungkiri, partai politik kini cenderung memilih calon dengan elektabilitas tinggi ketimbang mereka yang berpengalaman atau berkapasitas ideologis. Popularitas sering kali lebih penting daripada pemahaman tentang legislasi maupun tata kelola pemerintahan.
Di sinilah muncul kekhawatiran publik. Figur publik memang memiliki modal besar—penggemar setia, sorotan media, serta kemampuan membangun citra personal. Namun, menjadi wakil rakyat tidak cukup hanya dengan modal “terkenal.” Posisi legislatif membutuhkan pemahaman mendalam tentang konstitusi, sistem hukum, hak-hak rakyat, serta mekanisme check and balance dalam demokrasi. Jika ini diabaikan, jabatan legislatif hanya akan menjadi perpanjangan panggung hiburan tanpa arah dan substansi.
Sebagian masyarakat menyambut baik tren ini karena dianggap bisa mendekatkan politik dengan publik, terutama generasi muda. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata: ketertarikan figur hiburan untuk masuk ke politik kerap dipicu oleh insentif ekonomi dan sosial, akses ke sumber daya, peningkatan status, hingga peluang karier yang lebih luas.
Kekuatan atau Ancaman?
Data terbaru menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia masih bermasalah. Indeks Persepsi Korupsi (Transparency International, 2023) menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, turun dari tahun sebelumnya, dengan peringkat 115 dari 180 negara. Sementara itu, Indeks Demokrasi versi The Economist Intelligence Unit (2023) menempatkan Indonesia pada kategori flawed democracy dengan skor 6,71.
Kedua data ini menegaskan bahwa kekuasaan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius: lemahnya akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Namun di sisi lain, rakyat kini semakin peka. Kritik di media sosial, diskusi publik, hingga gelombang demonstrasi mahasiswa menunjukkan bahwa publik sudah tidak mau sekadar menjadi penonton. Mereka semakin memahami bahwa kekuasaan yang baik bukanlah yang “kebal kritik,” melainkan yang terbuka terhadap koreksi.
Harapan tetap ada. Ketika kekuasaan dijalankan dengan visi dan integritas, hasilnya nyata: program bantuan sosial yang menyentuh kelompok rentan, pembangunan infrastruktur di daerah terisolasi, serta kemajuan digitalisasi layanan publik. Artinya, kekuasaan bisa membawa kebaikan besar—selama tidak dibajak oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
Demokrasi yang Terlalu Dangkal
Namun ada bahaya lain yang perlu diwaspadai. Demokrasi bisa kehilangan makna jika hanya bertumpu pada popularitas, pencitraan, dan sensitivitas berlebihan terhadap kritik. Saat ruang-ruang publik mulai menyempit, diskusi dibatasi, dan kritik dilabeli “radikal,” maka demokrasi hanya melahirkan warga patuh, bukan warga sadar.
Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki peran vital sebagai penjaga ruang berpikir kritis dan pelindung kebebasan sipil. Perubahan memang tidak cukup hanya lewat aksi jalanan, tetapi juga perlu dibangun dari dalam sistem—melalui forum legislatif mahasiswa, riset kebijakan, dan literasi politik.
Masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh siapa yang diberi mandat kekuasaan, dan bagaimana mandat itu digunakan. Bila popularitas lebih utama daripada kapasitas, dikhawatirkan parlemen hanya akan dipenuhi selebritas tanpa strategi, gagasan, maupun keberanian moral.
Demokrasi Bukan Panggung Hiburan
Jika tidak ada pembenahan serius, demokrasi Indonesia berisiko jatuh ke dalam jebakan formalisme: tampak demokratis di permukaan, tetapi otoriter dalam praktik. Kita bisa membayangkan parlemen yang sibuk membuat konten media sosial, tetapi abai terhadap perumusan undang-undang. Atau wakil rakyat yang lebih sering live streaming ketimbang menyuarakan aspirasi konstituennya.
Fenomena ini bukan sekadar bayangan pesimistis, melainkan cerminan kecil dari realitas politik hari ini. Demokrasi yang seharusnya menjadi arena pertarungan gagasan kini terancam berubah menjadi panggung pencitraan, di mana keberhasilan diukur dari sorotan kamera, bukan dari kualitas kebijakan.
Namun, demokrasi Indonesia belum mati. Ia hanya sedang “sakit”—melemah karena budaya politik yang lebih mengutamakan popularitas dibanding substansi. Tanda-tandanya terlihat dari partai politik yang lebih senang mengusung figur populer demi mendulang suara, serta media yang lebih fokus pada rating ketimbang wacana kritis.
Meski begitu, demokrasi tetap bisa dirawat dan dipulihkan. Harapan itu nyata jika rakyat berani bersuara dan mengambil peran aktif. Perbaikan bisa dimulai dengan:
- Partai politik berani mencalonkan tokoh muda yang berkompetensi, bukan sekadar populer.
- Media menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi dengan mengkritisi, bukan memoles citra.
- Rakyat membangun budaya politik rasional, bukan emosional.
- Generasi muda menyadari bahwa masa depan politik ditentukan oleh nilai dan perjuangan, bukan viralitas.
Penutup
Transformasi figur dari dunia hiburan ke dunia pemerintahan memang menarik untuk diamati. Dari satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi memberi kesempatan yang sama bagi siapa pun tanpa memandang latar belakang. Akan tetapi, yang lebih penting dari sekadar transformasi adalah memastikan bahwa mereka yang terpilih memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Popularitas mungkin bisa membuka pintu menuju kekuasaan, tetapi hanya kerja nyata yang dapat menjaga pintu itu tetap terbuka bagi publik. Demokrasi bukanlah panggung hiburan, melainkan ruang perjuangan di mana setiap keputusan berdampak pada jutaan rakyat.
Tanpa integritas, kapasitas, dan keberanian moral, demokrasi hanya akan terjebak dalam pertunjukan semu—menghibur sesaat, tetapi merusak dalam jangka panjang. Namun dengan kesadaran kolektif dan keberanian rakyat menuntut kualitas, demokrasi Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga tumbuh lebih sehat, lebih bermakna, dan lebih berpihak pada masa depan bangsa.
Penulis: Alisha Nuraeni, mahasiswa semester 1 mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)